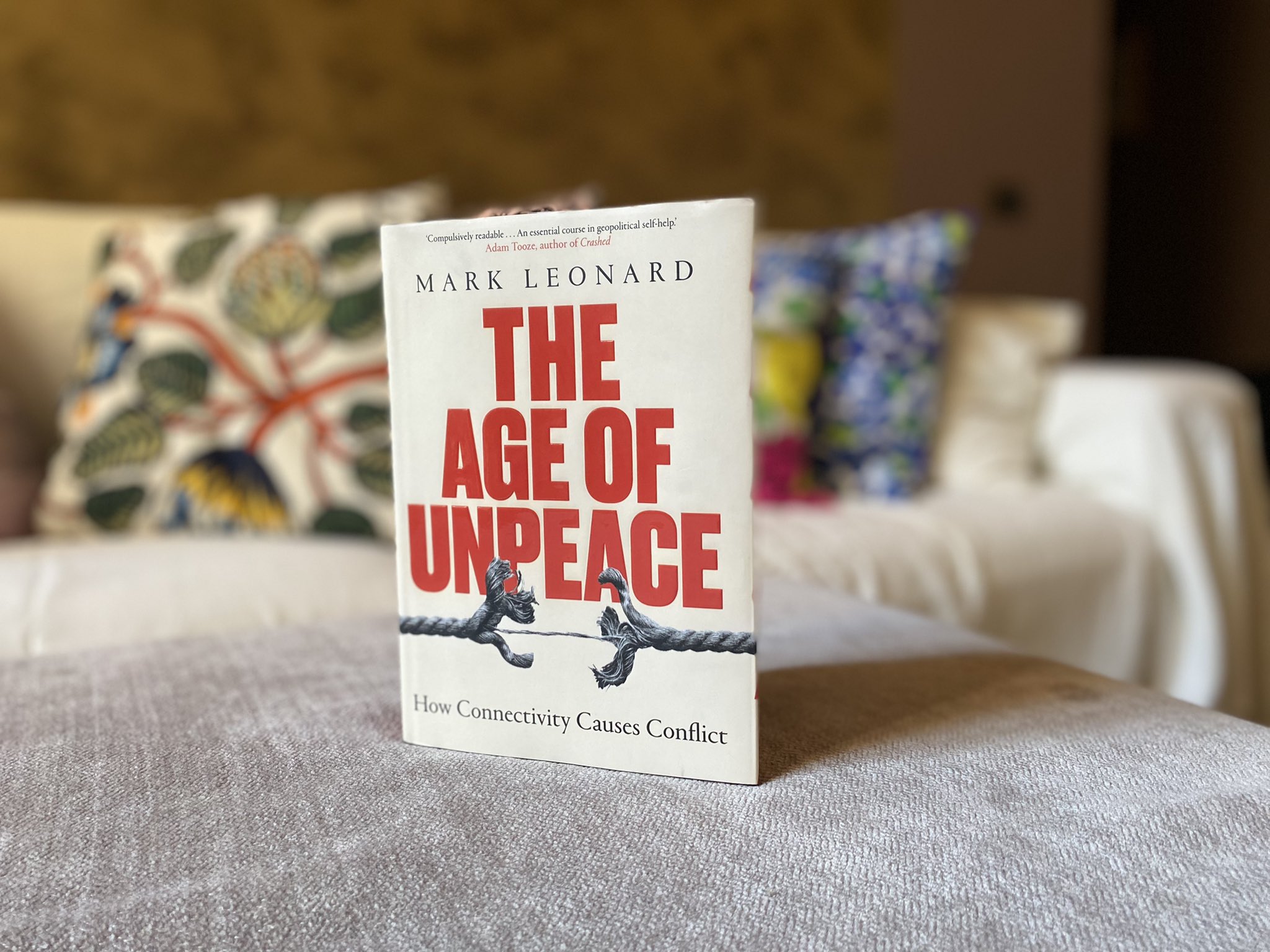
Konektivitas Penyebab Baru Konflik | Oleh: Virdika Rizky Utama
Virdika Rizky Utama*
| Judul | : | The Age of Unpeace |
| Penulis | : | Mark Leonard |
| Penerbit | : | Bantam Press |
| Tahun Terbit | : | Cetakan I (November, 2021) |
| Tebal | : | 229 halaman |
Abad ke-21 merupakan abad teknologi. Salah satu bukti nyata dari majunya teknologi adalah ditemukannya alat dan aplikasi untuk berkomunikasi secara langsung tanpa sekat dan tanpa perbedaan waktu. Mudahnya komunikasi dan dapat terhubung dengan berbagai manusia di penjuru bumi tentu dianggap sebagai sebuah berkah bagi hampir seluruh manusia dan negara, terutama untuk perdagangan dan perjalanan global.
Namun, disadari atau tidak, mudahnya komunikasi dan konektivitas ini juga memiliki dampak negatif, yaitu mudahnya terjadi konflik. Hal itu diungkapkan oleh Mark Leonard bahwa konektivitas itu sendiri memberi kesempatan manusia untuk berkelahi, alasan untuk berkompetisi, dan pengerahan senjata, terutama dalam konteks geopolitik global (Hlm.3).
Leonard berpendapat bahwa lonjakan konektivitas selama beberapa dekade terakhir perdagangan dan perjalanan internasional, internet, migrasi massal, lembaga antar pemerintah menyebabkan konflik daripada mencegahnya. Koneksi yang terus tumbuh ini telah dipersenjatai oleh negara-negara yang tak ingin mengalami kerugian sambil menghindari pembantaian perang. Penyebab utamanya, kata Leonard, adalah perdagangan global atau globalisasi ternyata tak menghadirkan kemakmuran. Perasaan iri tersebut yang dapat menggerakan negara bertindak agresif baik secara positif maupun negatif.
Bila negara tersebut memiliki modal sosial, budaya, dan dana yang cukup akan dapat mentranformasikan perasaan iri menjadi kompetisi melalui proses imitasi. Leonard mencontohkan China. Pada awal ke-20, ekonomi China masih jauh di bawah Amerika, tetapi China mengirimkan banyak pelajarnya ke AS untuk mempelajari teknologi dan ekonomi. Setelah mereka lulus, mereka membuat serangkaian teknologi yang mengimitasi produk AS. Sampai akhirnya, menjelang 2020 China dapat mengkudeta AS sebagai negara terkaya di dunia.
Majunya ekonomi China tersebut tentu tak disambut baik oleh AS. Mereka membuat serangkaian kebijakan untuk membendung laju pertumbuhan ekonomi China; melakukan proteksi, menaikkan tarif bea masuk barang China, dan intervensi kepada perusahaan teknologi untuk menarik dari China. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan prinsip globalisasi yang digagas oleh AS pasca perang dunia II. Maka tak mengherankan bila Leonard mengatakan, ini menandakan gejala tumbangnya globalisasi.
Sedangkan di pihak lain, China juga terus menaikkan permintaan dalam negerinya, sambil banyak mengekspor banyak produk sampai menguasai pasar (sistem sirkular ganda). Tak hanya itu, China juga mengaktifkan program Belt and Road Initiative (BRI) untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politiknya.
Xi ingin menjadikan China sebagai sebuah kekaisaran besar yang dapat menjadi pusat dunia. Hal itu dilandasi dari masa penghinaan yang dialami oleh bangsa China pada awal abad ke-20, saat itu kekaisaran China tak berdaya menghadapi negara-negara barat.
Tak seperti AS, yang mengekspor demokrasi bagi negara yang bersedia dibantu, China ingin menjadi mitra atau saudara dari negara-negara yang dibantu dengan prinsip co-existence atau hidup saling bergantung (Hlm.150-155). Namun, AS dan sebagian pengamat barat melihat hal itu hanya sebuah trick dari yang ingin dibentuk China, bukan saling ketergantungan, melainkan ketergantungan pada modal China.
Di tempat lain, Turki menggunakan ancaman pengiriman jutaan pengungsi dan migran ke Uni Eropa (UE) untuk mengekstrak bantuan miliaran euro. AS juga menggunakan supremasi dolar untuk merugikan musuh-musuhnya melalui sistem keuangan global. Iran menghindari perang konvensional dengan Arab Saudi dengan menggunakan proxy regional, serangan cyber, dan drone yang diarahkan ke fasilitas minyak. Hal-hal tersebut merupakan contoh lain yang dijelaskan oleh Leonard, migran sekalipun dapat digunakan sebagai senjata dalam berkonflik (hlm.119-124).
Leonard berpendapat, strategi terbaik untuk mencegah hal ini menjadi konflik abadi adalah dengan melucuti konektivitas melalui menetapkan aturan internasional baru di area potensi konflik, teknologi, dan mencari persetujuan demokratis yang lebih besar. Meski demikian, ia tidak menyalahkan globalisasi hanya untuk konflik antar negara; dia percaya itu juga berada di balik perpecahan yang berkembang dalam masyarakat kita. Bahkan, salam satu bab, dia mengeksplorasi paradoks bahwa konektivitas melalui sosial media itu menyatukan dan memisahkan kita.
Salah satu kekuatan dari The Age of Unpeace karya Mark Leonard adalah kemauan untuk menjungkirbalikkan keyakinan zaman ketidakdamaian ini pada ketidakberdayaan globalisasi. Selain itu, buku ini tak hanya berisi banyak data yang berimbang dari tiap negara yang dibahas, tetapi juga wawancaranya dengan para pemimpin negara dan penasehatnya.
Leonard juga berhasil menangkap tren yang berkembang dalam geopolitik selama satu dekade terakhir. Dia berpendapat bahwa tiga kekuatan utama – AS, Cina dan Eropa – semuanya bereaksi terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh konektivitas. Dia menggambarkan masa kini sebagai zaman ketidakdamaian, sebuah ungkapan yang tepat untuk era di mana perang antar negara jarang terjadi tetapi konflik mewabah.
Situasi politik global yang sudah dijelaskan oleh Leonard ini akan lebih lengkap bila membaca The New Map (2020) karya Daniel Yergin. Daniel menjelaskan pemetaan kekuatan politik global melalui sumber daya alam dan ekonomi serta komitmen pada perubahan iklim. Sebab, dua buku tersebut bisa melengkapi satu sama lain untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang situasi geopolitik dan ekonomi global.
*Penulis merupakan peneliti PARA Syndicate dan penulis buku Menjerat Gus Dur


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





