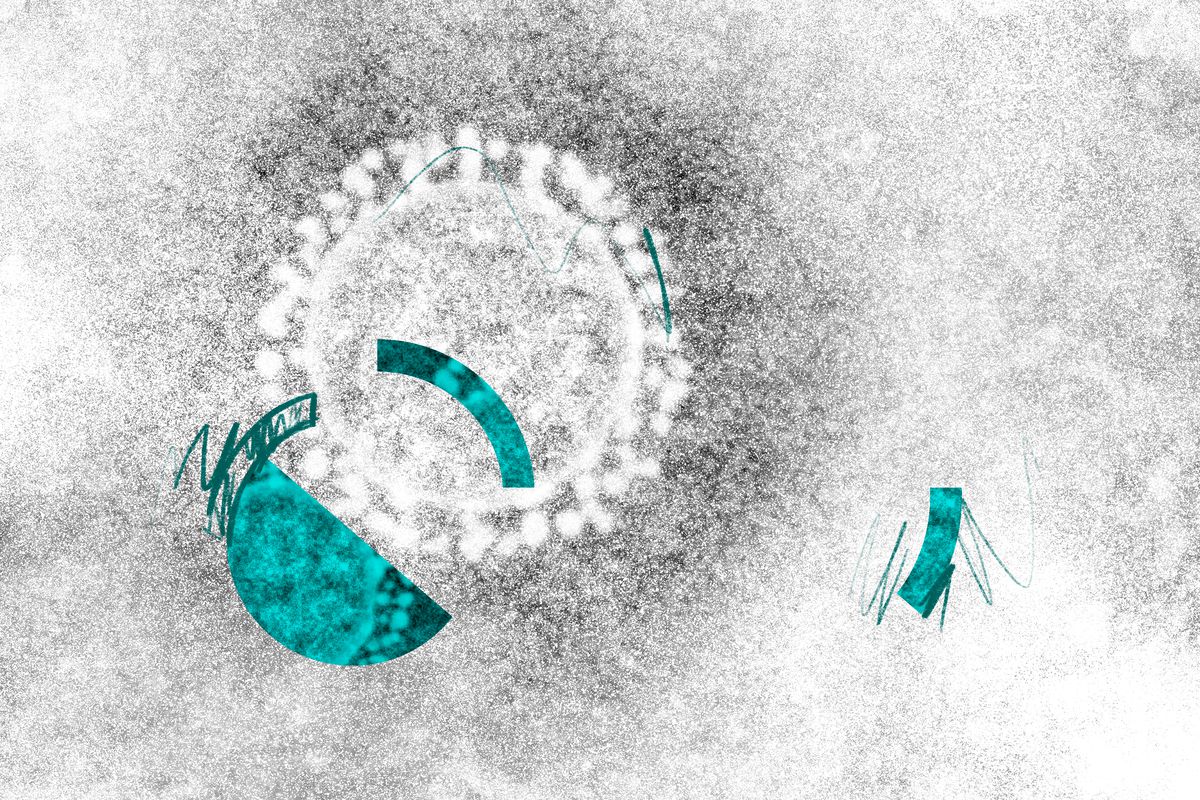Potret Bermacam Perjuangan dan Pemulihan Warga di Lingkar Industri Ekstraktif
Berita Baru, Analisa – Alam adalah kita. Alam menghidupi kita dan kita pun (seharusnya) merawat alam. Ini seperti kamar mandi dan air. Kita tanpa alam ibarat kamar mandi tanpa air. Betapa suwung?
Walhasil, adalah wajar ketika di berbagai daerah di Indonesia perlawanan warga terhadap industri yang berpotensi besar merusak alam (ekstraktif) terus terjadi. Mereka sedang memperjuangkan ruang hidup. Mereka memperjuangkan alam, memperjuangkan kehidupan.
Rilis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam bukunya Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan pada 2020 menunjukkan, dalam beberapa tahun terakhir ada enam (6) daerah yang warganya tidak kenal lelah melawan serta memperjuangkan ruang hidupnya dari kuasa pertambangan, termasuk enam (6) daerah yang mencoba untuk memulihkan kembali, bangkit, dan menolak untuk kalah selepas industri ekstraktif merenggut alamnya.
Catatan Perlawanan
Kampung Santan dan rencana pengeringan Sungai Santan
Dari catatan perlawanan, yang pertama adalah warga Kampung Santan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada 1997, pemerintah menerbitkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk PT Indominco Mandiri (IMM).
Terhitung sampai 2014, Sungai Santan yang posisinya sebagai sumber penghidupan warga sekitar, penyedia air bersih, kesuburan lahan pertanian, sumber protein, transportasi, dan sumber inspirasi budaya serta interaksi sosial tercemar akibat penambangan yang dilakukan di hulu hutan. Di tahun yang sama pun, PT IMM meningkatkan produksi batu baranya dari 16 juta metrik ton menjadi 20 juta metrik ton pertahun.
Peningkatan yang cukup signifikan ini mengulik keresahan warga. Pada 2015 warga akhirnya sepakat untuk mempelajari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terkait peningkatan produksi tersebut.
Hasilnya mencengangkan. Untuk meningkatkan produksi, PT IMM merencanakan penambangan langsung ke Sungai Santan (6.426 m) dengan cara memindahkannya sekaligus dua anak sungainya, Sungai Kare (1.430 m)) dan Sungai Pelakan (5.600 m) supaya bisa kering dan kemudian dikeruk batu baranya.
Mendapati itu, warga naik pitam sebab Sungai Santan di benak mereka tidak sekadar sungai, tetapi identitas kolektif. Sejak rencana PT IMM di muka diketahui, warga melakukan konsolidasi dan beberapa kali menggelar aksi yang memuncak pada 15 September 2015 di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), menolak tambang.
Aksi ini melibatkan perwakilan warga Santan dan mahasiswa Marangkayu—yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kecamatan Marangkayu (HMKM)—dengan membawa 471 tandatangan warga dilampiri fotokopi KTP. Mereka menuntut Dinas PU mencabut rekomendasi tambang yang telah dikeluarkannya. Setelah melalui beberapa hambatan, perlawanan mereka pun berhasil. Di tahun yang sama, rekomendasi tambang PT IMM dicabut.
Rumpun Asa Suku Dayak dan argumen alokasi ruang
Jika yang dihadapi warga Santan adalah proyek pertambangan yang sedang berlangsung, maka masyarakat Rumpun Asa Suku Dayak, Kutai Barat, Kalimantan Timur memiliki pengalaman sebaliknya. Mereka berhasil menggagalkan—untuk sementara waktu—didirikannya pertambangan batu bara oleh PT Kencana Wilsa.
Rumpun Asa Suku Dayak terdiri dari empat (4) kampung, yakni Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, dan Geleo Baru, sehingga untuk memudahkan mobilisasi, pada 2018 mereka mendirikan Forum Sempekat Peduli Gunung Layung (FSPGL). Forum ini dibuat berdasarkan kekhawatiran bersama pada dampak dari adanya tambang seperti rusaknya ladang pertanian dan hutang Gunung Layung yang tidak lain adalah sumber air bagi warga setempat.
Dalam sejumlah gelar aksinya, konferensi pers, kampanye di media sosial, dan pelaporan ke sejumlah lembaga pemerintah termasuk penegak hukum, FSPGL menuntut supaya pembangunan jalan angkut pertambangan sepanjang 7,32 km dan terminal khusus seluas 4,1 hektare diberhentikan.
Dalam tuntutan tersebut, warga menggunakan argumen alokasi ruang yang sudah tertulis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 menunjukkan, wilayah yang dipakai oleh PT Kencana Wilsa sebagai jalan tambang dan terminal khusus berada pada alokasi ruang pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
Melalui kajian tentang ini dan desakan warga terhadap Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya pada Januari 2019 surat larangan pembangunan jalan tambang dan terminal khusus diterbitkan. Artinya, pembangunan tambang di wilayah Rumpun Asa Suku Dayak berhasil digagalkan, meski PT Kencana Wilsa masih saja belum menyerah.
Para Perempuan Pulau Bangka dan narasi klise pemerintah
Pada 2013 anak-anak menjadi perantara PT Mikgro Metal Perdana (MMP) untuk memberikan uang sogokan kepada para ibu yang melawan di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Uang ini adalah usaha dari MMP untuk ke sekian kalinya supaya proyek pertambangannya di Pulau Bangka lancar, namun terhitung sampai tahun tersebut para ibu menolak dengan tegas pemberian uang gratifikasi itu. Mereka mengembalikan semuanya ke balai desa.
Beberap saat sebelumnya, sejumlah sepuluh (10) perempuan melakukan aksi penolakan masuknya alat berat. Mereka, khususnya yang dari Desa Kahuku, menolak keras masuknya alat berat tambang sebab titik operasinya adalah laut. Laut di wilayah pulau bangka merupakan sumber penghasilan, sehingga siapa pun pasti tidak menginginkan itu dirusak.
Selain itu, mereka juga bercermin dari hancurnya Teluk Buyat akibat tambang, apalagi Bangka termasuk pulau yang kecil. Ketika ada blasting yang dipakai saja, Pulau Bangka bisa hilang.
“Pun, soal diskusi, kami sama sekali tidak pernah diajak. Tidak ada yang memberitahu kami bahwa di sini akan dibangun tambang. Semisal ini dari Dinas Pekerjaan Umum, kenapa tidak ada sosialisasi? Pernah suatu hari kami melempari kapal pengangkut alat berat. Kami jelas takut. Namun, kami lebih takut terusir dari tempat kami sendiri,” kata salah satu perempuan yang berada di garis depan menghadang datangnya alat-alat berat tambang.
Perlawanan mereka tidak berhenti di situ. Selain melakukan penghadangan langsung, mereka juga memakai jalur hukum dan perlawanan khas Pulau Bangka. Di suatu pagi menjelang siang, bahkan, bertepatan dengan upacara 17 Agustus, mereka mendapati MMP sedang menurunkan alat berat dan seketika itu juga salah satu perempuan, Ibu Maria Parede, langsung pergi ke pantai, sendirian, dan berteriak, memperjuangkan alamnya.
Ibu Maria terluka dalam aksi ini dan pelaku penganiayaan, Manajer MMP sekaligus Kepala Sekolah SMP swasta di Pulau Bangka, hanya dikenakan hukuman tindak pidana ringan.
Merasa bahwa pergerakannya terhambat, MMP bekerja sama dengan negara akhirnya melakukan cara lain, yakni melalui diseminasi narasi yang miring tentang Pulau Bangka. MMP menyebarkan isu betapa Pulau Bangka tidaklah layak untuk kehidupan manusia sebab hawanya panas dan tanahnya tandus, tidak bisa dipakai menanam apa pun.
Kendati begitu, warga Pulau Bangka berhasil mematahkan narasi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa tanah Pulau Bangka bisa menghasilkan jagung yang melimpah, bahkan menjadi produk unggulan Pulau Bangka.
Silo, Padarincang, dan agama sebagai inspirasi perlawanan
Kisah perlawanan terhadap pertambangan di Jawa menyisakan sesuatu yang khas. Perlawanan warga Silo, Jember, Jawa Timur dan Padarincang, Serang, Banten diinspirasi oleh nilai-nilai agama dan yang berdiri di barisan paling depan adalah jajaran santri, termasuk kiai dan para ustaz/ustazah.
Untuk kasus Silo, didorong oleh ketidakinginan ruang hidupnya bernasib sama dengan Tumpang Pitu dan daya rusaknya yang tinggi terhadap ekologi dan dimensi sosial, warga setempat kompak memobilisasi berbagai level masyarakat mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) untuk menuntut supaya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT ANTAM seluas 4.023 hektare di blok Silo dicabut.
Sebagai sebentuk perlawanan, pada 14 November 2018, NU mengadakan Bahtsul Masail—forum diskusi keagamaan khas NU—dan secara lantang menyerukan bahwa operasi pertambangan emas di blok Silo haram hukumnya. Hukum ini berdasarkan pada dampak yang akan terjadi bila PT ANTAM masih memaksa untuk melanjutkan pertambangan.
Dalam beberapa kajian yang dilakukan, mereka menemukan satu celah untuk memperkuat tuntutan. Dalam WIUP blok Silo ternyata tidak ada rekomendasi dari Bupati Jember, padahal rekomendasi Bupati adalah syarat sebelum WIUP diterbitkan.
Berpijak pada celah ini, kemudian warga mendesak Bupati Faida, Bupati Jember, supaya segera melapor pada Kementerian Hukum dan HAM agar SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dicabut. Pada Februari 2019, berkat segenap perjuangan warga dan santri, Kementerian ESDM secara resmi mencabut izin pertambangan di blok Silo melalui Keputusan Menteri ESDM No. 23K/MEM/2018 tentang WIUP dan WIUP khusus periode 2018.
Sementara itu, dengan aktor yang sama, santri sebagai pihak dominan, warga Padarincang pada 2016 membentuk Sarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR) sebagai kendaraan untuk menuntut supaya operasi pertambangan panas bumi (geothermal) yang dikelola oleh PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) dihentikan. Pasalnya, alam bukan saja sumber kehidupan yang harus dipertahankan, tetapi juga amanah dari Tuhan yang perlu dijaga dan dibela dari eksploitasi.
Upaya-upaya yang dilakukan warga untuk melawan beragam, mulai dari mengadakan istigasah, gelar aksi di DPRD Serang, berjalan kaki dan protes di Kementerian ESDM, bertemu dengan anggota DPR RI komisi 3 dan 7, sampai memblokade jalan supaya mobil perusahaan tidak memiliki akses. Meski SBG sudah mengantongi izin dan hingga sekarang belum ada tindakan jelas pemerintah untuk menghentikan operasi pertambangan, warga tetap gigih melawan dan menilai bahwa pertambangan adalah sesuatu yang merusak ruang hidup bersama.
Pulau Wawonii dan penggusuran paksa PT Gema Kreasi Perdana
Masyarakat pulai Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, boleh dibilang sudah terbiasa dengan bersitegang dengan perusahaan pertambangan sekaligus oknum pemerintah yang mendukung tambang. Pada tahun 2000 warga sempat berhadap-hadapan dengan perusahaan tambang yang hendak secara sepihak mengkaveling pulau Wawonii, namun warga berhasil memenangkan pertarungan dengan mengusir pengusaha tambang.
Hal senada terjadi lagi pada tahun 2017 dengan PT Gema Kreasi Perdana sebagai pelakunya. Mirip dengan pendahulunya perusahaan yang berada di bawah kendali Harita Group ini—perusahaan yang gemar mengeruk nikel di banyak pulau di Indonesia—begitu saja mengaku memiliki konsesi di Pulau Wawonii.
Klaim tersebut didasarkan pada izin yang sudah mereka kantongi dari Kementerian Perhubungan untuk mendirikan terminal khusus atau pelabuhan yang secara bersamaan mereka membutuhkan akses antara titik pertambangan dan pelabuhan. Bicara akses, tentu bicara pembebasan lahan. Warga kompak tidak mau menjual kebun mereka.
GKP tidak menyerah. Mendapati warga tidak mau menjual kebun, GKP melakukan penggusuran paksa dengan alat berat. Warga yang mengetahui kebunnya digusur geram. Bermula dari tiga warga yang gagah berani berhadap-hadapan langsung dengan pekerja perusahaan yang tengah menggusur, termasuk aparat polisi dan beberapa warga lain yang pro-tambang, guna mencegah berlanjutnya penggusuran paksa, akhirnya warga bergiliran menjaga kebun mereka gusuran perusahaan.
Di samping bergiliran menjaga kebun, warga pulau Wawonii juga rela berkali-kali menyeberangi perairan menuju Kendari untuk menyampaikan keresahan mereka serta menuntut supaya izin GKP dicabut, termasuk agar kriminalisasi terhadap warga dihentikan—mengetahui sudah ada 27 warga telah dijebak dengan pasal yang berbeda-beda—di gedung DPRD dan kantor gubernur.
Pada awal tahun 2020 kabar baik berhembus. Kemenangan-kemenangan kecil warga mulai muncul ke permukaan. Beberapa alat berat ditarik mundur dan aktivitas pertambangan dihentikan. Dan baru pada 1 April 2020, pertambangan GKP resmi ditutup hingga waktu yang belum ditentukan.
Catatan Pemulihan
Siapa saja yang mendapati rumahnya, alamnya, dirusak tentu akan merasakan trauma, apalagi oleh segelintir elite yang tidak bertanggung jawab. Survei yang dilakukan JATAM menunjukkan, ada enam (6) wilayah yang hingga hari ini masih berjuang untuk memanggil kembali memori kolektifnya terhadap alam tempat mereka hidup pascatambang dan mencoba untuk bangkit dari trauma, meliputi Kampung Santan, Sumba, Desa Rindu Hati, Kecamatan Sanga-Sanga, Porong, dan Sidikalang.
Sumba, Kampung Santan, dan jalan menuju pemulihan kolektif
Dalam upaya pemulihan, setiap daerah memiliki cara yang khas. Warga Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan Kampung Santan, Kalimantan Timur berjuang dengan ritual dan festival yang diadakan secara rutin di sungai bekas tambang.
Warga Sumba menggelar festival Wai Humba di Sungai Paponggu, kawasan Pegunungan Tana Daru, Sumba Tengah. Acara yang kali pertama diadakan pada 2012 ini merupakan agenda tahunan dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya.
Sebagaimana festival dan ritual pada umumnya, Wai Humba terdiri dari beberapa kegiatan seperti ibadah, ikrar persaudaraan, pentas seni, diskusi kampung, dan kunjungan dari kampung ke kampung. Di sisi lain, Wai Humba dianggap juga sebagai ruang pembelajaran serta kampanye mengenai dampak rusak industri ekstraktif, khususnya tambang yang pernah mengancam Pulau Sumba.
Sementara itu, warga Kampung Santan menggelar festivalnya di Sungai Santan. 2018 menjadi tahun pertama mereka mengadakan acara tersebut. Pihak yang menginisiasi adalah Tani Muda Santan (TMS), meski demikian TMS tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan warga dalam mengurus acara yang berlangsung selama 3 hari itu.
Adapun rangkaian kegiatannya meliputi tari-tarian, pembacaan puisi, permainan tradisional, ziarah ke makam leluhur desa, susur sungai, dan diskusi seputar dampak rusak pertambangan. Yang terakhir tidak lain berhubungan dengan upaya warga untuk senantiasa merawat ingatan bahwa industri ekstraktif sangat berbahaya untuk alam.
Melawan lewat kopi: kisah dari Rindu Hati
“Kami telah menikmati kebaikan yang diberikan alam, maka sudah tugas kami menjaga kelestariannya sampai kami bisa menikmati kebaikannya hingga anak cucu kami,” ungkap Ibu Tinut, salah petani kopi di desa Rindu Hati, Bengkulu.
Warga desa Rindu Hati memiliki cara yang elegan untuk menolak pertambangan. Mereka bertani kopi dan menggenjot produksi padi. Mereka memang mendapatkan iming-iming pekerjaan dari perusahaan tambang batu bara, PT Bara Mega Quantum (BMQ), namun mereka lebih memilih mengelola alamnya sendiri.
Mereka menolak sebab mereka tahu secara langsung bagaimana nasib tetangga desanya, Niur, Bengkulu Tengah, yang mengalami kriris pangan dan air bersih, sehingga untuk kebutuhan tersebut warga Niur harus mendatangkan dari desa tetangga. Pertambangan pun membuat mereka harus beralih profesi dari betani menjadi buruh yang memungut batu bara di sungai-sungai.
Keberanian warga Rindu Hati selaras dengan ketekunannya. Pada 2017 di Festival Bumi Raflesia, kopi petik merah Rindu Hati mendapatkan penghargaan kopi terbaik. Dari segi produksinya pun tidak perlu ditanya. Setiap Februari-Juni hasil panen kopi desa Rindu berada di antara 600 kg hingga 1 ton.
PT BMQ sebenarnya sudah memiliki konsesi di Desa Rindu Hati pada 2011, tetapi karena kerja keras warganya dengan hasil panen kopi dan padi yang mumpuni, PT BMQ menciut dan akhirnya Desa Rindu Hati dibebaskan dari konsesi.
Dilihat dari sejarahnya, Desa Rindu Hati memiliki potensi tambang yang tinggi. Pada 1950, perusahaan bijih besi, emas, dan batu bara pernah merayu warganya, tetapi gagal. Tujuh tahun setelahnya pun, perusahaan lain datang. Kali ini berencana untuk membuat perusahaan kelapa sawit, tetapi jawaban warga sama: tidak.
Kelompok Tani Sanga-Sanga dan pemerintah yang menutup mata
Kelompok tani Daya Karya Mandiri (DKM) di RT 24, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memang hanya beranggotakan 25 orang. Namun, daya geraknya mampu memulihkan secara perlahan pertanian di wilayah bekas tambang migas dan batu bara di daerahnya.
Mereka memanfaatkan lahan-lahan sisa tambang yang masih bisa digarap. Mereka menanam sayuran dan buah-buahan. Mereka pun beternak sapi di sekitarnya dan menjadikan kotorannya sebagai pupuk organik untuk tanamannya. Lahan yang mereka kelola memiliki lebar masing-masing 20 meter dengan panjang yang tidak dibatasi.
Motivasi mereka sebenarnya cukup sederhana, yaitu ketidakinginan untuk terjebak dalam kubangan yang sama. Pada 2003, sebagian besar warga Sanga-Sanga tergiur melepas lahannya demi pertambangan. Akibatnya, lahan-lahan mulai susah ditanam, bahkan rusak, dan banjir menjadi langganan, apalagi ketika tambang sudah pergi dan lahan dibiarkan begitu saja: tidak ada pemulihan, tidak ada reklamasi.
Karena itu, ketika pada 2016 pemerintah kembali memberikan izin tambang, setelah pada 2013 pertambangan sebelumnya sudah selesai, warga RT 24 menolak tegas. Mereka memilih, khususnya melalui DKM, untuk mengelola lahannya sendiri, meski sudah sangat mengernyitkan hati.
“Yang paling terasa itu, saat hujan tiba, parit dan sungai masih dipenuhi sedimen lumpur yang berasal dari kawasan bekas tambang yang sama sekali tidak dipulihkan pemerintah,” ujar salah satu anggota DKM.
Porong dan strategi pemulihan mandiri ekonomi-kesehatan warga
Sejak bencana yang menimpa Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Mei 2006 yang disebabkan oleh PT Lapindo Brantas, warga setempat harus berupaya sendiri untuk melakukan pemulihan baik ekonomi ataupun kesehatan. Daerah Porong tidak saja tercemar dari segi airnya, tetapi juga udara.
Pengeboran yang dilakukan perusahaan minyak dan gas alam di bawah kendali Bakrie Group tersebut berakibat pada keluarnya lumpur panas secara terus-menerus dengan diiringi gas metana yang beracun, Polycylic Aromatic Hydrocarbon (PAH). Sementara itu, berdasarkan hasil pantauan warga bekerja sama dengan Ecoton dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), air di Sungai Porong tercemar berat dan sedang oleh logam seperti timbal dan cadmium dengan 1000 kali lipat lebih tinggi bahayanya dari ambang batas yang diperbolehkan.
Oleh sebab itu, warga melakukan upaya pemulihan ekosistem secara kolektif melalui beberapa kelompok yang mereka miliki seperti Kelompok Belajar ar-Rohma, Sanggar Alfaz, Paguyuban Ojek Tanggul, Korban Lapindo Menggugat, dan warga Kelurahan Gedang, Sidoarjo. Mereka juga menginisiasi adanya kelas perempuan sebagai ruang untuk berbagi kisah tentang pengalaman menjadi korban pertambangan, sosialisasi dampak lingkungan yang rusak parah, kesehatan, dan sebentuk tuntutan pada pemerintah untuk tidak menutup mata, termasuk mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi dengan Porong.
Dan sejak 2016, warga melakukan pemeriksaan medis rutin guna memantau kesehatan warga terdekat dari tanggul Lapindo. Sebab betapa pun apa yang mereka hirup masihlah mengandung sisa-sisa racun dari PT Lapindo Brantas yang seolah selepas mereka membayar ganti rugi, semuanya selesai.
Kopi Sidikalang dan senjata perlawanan
“Bukannya sombong. Bawa pulang tambangmu. Jadilah petani saja di sini. Nanti Tuhan dan Tanah yang akan menggajimu,” tegas Opung Rainim Boru Purba pada salah satu pekerja PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Desa Pandiangan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pada 2018, PT DPM melakukan peningkatan produksi—sejak pertama kali hadir menancapkan bisnisnya pada 1998—yang berarti akan ada perambahan wilayah konsesi. Di waktu bersamaan, secara sepihak Menteri Kehutanan mengklaim kebun-kebun warga Pandiangan sebagai kawasan hutan dan kemudian diberi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dibuatnya IPPKH tentu mengarah pada jalan masuk konsesi perusahaan tambang. Warga desa menyadari gerakan tersebut, walhasil karena nyaris semua warga Pandiangan adalah petani, mereka kompak menolak datangnya tambang.
Salah satu yang paling vokal melawan adalah Opung Rainim Boru Purba, petani perempuan yang produktif di Pandiangan. Opung memiliki ladang jagung seluas setengah hektare dan panen tiga kali dalam setahun. Ia juga punya kebun kopi dengan luas yang sama dan hasil panennya mencapai 7,5 kuintal, memiliki kebun Durian Parongil dengan 50 pohon, kapulaga, kelapa, pisang, nanas, kakao, kemiri, jahe, cabe, ternak ayam, babi, dan sebagainya.
Dalam satu tahun Opung bisa mendapatkan 12 juta dari jagung, 14,5 juta dari kopi, dan 40 juta dari durian. Untuk ukuran Opung saja, jumlah panen yang dihasilkan dari kebun—jika dikelola sendiri—jauh melampui uang yang diterima baik dari gaji ataupun hasil penjualan kebun. Walhasil, dengan alasan itulah warga Pandiangan memilih untuk melawan dan mempertahankan kebun. Mereka berhasil membuktikan bahwa ekonomi tanding yang mereka teriakkan jauh lebih menghasilkan sekaligus memuaskan ketimbang ekonomi pertambangan yang merusak. Ini pulalah yang menjadikan mereka tidak tergoda dengan bujuk rayu PT DPM.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co Server
Server