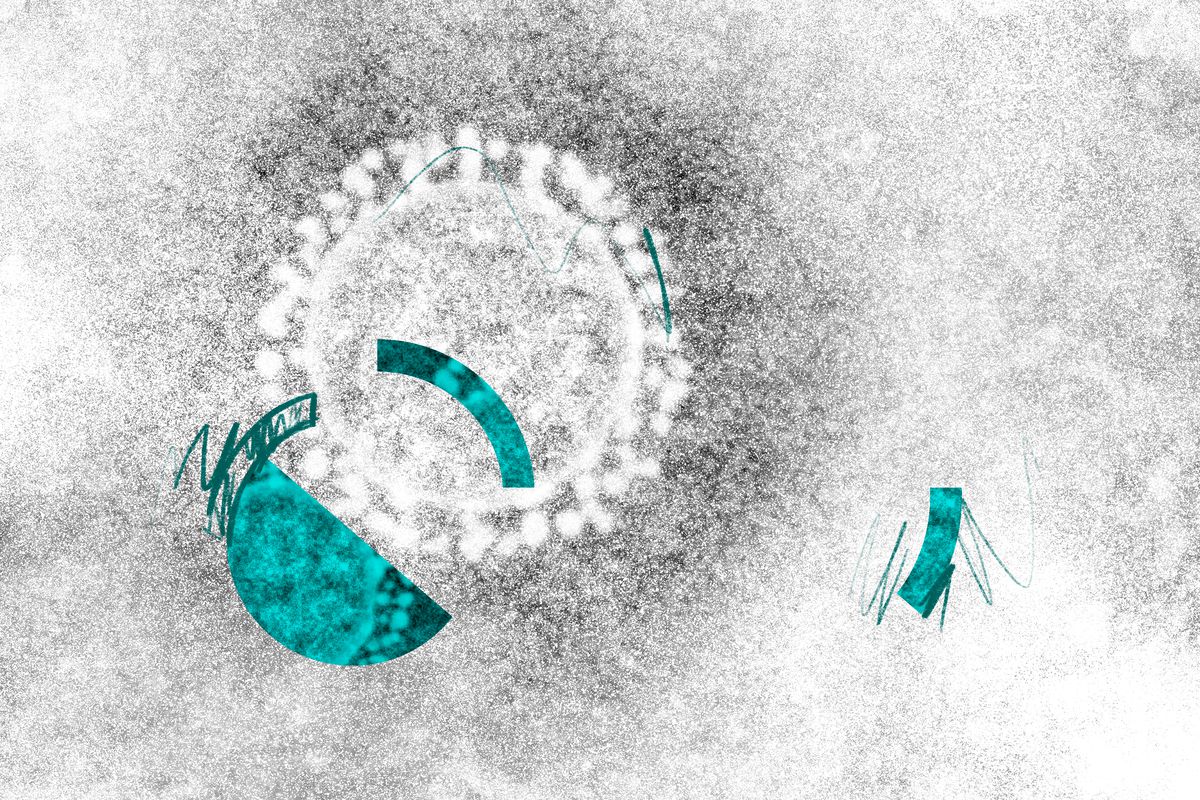Jalan Berliku Sosialisme Indonesia
Oleh Taufiq Ahmad*
Ketika Republik Indonesia berdiri, gagasan sosialisme bersemarak dan cukup menentukan jalannya negara. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan segenap tokoh pendiri bangsa lainnya, bukan hanya mengenal sosialisme, namun mempunyai visi untuk republik yang baru berdiri itu dengan warna sosialisme yang sangat kental. Soekarno merumuskan marhenisme, suatu ideologi adaptasi dari marxisme, Hatta merumuskan sosialisme ala Indonesia dan mempelopori koperasi, lalu syahrir dengan sosialisme kerakyatannya, dan sebagainya.
Hal itulah yang membuat Indonesia awal-awal cenderung sosialistis daripada kapitalis-liberalis. Sila kelima dalam Pancasila, yakni keadilan sosial, berbagai pasal dalam UUD 45 seperti tertera dalam padal 33, lalu koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, misalnya, dianggap mewakili ideologi sosialisme. Dalam era Demokrasi Terpimpin, Soekarno juga mencanangkan agar Indonesia menjadi negara sosialis ala Indonesia.
Namun, sosialisme sebagai ideologi seolah redup ketika Orde Baru berdiri. TAP MPRS No. 25 tahun 1966 yang berisi pelarangan marxisme-leninisme/komunisme, suatu varian dari sosialisme, dijadikan alat pemukul PKI, dan membuat sosialisme seolah menjadi barang haram. Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang sebelumnya dibubarkan oleh rezim Soekarno pada 1962, tidak pernah bisa dihidupkan kembali.
Sosialisme Orde Baru
Meskipun Orde Baru yang dianggap mengambil jalan yang berbeda dari Orde Lama, ternyata kalau ditelisik masih kental dengan unsure-unsur sosialismenya. Orde Baru tidak sebagaimana Barat yang mengambil jalan pasar bebas, melainkan mengatur pasar di bawah kendali pemerintahan. Pembangunan terencana, sebagaimana tertuang dalam Repelita, dijalankan sebagaimana negara komunis. Pembangunan koperasi digencarkan di desa-desa, sesuai doktrin bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Reforma agraria yang menemui jalan buntu pada era demokrasi Terpimpin khususnya di Jawa sehingga berlangsung konflik social besar-besaran 1965/1966, dicari jalan keluarnya dengan program transmigrasi. Tanah-tanah di Jawa memang terlalu sempit sehingga tak memungkinkan redistribusi. Berbagai subsidi digelontorkan, terutama untuk sektor strategis, dan sebagainya.
Selain itu, banyak sekali aktivis-aktivis sosialis yang kemudian masuk dalam pemerintahan. Sebut saja misalnya Adam Malik, seorang aktivis partai Murba, partai besutan Tan Malaka, yang kental dengan ideologi sosialisme. Adam Malik berkarir menjadi Menteri Luar Negeri (1967), dan menjadi Wakil Presiden (1978),
Adapun Soemitro Djojohadikusumo, seorang aktivis Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang bahkan sempat bersaing ketat dengan Sutan Sjahrir, pada era Orde Baru menjabat sebagai Menteri Perdagangan (1968-1972) dan Menteri Negara Riset (1972-1978). Soemitro juga adalah pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dari kampus UI itulah ia mengkader beberapa pelajar yang kemudian dikirim ke Amerika. Kader-kader itu kemudian pulang dan mempengaruhi jalannya Orde baru, yang kini kita kenal dengan “Mafia Berkeley.”
Sebagai sebuah gagasan, sosialisme memang tidak nampak secara vulgar. Namun gagasan-gagasan sosialisme seperti beradaptasi dengan suasana Orde Baru, sehingga bermunculan berbagai istilah yang sebenarnya nuansa sosialisnya cukup kental. Misalnya istilah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan sebagainya. Jurnal Prisma (dibawah naungan LP3ES), yang merupakan salah satu wadah pergulatan pemikiran yang cukup bergengsi pada era Orde Baru, banyak sekali menampilkan berbagai gagasan yang sosialistis, dengan beragam variannya. Semua itu menunjukkan bahwa, bagaimanapun, pada era Orde Baru, cita-cita “sosialisme ala Indonesia,” masih tercium aromanya dalam berbagai gagasan dan berbagai kebijakan.
Menganut Marx, peletak dasar sosialisme ilmiah alias marxisme, jika sosialisme adalah suatu era transisi dan perwujudan dari kritik atas kapitalisme liberal khas laissez faire dan bentuknya adalah pengendalian negara atas pasar agar efek eksploitatifnya bisa dihilangkan, Orde Baru dalam kadar tertentu masih dalam jalur itu. Mirip sekali misalnya dengan Singapura atau Tiongkok saat ini, dimana pasar bebas ditolak dan intervensi negara dicanangkan.
Sosialisme era Reformasi
Orde Baru yang dibangun dengan dua pilar yakni militer dan teknokrat, ternyata tidak mampu menghadap badai krisis financial global, sehingga dengan tekanan gerakan mahasiswa yang mengusung reformasi, membuat Soeharto mengundurkan diri pada 23 Mei 1998 dari kursi kepersidenan setelah berkuasa selama 32 tahun. Dengan suksesi kepemimpinan tersebut, Orde Baru dinyatakan bubar dan reformasi sedang dilangsungkan.
Dalam masa Orde Baru, kebebasan berbicara dibungkam. Gagasan-gagasan yang tersebar dalam masyarakat dibatasi sedemikian rupa. Apalagi jika berkaitan dengan marxisme khususnya komunisme. Novel-novel karya Pramoedya Ananta Toer (tokoh Lekra) misalnya, selalu dilarang beredar. Bahkan ada beberapa aktivis yang dipenjara oeh Orde Baru hanya karena ketahuan menjual novelnya Pramoedya. Hal itu menunjukkan bagaimana ketatnya Orde Baru dalam mengontrol wacana yang beredar dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, ketika reformasi bergulir, gagasan-gagasan yang sebelumnya terlarang menjadi beredar secara luas. Buku-buku yang berkaitan dengan ideologi kiri begitu digandrungi para pemuda. Bukan hanya itu, organisasi-organisasi mahasiswa juga banyak sekali mengkaji buku-buku kiri, sehingga terinspirasi dalam melakukan pergerakan. Namun, sindrom “kiri itu seksi” itu semua yang berlangsung pada ranah akar rumput, atau hanya di kampus-kampus.
Dalam aras “negara” yang berlangsung adalah sebaliknya. Sosialisme yang digndrungi kalangan pergerakan itu tidak pernah berwujud menjadi partai politik yang bisa menentukan jalannya kebijakan negara. Partai-partai yang ada adalah partai yang tidak lagi ideologis sebagaimana era 1955, dan hanya sekedar menjadi partai yang berbasis kepentingan kekuasaan sesaat, yang mengabdi pada pemilik modal belaka. Partai menjadi tak ada bedanya dengan unit usaha laiknya perseroan terbatas yang misi utamanya adalah melakukan transaksi politik. Walaupun dalam transaksi-transaksi itu selalu mengatas-namakan kepentingan rakyat, pada kenyataannya yang berlangsung adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok pemodal partai.
Oleh sebab itu, setelah reformasi, berbagai macam peraturan perundang-undangan yang lebih condong pada liberalism digulirkan. Kebijakan-kebijakan seperti deregulasi pasar, pencabutan subsidi, penanaman investasi asing secara besar-besaran, dilangsungkan oleh rezim-rezim setelah reformasi, khususnya setelah Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan yang dia duduki amat singkat.
Proses tersebut terus berlangsung hingga hari ini, sehingga cita-cita awal republik ketika didirikan seperti sosilisme ala Indonesia, keadilan social, kemakmuran bersama, kian jauh panggang dari api.
Sebagai perbandingan dengan negara utara yang kini banyak andil dalam investasi di Indonesia, yakni Tiongkok, pada tahun 1980 GDP perkapitanya hanya $ 196.44, sementara GDP perkapita Indonesia $ 491.44, tiga kali lipatnya. Adapun pada tahun 2020, GDP perkapita Tiongkok naik 52 kali lipat alias $ 12,263.471, kalau dibandingkan dengan Indonesia hanya $3.869,59, alias hanya naik 5 kali lipat. Bukankah kita seperti terseok-seok, terjebak dalam middle income trap? Itu belum lagi soal kesenjangan, dimana rasio gini Indonesia adalah 0,384 alias sangat senjang hampir mencapai titik ledak.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aras negara, sosialisme Indonesia (Orde Lama) atau ekonomi kerakyatan dan ekonomi pancasila (Orde Baru), semakin ditinggalkan oleh rezim saat ini. Di sisi lain, kebebasan berpendapat yang merupakan suatu berkah dari reformasi juga mulai terkikis habis, terutama telah digulirkannya UU ITE. Indonesia era reformasi jadi semakin mirip dengan negara kolonial Hindia Belanda.
Saya teringat guyonan budayawan Emha Ainun Najib, “negara sosialis itu kamu dikasih makan tapi tak boleh mengkritik, negara kapitalis kamu boleh mengkritik tapi makan cari sendiri, sementara Indonesia adalah perpaduan keduanya: kamu harus bungkam tapi makan cari sendiri!”.
Baca juga: Konfusianisme dan Sosialisme Tiongkok
*Penulis aktif di Gerakan Alternatif 21


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co