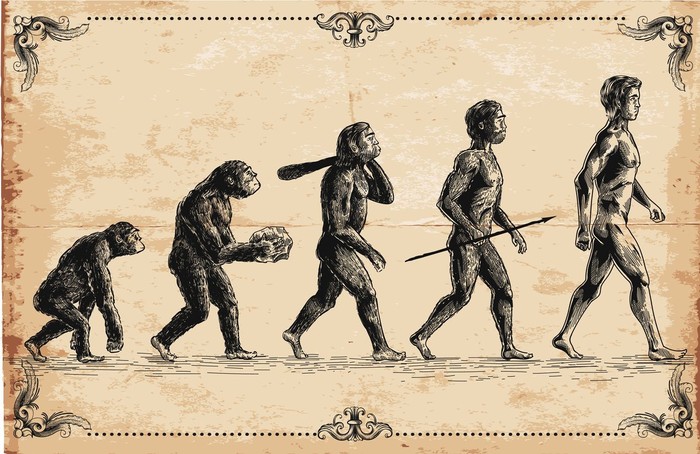
Awal Mula dan Akhirnya; Sebuah Analisis Sosial
Opini: (M. R. Firdausi)
Setiap perkembangan, kemajuan, baik bagi individu maupun tatanan sosial, diantaranya selalu dimulai oleh timbulnya kemauan lepas dari kejenuhan (untuk sekedar tidak menanggung rasa bosan), yang kemudian bertransformasi sebagai sebuah nilai yang diyakini. Suatu upaya untuk bertahan dan melanjutkan hidup.
Keberlakuannya sebagai nilai yang baru, membuat pertentangan dengan nilai yang ada dan sedang berlangsung tidak bisa dihindari, timbul upaya untuk saling mempertahankan, demikian berlakunya survival of the fittest, terjadilah persaingan dimana hanya yang kuat dan unggul yang akan terus hidup. Yang lalu dengan murah hati kita menamainya sebagai seleksi alam.
Satu konsekuensi dari berlakunya sebuah nilai, yakni keharusan untuk meredam apapun yang menjadi penghambat, demikian mudahnya perselisihan, konflik dan perang terjadi. Tapi tentu saja, kejenuhan tidak se-iseng itu untuk menciptakan suatu kemajuan. Belenggu sosial-budaya telah membuat manusia saling berselisih hingga menderita, dan mendorong seseorang untuk berkembang, menemui kemajuannya.
Halnya suatu perselisihan diantara individu dan konflik sampai peperangan antar bangsa-bangsa yang saling memberangus satu sama lain dari sejak dulu, yang juga mungkin hingga esok, entah memperebutkan harta (sumber daya alam; ekonomi), atau kebenaran (mitos, sains dan agama), bahkan pertunjukan kekuatan (gengsi ras paling unggul; politik). Nilai hanyalah sesuatu yang berharga, tidak peduli sebelum atau sesudah berkembangnya pengetahuan diantara manusia.
Sebagian diantaranya (bukan saja selamat) sebab memenangkan persaingan lalu menetapkan nilainya dalam sebuah komunitas masyarakat, yang secara perlahan pengaruhnya menguat menjadi nilai paling dominan, melegitimasi kekuasaan, sebagai pemegang kuasa, dengan demikian kita dapat menandai sebuah jaman dimana sosial-kemasyarakan mulai terbentuk, dan peradaban dimulai.
Manusia, dengan begitu, berkumpul membentuk budaya, sebagai akibat penerimaan pada nilai tertentu. Sementara keharusan menjaga nilai juga menjadi hal yang membosankan. Demikian pola yang sama masih saja berlangsung, bahkan seperti apapun sebuah pencapaian, manusia tidak juga sanggup meredam datangnya perubahan; suatu kemajuan. Kala manusia berhasil keluar dari kejenuhan, ada upaya untuk menjaga keberlangsungan nilainya dan kembali jemu.
Sejarah menceritakan itu semua, bagaimana prilaku yang menyimpang terjadi dari nilai yang disepakati, dan boleh jadi penguasa menjerat sebagian individu yang menyimpang, tetapi penyimpangan penguasa dengan kekuasaannya membuat kekacauan tatanan sosial selalu lebih payah. Hal-hal yang terjadi justru memperjelas bahwa kejenuhan mendorong manusia untuk memperbarui apa yang terlintas dipikirannya. Tidak ada penyimpangan tanpa kejenuhan. Sementara kejenuhan akan menyertai kehidupan, disekitar (oleh dan dengan) kekuasaan, hasrat (naluri alamiah) manusia menjadi lebih terwadahi, ntah lebih baik atau sebaliknya, yang jelas perubahan terjadi.
Sedang dalam pada itu, sebagai sebuah kesempatan yang ada disekitar manusia, yang disadari bisa memenuhi segala inginnya, melalui kekuasaan, manusia memperbarui segalanya, bahkan gerak ilmu-ilmu sosial dipengaruhi olehnya, yang pada gilirannya ilmu sosial juga akan memengaruhi masyarakat. Tetapi begitulah kekuasaan, menjadi konsep dasar kemana tatanan sosial dihendaki, sebab disanalah mulanya suatu interaksi, perilaku sosial dibentuk. Satu kenyataan yang hanya perlu diterima, lagipula dimana-mana kehendak mencapai kemajuan tidak juga menyimpan maksud selain perhatiannya pada kemanusiaan besok.
Sebelum Mitologi hingga Darwinisme
Sedari awal, manusia sudah diliputi kesamaan nilai, bahwa kehidupan adalah segalanya; sebagai sebuah pengantar bagi setiap manusia untuk melanjutkan nasib. Tidak memerlukan kesadaran untuk itu, sebab peradaban hanya dimulai dari kehampaan pengetahuan, hal yang setimpal sedang berlangsung.
Saat itu otoritas kebenaran berada diluar manusia, pada yang Esa manusia bersandar. Itu pula satu-satunya alasan bahkan mengapa kita, sebagai manusia bersandar, bahwa tidaklah lain sebab didorong oleh kecintaan pada diri sendiri, pada kesempatan hidup, tapi itulah kewajibannya, dan dari ketiadaan manusia diciptakan hanya untuk menunaikan apa yang diperintah.
Namun seiring dengan besarnya kecintaan manusia pada dirinya, pada yang kasat mata ini (materialisme) kemudian kewajibannya tersisihkan. Sebagian bergegas menjadi tuhan, mengambil alih otoritas, dengan begitu manusia menciptakan sendiri kebenarannya. Sedang sebagian lagi beranggapan Tuhan sendiri yang akan mengatasi tabiat bebas manusia.
Satu diantaranya menandai bagaimana persoalan manusia dimulai dan yang lain masih membuka peluang bagi dua kemungkinan, pertama redupnya kemanusiaan, dan yang kedua hanya menyisakan misteri kehidupan, bahwa manusia adalah subjek sekaligus objek yang selalu mungkin dibentuk.
Tatkala sebagian membentuk kuasanya sendiri, keengganan melawan dari sebagian yang lain larut memperpanjang ketimpangan. Saat iklim tatanan kemasyarakatan menjadi timpang, kuasa antara yang satu dengan yang lain bukan saja tidak lagi setara, melainkan akses manusia untuk mengerti (kebenaran dan gejala) juga terbatas pada nilai-nilai dominan yang berkuasa dan karenanya membelenggu. Tidak ayal, Tuhan berkali-kali mengirimkan seorang nabi.
Hanya saja sejarah selalu hilang bersamaan dengan menguatnya dominasi nilai tertentu, manusia tidak lagi mampu menjamah, memberi pengertian siapa dirinya disini, dan lambat laun prasangka, dugaan yang berarti mitos berkembang diantara manusia. Sementara mitos berkembang (otoritas yang berada diluar manusia kembali dipulihkan), kehidupan manusia dipenuhi kekhawatiran dan penderitaan, ada keyakinan bahwa dewa akan menjamin sekaligus menghukum setiap perbuatan secara setimpal. Tidak ada kemajuan dalam mitos.
Waktu itu, mitos sebagai sandaran paling rasional manusia, menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup, sebagai modal untuk berdiam diri menerima nasib. Sebaliknya, sisanya berperang menentukan nasib, memberangus satu sama lain, menghidupkan otoritas dari dalam dirinya. Tapi keduanya tidak sekali beda, hanya sama-sama didorong oleh kecintaan pada dirinya sendiri.
Dalam tempo yang cukup lama kehidupan manusia telah berlangsung tanpa kepastian juga sejarah, tapi sejarah berulang, dalam pola yang hampir tidak jauh beda. Disinilah mulanya darwinisme menemui kesempatannya untuk dianggap sebagai nilai kebajikan sosial, dan secara perlahan ‘kesempatan hidup’ bukan hanya tidak lagi memiliki makna terdalamnya melainkan juga tidak cukup untuk membuat manusia kembali bersandar pada yang Esa, tidak cukup sebab kehidupan sudah terlanjur didaur ulang oleh darwinisme dan tergantikan oleh narasi kepastian tunggal saintism, suatu upaya mengaburkan identitas manusia dan menjelaskan ulang bagaimana kekacauan sosial bisa terjadi.
Lalu bagaimana saintisme bisa menjadi cara pandang dunia yang paling otoritatif hingga menyingkirkan cara pandang yang lain. Kepastian menjadi kebutuhan manusia mulai saat itu dan generasi berikutnya, hingga kini diluar sains adalah mitos. Padahal, selain kepastian kita (manusia) juga butuh pengertian, pengertian untuk menerima ketidakpastian. Hanya itu satu-satunya konsepsi yang mampu menghapus kebutuhan manusia pada suatu kepastian.
Dari Darwinisme peluang keberlangsungan antroposentrisme menjadi nyata, yang dengan begitu manusia menulis kembali sejarahnya yang tanpa transendensi. Otoritatif dibentuk dari dalam diri manusia, tidak lagi ada kuasa diluar kehendak manusia, egosentrisme tumbuh melampaui umur manusia.
Egosentrisme Diantara Manusia
Sampai pada jaman dimana manusia berkembang dan membentuk koloni-koloni kecil. Seiring berjalannya waktu, wilayah jarahan untuk menopang kebutuhan bertambah, hal sama terjadi ditempat lain yang tidak jauh, hingga gesekan antar koloni tidak dapat dihindari, mula-mula berselisih soal kebutuhan, tetapi lambat laun gensi ras larut menyelimuti.
Wilayah kekuasaan menjadi semakin luas bagi yang memenangkan perang, dan bagi yang kalah berlaku sebaliknya, mereka hanya menyimpan memori penderitaan. Diantaranya menjadi pemimpin dan selalu yang terkuat, juga lebih dari sekedar pimpinan perang. Upaya-upaya untuk menetapkan garis wilayah kekuasaan dimulai. Mulaillah manusia mengenal lalu menetapkan aturan sebagai bagian penting dalam kehidupannya, hal-hal mulai dilembagakan (termasuk kekuasaan), hubungan manusia yang mulanya sama rata sama rasa (bersama; dalam koloni) bergeser antara tuan dan hamba. Kekalahan dan kemenangan dalam perang memberi kesempatan untuk itu.
Sementara kekuasaan hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kemampuan membunuh, interaksi sosial masih juga ditemukan dalam, perang demi perang. Lambat laun, seiring dengan penderitaan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, akhirnya membuat manusia terpaksa berpikir untuk menghapus penderitaan (dengan atau tanpa konflik). Kekuasaan yang mulanya didasarkan pada kehendak tunggal dan turun-temurun, mulai menemui keruntuhannya dihadapan perkembangan pengetahuan, secara perlahan dan pasti, jaman berganti. Tapi tentu sejarah tidak berlangsung sekejab.
Terjadilah suatu pengembangan naluri dasar manusia untuk bebas-lepas, berpikir untuk menata kembali iklim sosial kemasyarakatan yang layak dijalani bersama. Diantara iklimnya, kekuasaan mulai diakses oleh siapapun dengan cara yang lebih beradab, kekuasaan tidak lagi diperebutkan dengan kekerasan, dan kekuasaan dimanifestasikan untuk menjaga kehidupan bersama. Agar kekuasaan dapat melayani kepentingan bersama, manusia menentukan aturan, suatu kuasa hukum yang juga akan dijalankan oleh manusia, yang dengan diaturnya kepentingan bersama, kita menandainya sebagai kemajuan suatu peradaban.
Sayangnya selalu ada egosentrisme diantara manusia yang memungkinkannya untuk terus bersaing, satu kehendak untuk mengorbankan yang lain, demikian sedari awal, yang dengan aturan penderitaan manusia menjadi sedikit lebih elegan. Pelembagaan masyarakaat membuka peluang untuk itu. Tapi itulah konsekuensi dalam peradaban modern, yang kita sebut sistem demokrasi. Kekuasaan diperebutkan. Sementara kekuasaan dapat mempengaruhi aturan; hukum memberinya legitimasi untuk memperebutkan kekuasaan secara sah, dan beradab.
Sebuah pergolakan sejarah yang cukup lama dan panjang lagi berlanjut, bagaimana perjalanan peradaban -kekuasaan- yang dipengaruhi oleh kebudayaan berlangsung, dari koloni, otoritarian, monarki hingga demokrasi. Meski begitu, terbukanya upaya-upaya untuk membuka ruang bagi persamaan derajat, lahirnya hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, bukan juga akhir dari periodeisasi suatu peradaban, kemajuan bukanlah sebuah tujuan namun perjalanan yang berkesinambungan.
Manusia Mencari Kemajuannya
Sesampainya pada dunia yang mulai dipenuhi teknologi, manusia masih saja mencari kemajuannya. Tetapi seperti pencapaian manusia dimasa lalu, megahnya kekuasaan bangsa-bangsa besar, nyatanya juga menemui keruntuhannya; Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar didunia selalu muncul, tumbuh jaya, lalu tumbang. Pada jamannya, bangsa Mesir menjadi idola bangsa-bangsa lain disekitarnya, dimasa-masa berikutnya kebesaran bangsa Yunani berlangsung, disusul Romawi, Persia, Spayol, Prancis, dan Inggris (rules the waves), lalu Amerika menggantinya.
Masing-masing bersiap-siaga menggali kuburannya sendiri, tak ada satupun yang berarti. Kejayaan semua bangsa ini begitu mempesona bagi bangsa lain. Pada masa kejayaan Napoleon, mode pakaian, bahasa, dan gaya hidup orang Perancis menjadi gaya Eropa. Tapi setelah Napoleon jatuh, leyap pula kebesarannya, dan Inggris merayap menuju kejayaan, kini Amerika juga turut menggali masa depannya (menuju kenangan). Peradaban bangsa tumbuh dan berkembang, untuk berakhir menjadi kenangan. Tak lebih.
Kekuasaan; otoritas kebenaran yang mereka ciptakan sendiri pun juga tak mampu melampaui kenyataan, lenyap bersamaan dengan kematian yang menjemputnya, kesemuanya sirna, harapan untuk menutup kenyataan hanyalah sebatas upaya menghapus ketidaktahuannya sendiri. Tetapi bagaimana mungkin untuk tidak menganggap mereka sebatas bertengkar melawan ketidaktahuannya?
Sebuah pengantar menarik dari Erich Fromm, dalam karyanya, The Revolution of Hope: Towards a Humanized Tegchnology, mengingatkan tentang keharusan-sepenuhnya menerima ototitas Tuhan. Bagi Fromm, siapa yang tidak menerima otoritas Tuhan akan menghadapi tiga pilihan, yaitu; (1) relativisme total yang nilai-nilai sepenuhnya urusan pribadi; (2) nilai tergantung kepada masyarakat, yang pasti nilai-nilai yang dominan akan berkuasa; dan (3) nilai tergantung pada kondisi biologis, sehingga Darwinisme sosial, egotisme, kompetisi, dan agresivitas akan dianggap sebagai kebajikan.
Tentu saja satu-satunya musuh manusia adalah ketidaktahuan, bahkan menjadi musuh yang tak akan pernah bisa dilihatnya, dari sanalah penderitaan terus terjadi. Manusia menjadi serakah, hanya karena ia tidak mengerti; manusia berebut-menguasai tanah sebagai sumber kehidupan karena tidak mengerti bahwa pada akhirnya tanah yang dibutuhkan, hanyalah dari kepala hingga ujung tumitnya; manusia bertengkar tentang kebenaran hanya sebab lebih dulu ragu oleh kebenarannya sendiri; manusia saling memberangus satu sama lain hanya sebab tidak mengerti betapa fananya kekuatan, kekayaan, dan kemegahan.
Tidak ada muara keserakahan selain penderitaan; kesia-siaan. Suatu kebiasaan buruk yang benar-benar telah melampaui umur manusia. Tentu bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir kecil manusia yang serakah. Tapi tetap saja selalu ada manusia yang senang menciptakan kerumitannya sendiri, yang bahwa manusia adalah satu-kesatuan yang saling terhubung, bahwa penderitaan yang dialami sebagian manusia selalu menuntut perhatian dari sebagian lainnya, dan keduanya sama saja menguras energi.
Dan benar saja bahwa tidak cukup banyak manusia yang mampu menahan keinginan, sebab kehampaan adalah hukum yang berlaku, atau mungkin tidak mengerti bila buahnya adalah keselamatan. Inipun kisah umat manusia. Kita bisa melihat bahwa sebuah peradaban, telah dimulai dari ketidaktahuan, dan karena itu pula berselisihnya paham tidak juga dapat dihindari, yang pada gilirannya menjadi bencana kemanusiaan.
Tentu kini kita telah berada dalam periodeisasi terakhir perjalanan umat manusia, dimana nilai, sebuah paham; pengetahuan telah menyelimuti kehidupan manusia. Sedang peradaban, tidaklah lebih seperti tumbuhnya seorang anak, bagaimana ia akan melewati fase egois, tidak mau mengalah dengan anak lain, segala keinginannya harus selalu dipenuhi, tidak memiliki empati terhadap orang lain. Lalu ia melalui masa remaja yang penuh konflik, masalah dan ia sendiri tidak mampu mengatasinya. Secara perlahan dan pasti, masa berubah, anak itu kini tumbuh dewasa, tentu tidak mudah untuk melupakan dan meninggalkan masa lalu yang begitu sulit. Hal itu tentu harus kembali pada dirinya, bagaimana kita akan menciptakan kehidupan selanjutnya.
Kemajuan perabadan perlu menuntut hal yang sama pada setiap manusia, tidak bisa kita membiarkan sebagian tetap berada dalam hamparan ketidaktahuan; hal yang tidak akan mungkin tergapai tanpa pemahaman bahwa, kemajuan hanya akan terjadi pada hari dimana kekuatan cinta mengalahkan kecintaan akan kekuasaan, dan dunia akan mengenal kedamaian. Tidak lagi peduli seberapa dahsyat sebuah teknologi memproduksi kecemasan, hal utama manusia dimasa depan hanyalah harapan dan kasih sayang.
Referensi:
- “Selain kepastian kita juga butuh pengertian, pengertian untuk menerima ketidakpastian”. Suatu konsepsi yang dibangun berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 216.
- Relasi pengetahuan dan kekuasaan bagi M. Foucault terpilin dalam kesatuan tunggal. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan (Vice versa). Demikian kebenaran tidak juga lain adalah hasil relasi kekuasaan, kebenaran merupakan hasil produk kekuasaan yang memiliki semacam politik kebenarannya masing-masing.
- Erich Fromm, The Revolution of Hope: Towards a Humanized Tegchnology, tentang keharusan-sepenuhnya menerima ototitas Tuhan.
- Bertrand Russell, Kekuasaan (Sebuah Analisis Sosial dan Politik).
- Leo Tolstoy, Berapa Luas Tanah Yang Dibutuhkan Seorang Manusia.
- Noam Chomsky , How The World Works (Taktik Licik Rezim Zalim).


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co Server
Server






