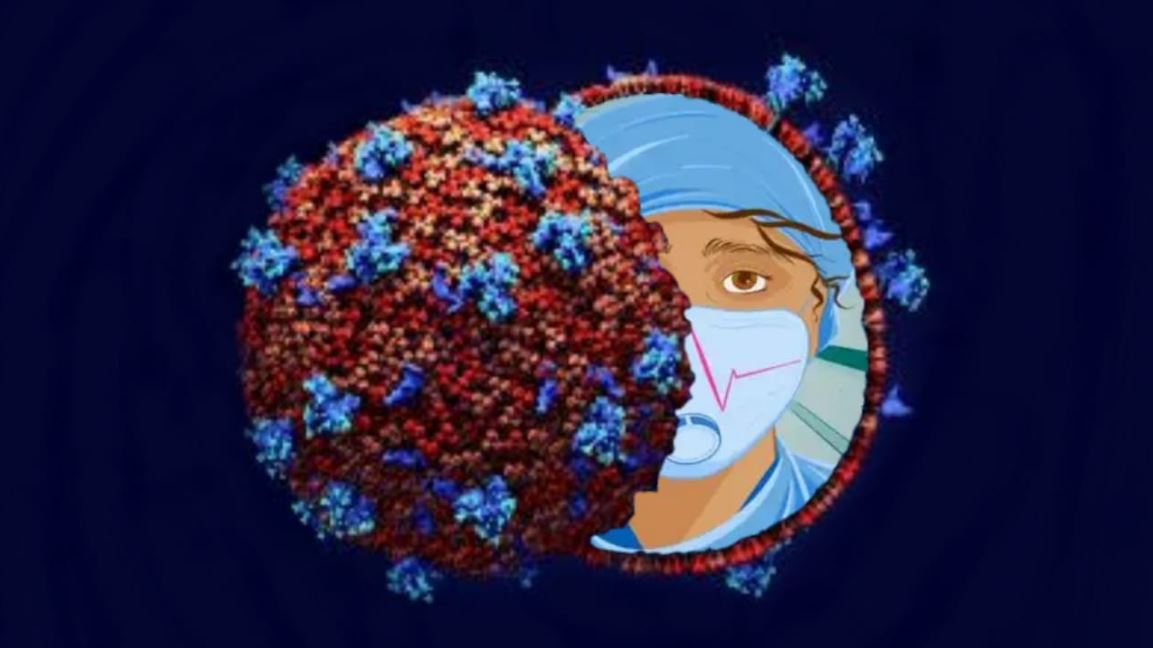
Penyair, Puisi, Masyarakat dan Hawar Virus Korona

Lahir di Gresik, nomaden, pecandu kopi, arbitrer seperti bahasa, suka catur, dan kerap menulis.
Ada yang mengatakan, puisi lebih berurusan dengan persoalan elite dan personal, Platon misalnya. Muridnya, Aristotle, mengatakan puisi adalah tiruan (mimesis) dan universal. Lalu jauh setelah itu, George Lukacs meluaskan pandangan Aristotle, bahwa puisi itu memang wajib menyatakan hal-hal universal, dan itulah sebabnya puisi lebih bijaksana dibanding sejarah. Artinya, puisi itu tidak sekedar meniru watak, tokoh, situasi dan ekspresi, ide, pemikiran dan peristiwa begitu saja, namun juga harus ada unsur sastrawi (das Typische) sekaligus bersifat universal (das Gesetzmaessige).
Dilema hadir–terutama bagi penyair yang mempelajari marxisme atau realisme: puisi (atau kesusastraan) harus mencerminkan kenyataan, artinya kenyataan lebih dulu baru puisi lahir, atau puisi dulu baru menjadi kenyataan–atau mungkin pula tidak menjadi kenyataan sama sekali. Dilema ini sebenarnya sebenarnya adalah dilema usang, meskipun masih akurat sampai sekarang. Jutaan diskusi dan perdebatan terbentang. Misalnya saja, di Indonesia, jika boleh disebut di sini: Lekra dan Manikebu.
Di awal tahun 2000-an, dunia puisi Indonesia kembali riuh oleh perdebatan lain terkait dengan kemajuan teknologi: sastra siber dan nonsiber. Perdebatan itu bermula dari situs yang dikelola Yayasan Multimedia Sastra (YMS) sebagai wadah berkarya. Di satu pihak, ada yang beranggapan kehadiran sastra siber adalah hal yang positif; di pihak lain, sastra siber dianggap sebagai “tong sampah” karya yang tidak layak masuk penerbit–terkait argumen-argumen dari perdebatan ini, bisa dibaca buku Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk.
Lalu di tahun 2014-an, dunia sastra Indonesia, terutama puisi, kembali bergejolak dengan hadirnya puisi esai–puisi catatan kaki atau puisi panjang-berbabak atau drama-prosa-cerita-yang-dipuisikan–yang digalakkan oleh dedengkot LSI. Tapi apakah keriuhan dunia puisi dan para penyair itu punya hubungan atau pengaruh dengan kondisi riil masyarakat? Terutama, di tengah hawar virus korona ini, bagaimana kabar puisi, di mana para penyair?
Penyair, Puisi dan Masyarakat Indonesia
Ada banyak tonggak sejarah sastra (khususnya puisi) di Indonesia. Tidak mungkin ditulis di sini semua: mulai dari pembebasan konvensi puisi lama–pujangga baru dan seterusnya; pembebasan isme dan struktur puisi–nama Taufiq Ismail harus disebut di sini; lalu pembebasan kata dari makna dari Si Tukang Mantra Sutardji; dan seterusnya hingga puisi esai–atau bahkan puisi IG kalau boleh disebut di sini.
Dari banyaknya tonggak sejarah puisi Indonesia itu, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah apakah arus sejarah dunia puisi Indonesia berdiri sebagai runtutan gejala yang berdiri sendiri, ataukah memiliki kaitan–erat atau tidak–dengan keseluruhan proses masyarakat Indonesia? Mudahnya, apakah ia menentukan, atau justru ia malah ditentukan oleh suatu kondisi masyarakat yang lebih menyeluruh?
Menjawab pertanyaan ini berarti sama saja kembali pada perdebatan di awal – universal atau personal. Dan jawaban ini akan menuntun kita pada blok-blok atau isme-isme tertentu. Oleh karenanya, pertanyaan itu baiknya diperiksa dengan yang lebih ‘demokratis’: bahwa puisi, seperti halnya kesenian pada umumnya, merupakan hasil dari proses kreatif; dan proses kreatif harus merdeka–bahwa kemerdekaan menulis puisi adalah hak segala penyair.
Sepintas, tema kedaulatan proses kreatif lebih sering diletakkan di wilayah eksternal dan jarang diletakkan di wilayah internal. Ini artinya lebih digaungkan perlawanan terhadap kekuatan dari luar kesusastraan dibanding di dalam kesusastraan. Maksud dari wilayah eksternal di sini misalnya teknologi, sensor, momentum hari besar nasional, peringatan kematian seseorang, dan sebagainya. Sementara wilayah internal di sini misalnya bentuk, tema, substansi, genre dan sebagainya. Jika meminjam istilah dari Bourdieu, wilayah eksternal ini bisa disebut sebagai medan sastra dan wilayah internal inibisa disebut dengan medan nonsastra (Lihat Wahmuji, 2015 dalam Skandal Sastra – yang mengulas bagaimana gawatnya hubungan medan sastra dan medan nonsastra).
Akan tetapi, tema ini, pada akhirnya, kurang (hampir tidak mungkin) membawa kita pada pengertian kita terhadap kondisi personal penyair dalam proses kreatifnya. Tema ini juga tidak memberi penjelasan seberapa jauh penyair berdaulat dari hingar-bingar di luar yang membentuk dan mengkondisikannya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka kita harus pindah tempat; kita tidak harus melihat bagaimana penyair melindungi diri dari hingar-bingar dunia luar. Akan tetapi kita harus melihat bagaimana penyair mendengar, melihat, memahami dan menguasai hingar-bingar dunia luar itu dalam dirinya, agar kemunculan proses kreatifnya sesuai dengan kemerdekaan manusiawinya yang paling mandiri.
Mengingat tulisan Emha (1984), inilah kemudian yang menentukan apakah ia disebabkan atau menyebabkan kondisi eksternalnya. Mudahnya, apakah seorang penyair bisa berbuat untuk lingkungannya, ataukah justru diperbuat. Kedaulatan proses kreativitas penyair di sini bukan terutama bahwa ia merdeka untuk mengekspresikan diri, melainkan bahwa sumber kreativitas penyair itu sendiri harus merdeka.
Kini, puisi atau kesusastraan kiwari hidup dalam masyarakat baru: kaum rebahan, kaum milenial, generasi Z. Masyarakat kiwari punya cara-cara dan piranti spesial yang baru untuk lebih bisa menikmati proses kreativitasnya. Buku puisi menjadi e-book puisi. Puisi adalah ngonten. Buat puisi romantis dibilang bucin. Ada lomba puisi, hadiah jutaan, lalu mendadak penyair. Ada agenda menulis puisi bersama, tema Kapitalisme Progresif, gratis, hadiahnya dibukukan ber-ISBN, lalu minta tolong kawan untuk buat puisi, dan forward. Tidak masalah, selama sumber kreativitas penyair itu sendiri berdaulat. Ini adalah persoalan tersendiri bagi sang penyair, dan hanya penyair yang tahu. Berdulatkah kau dalam puisimu, duhai penyair?
Persoalan lain bagi masyarakat kiwari adalah doktrin spesialisasi atau pembagian kerja: kompetensi adalah mahakuasa. Hanya dokter ‘saja’ yang punya kuasa penuh untuk bicara tentang kesehatan. Psikologlah yang paling bisa dipercaya pendapatnya tentang masalah-masalah percintaan, eh, kejiwaan maksudnya. Kita sering mendengar, “Biarkan penyair dalam keheningan kata-kata”; “Pemilu itu politik, bukan urusan agama”; “Jangan mengutuk presiden dalam puisi”; “Perang itu soal militer”; atau “Biarkan polisi yang mengamankan.”
Oh, bukankah harga berambang pada mulanya adalah karena politik? Bukankah harga 200 gram buku puisi ditentukan oleh pasar, harga kertas, biaya cetak, ongkos produksi – mungkin branding penulis, dan bukannya dari kualitas-inheren dan ‘oh-effect’dari puisi itu? Atau sekarang, di tengah hawar virus korona ini, bukankah harga masker dan penyanitasi tangan menjadi mahal karena ada pengaruh dari politik-ekonomi?
Perlu ditekankan, ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau menyudutkan satu pihak tertentu. Tidak. Kita tentu, dan harus sepakat, bahwa dokter dan tenaga medis adalah garda terdepan dalam perang melawan virus korona. Kita tak mampu membalas mereka – bahkan dengan jutaan puisi sekalipun. Mereka adalah pahlawan-dalam-arti-leksikal. Namun apakah kita hanya bergantung pada para pahlawan di tengah hawar virus korona ini? Jika begitu, Anda durjana! Memang, dokter dan tenaga medis adalah spesialis penyelamat kehidupan manusia. Beliau-beliau mempunyai kapasitas dan kualitas dalam menyelamatkan nyawa kita. Namun siapa pun kita, kewaspadaan dan usaha kita sendirilah yang menjadi kunci keselamatan kita. Dokter memberikan saran, siapa pun kamu, wajib menuruti.
Maksudnya di sini adalah, kembali mengingat tulisan Emha (1984), pada akhirnya kita harus kembali ke hulu, yakni keseluruhan tatanan menyeluruh dari kehidupan. Seperti juga kalau kita melihat di saat hawar virus korona ini, bahwa secarik puisi pun mengemban suatu nilai kemanusiaan yang terkandung dalam hal kesehatan, dan menjaga kesehatan pun mengandung disiplin estetika. Susunan kata puitis, atau sebuah puisi yang-bagus, memiliki cara tersendiri dalam menjaga kesehatan tubuh, pikiran dan jiwa manusia. Yakinlah, puisi punya cara yang magis untuk membuatmu bahagia. Dan bukankah sistem imun tubuh kita akan meningkat jika kita bahagia?
Puisi dan Virus Korona
Para (kritikus) sastrawan mengemukakan bahwa karya sastra adalah ekspresi atau refleksi zamannya. Dan dalam situasi terkini, di mana seluruh dunia berperang dengan hawar virus korona, sudah banyak puisi yang tercipta yang bertema virus korona–atau setidaknya berhubungan. Gus Mus, pada tanggal 18 Maret, mengunggah puisi di Instagram berjudul Talbiyah dalam Kesendirian. Puisi itu menceritakan sikap tawakkal penulis dan harapan terkait sepinya Masjidil Haram karena virus korona. Hingga tanggal 24 Maret, puisi yang diunggah di Instagram itu sudah mendapatkan ‘like’ 38 ribu lebih, dengan 372 komentar.
Wakil Bupati Lumajang, Indah Masdar, juga mengunggah puisi di akun Facebook miliknya yang bertitimasa 22 Maret 2020. Ia juga mengekspresikan harapan dan sikap tawakkal kepada Tuhan atas hawar virus korona. Hingga 24 Maret 2020, puisi itu mendapat tanggapan lebih dari 450 akun, dikomentari 155 akun, dan 56 kali dibagikan. Baru-baru ini, seorang pejabat yang positif COVID-19 juga mengungah puisi di linimasa Facebook. Kata-katanya menyentuh. Ada getar ketika membaca puisi itu.
Selain Gus Mus, Wakil Bupati Lumajang, dan pejabat yang positif COVID-19, tentu ada banyak warganet yang ikut mengekspresikan perasaan atau pikirannya dalam bentuk puisi melalui media sosial atau yang lain. Di internet akan banyak kita temukan puisi-puisi-virus-korona.
Lalu di skala internasional, kita bisa melihat bagaimana Sang Pahlawan Virus Korona, Li Wenlian, dalam akun Facebook-nya (Dencio Acop) juga menulis catatan+puisi sebagai pesan terakhirnya sebelum meninggal. Ia menulis:
Integritas tak cukup menjadi kebaikan;
meskipun tersesat;
namun pantang untuk mundur,
Siapa aku; hingga aku memilih negara ini?
Triluyunan keluhan menggema; menunggu pertarungan–
menangis seperti hujan mendongak ke langit.
(Note: Bait ini adalah sebagian catatan+puisi yang disadur penulis dari bahasa Inggris. Tulisan aslinya beraksara dan berbahasa Cina)
Unggahan itu disukai 53 ribu lebih, dikomentari 10 ribu lebih, dan dibagikan 58 ribu lebih. Dan catatan+puisi dari Li Wenlian itu, menurut banyak kantor berita, telah membuat pemerintah Cina sadar bahwa virus korona adalah virus yang berbaya. Lalu Pemerintah Cina memutuskan berperang melawan virus korona secara bersama-sama dan membuka diri pada dunia.
Tidak usah muluk-muluk mengatakan puisi bisa mengubah dunia, atau jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya (JFK). Apa yang bisa kita catat adalah puisi punya tempat di sini. Bodo amat, dengan label puisi siber, puisi realisme, puisi pamflet, puisi IG, dan jutaan label-label lainnya.
Intinya, di hawar virus korona ini, puisi masih mampu menyentuh jiwa manusia dengan caranya yang magis. Dan kemerdekaan dalam melakukan proses kreatif penciptaan puisi dari penyair masih hadir. Oleh karenanya, ia punya peran juga di sini, meskipun tentatif.
Penyair dan Virus Korona
Sejauh ini, penulis hanya bisa menemukan satu acara menulis puisi yang bertemakan virus korona, yakni Puisi Melawan Corona, diadakan oleh Yayasan Dapur Sastra Jakarta. Poster acara itu diunggah melalui Instagram @lingkarpenulis. Yang menarik, dalam pendahuluan acara, ditulis:
Bagaimanakah peran penyair? Para penyair tentu tidak akan terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 di lapangan. Tetapi para penyair harus mampu menyatukan semua energi positif bangsa dengan cara menggugah kesadaran bahwa ini adalah perang kita bersama.
Ya. bagaimana peran penyair terhadap virus korona? Atau bahkan, mengubah sedikit pertanyaan arkais: bagaimana cara penyair menyelamatkan Indonesia dari hawar virus korona?
Pertanyaan ini hanya dijawab dengan menawarkan penyair, baik zaman-old maupun zaman-now, bahwa mereka sebaiknya bekerja sama dengan penerbit, atau NGO, LSM, atau lembaga apapun untuk mengadakan lomba atau program puisi tingkat nasional yang dibintang tamui oleh penyair-penyair ternama; lalu buku itu dicetak digital; dijual digital; lalu keuntungan penjualan itu digunakan untuk membeli masker, penyanitasi tangan atau APD lainnya; lalu membagi-bagikan pada mereka yang membutuh secara gratis. Atau lebih mudahnya, langsung transfer hasil penjualan buku-puisi-digital itu kepada rumah sakit atau puskesmas yang membutuhkan bantuan. Ingat, jangan remehkan kaum milineal. Bagi kaum milenial, semua bisa jadi uang. Kaum milenial selalu punya cara unik menghasilkan uang. Cocot ambyar saja bisa jadi uang, apalagi puisi.
Atau mungkin, opsi lain: membuat vlog seperti yang dilakukan oleh Najwa Shihab yang membuat video menyanyi bersama Rumah Kita oleh para artis. Tinggal diganti konsepnya jadi pembacaan puisi atau deklamasi, dikhususkan untuk para dokter dan tenaga medis. Mumpung, Indonesia masih punya segudang penyair berkualitas dan ternama, meskipun penyair-penyair milenial juga tak kalah kualitasnya. Membuat Podcast puisi juga bisa. Atau mungkin dengan membuat video TikTok deklamasi puisi, daripada-daripada~
Tidak apa-apa. Bagus. Bebaskan kreativitasmu! Biarkan publik yang menilai. Lagipula, bukankah kita semua rindu mendengar lantunan puisi yang menggugah jiwa di saat hawar virus korona ini, seperti Rendra misalnya?
Namun, ketika cara-cara itu dilakukan, dalam rangka mengambil peran dalam usaha membantu hawar virus korona, terkesan kurang sreg: pertama, puisi bukan lembaga donasi. Puisi, dengan segala kelemahan dan keterbatasan jangkauannya, paling banter bisa menyumbang pada sejarah dan peradaban manusia; kedua, perlu dibedakan konteks proses penyembuhan virus korona secara medis – dalam artian obat-obatan, dengan proses penyembuah nonmedis.
Mengikuti Rendra (2001), tugas penyair serta perannya dalam permasalahan sosial adalah menjadi imbangan spiritual bagi operasi dari lembaga sekuler. Rendra menulis:
~ keadaan peradaban yang ideal adalah adanya keseimbangan yang dinamis antara suara spiritual dan operasi sekuler. Sebagaimana juga dalam hidup manusia secara pribadi: roh dan badan itu sama pentingnya. Dinamika pembangunan mengandung dua aspek yang sama pentingnya, yaitu aspek struktural dan aspek mental. Peran penyair adalah memupuk dinamisme mental masyarakat (hlm. 4-5).
Dari kutipan itu, tampak jelas bagaimana peran penyair di tengah hawar virus korona ini. Penyair adalah penjaga mental masyarakat. Kantor berita atau media-media informasi lain yang merupakan tempat yang efektif untuk menjaga mental masyarakat, tak bisa mengisi peran itu. Malahan berita-berita semakin membuat kita gelisah, terkejut, dan panik.
Dengan demikian, seperti yang sudah disebutkan di atas, ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh penyair, baik zaman-old maupun zaman-now. Namun semua itu harus lebih ditunjukkan pada aspek mental masyarakat, bukan pada nilai ekonominya. Jikalau ada nilai ekonomi, semoga ada, itu adalah bonus. Hoi, penyair. Bangun!*
Sumber Bacaan
| Emha Ainun Nadjib, 1984. Sastra Yang Membebaskan: Sikap terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia. Yogyakarta: PLP2M. |
| Jamal D. Rahman, dkk, 2014. 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. |
| Rendra, 2001. Penyair dan Kritik Sosial. Yogyakarta: Kepel Press. |
| Saut Situmorang (ed.), 2004. Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk. Bandung: Penerbit Angkasa. |
| Wahmuji, AS. Laksana, dkk, 2016. Skandal Sastra: Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh dan Kriminalisasi Saut Situmorang. Yogyakarta: Indie Book Corner. |


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





