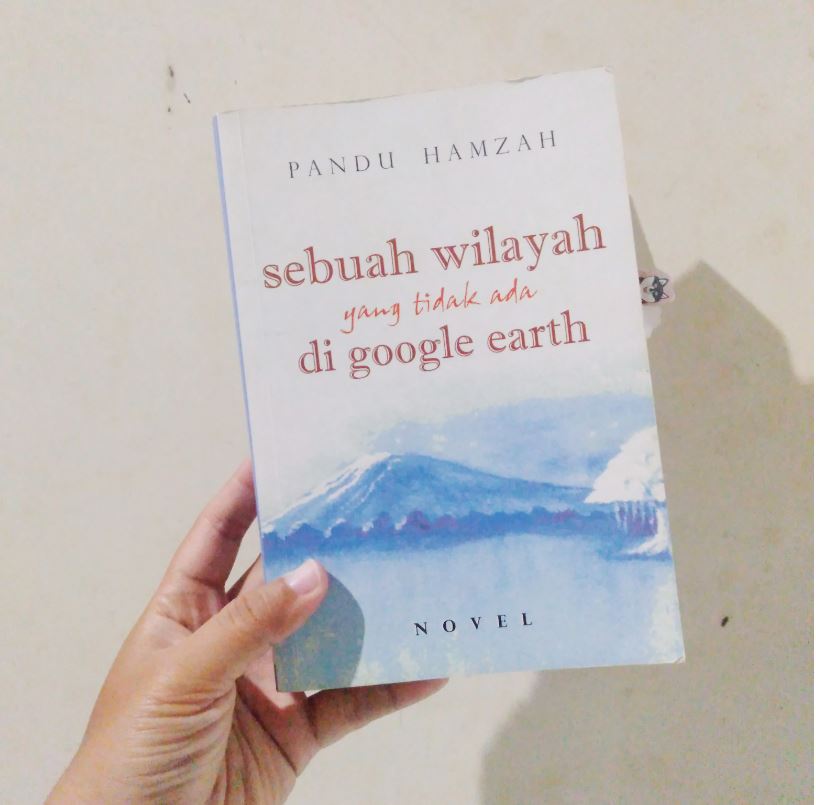Berabad-Abad Kemudian | Puisi-Puisi Dadang Ari Murtono
Berabad-abad Kemudian
Berabad-abad kemudian mungkin mereka akan bertemu lagidalam sebuah mimpidengan latar yang samar.Barangkali sebuah kamar dengan dinding pucat
atau lamin dengan lantai mencuat.
Meski bisa saja mereka akan berjumpa di sebuah padang
gersang
yang tak pernah benar-benar ada.
“Akhirnya aku menemukanmu,” itu mungkin yang dikatakan
si hantu dari Huang Lirung, Hantu Mulaang yang besar dan
bersemu murung.
Dan si perempuan – barangkali ia masih bernama Apeq, meski
bisa saja ia telah berganti rupa menjadi siapa saja –
mundur sedepa.
“Aku perempuan bersuami,” ia menjawab. “Aku perempuan terhormat.”
“Tapi aku mencintaimu,” si hantu kembali berkata.
“Sejak ratusan tahun lalu, sampai ratusan tahun lagi.”
“Tapi aku perempuan bersuami,” perempuan itu kembali
undur sekali. “Dan aku perempuan terhormat.”
“Tapi aku mencintaimu,” ulang Hantu Mulaang.
“Sejak ratusan tahun lalu, sampai ratusan tahun lagi.”
Itu, sepertinya, akan menjadi adegan yang terus berputar
hingga ratusan tahun lagi.
Tapi mimpi, bagaimana pun, akan berakhir pada sebuah pagi.
Dan itulah yang terjadi,
yakni ketika wangi fajar merambat ke ujung perdu
dan si perempuan membuka mata dan ia saksikan hijau
dari wajah suaminya – apakah si suami masih bernama Nalau,
atau apakah juga sudah berganti paras dan kilau? –
dan si perempuan berbisik kepada si lelaki,
“Kita butuh sebuah lagi Patung Jelemaeq untuk menipu hantu-hantu.”
Meski begitu, ketika siang datang,
di ladang, di antara tugal padi gunung,
ia terkenang juga mata berlinang si Hantu Mulaang.
Dan ia gamang tentang apa yang sebenarnya ia rasakan.
Perjuangan
Seorang tua dari milenium lalu bercerita perihal
perjuangan:
Ada seekor babi berjalan jauh, mendaki ke Apau Lagaan,
menghadap Amai Tingai, dewa yang murah hati.
Ia ingin sayap, sebab ia ingin terbang seperti unggas, sebab
ia ingin menjelajahi langit luas, memandang semesta hijau dari
ketinggian, memetik buah-buah segar agar tak perlu lagi
memungut buah-buah kisut busuk di permukaan tanah.
Dan ia mendapatkannya. Sepasang sayap liat dari lilin sarang
lebah. Dan ia terbang. Terbang seperti yang ia harapkan.
Kemudian matahari memanggilnya dari balik segumpal awan
yang serupa enggang. Dan ia melambai. Ia akan datang.
Ia terbang ke atas. Semakin tinggi. Semakin mendekati matahari.
Semakin mendekati pusat api.
Dan lilin itu meleleh. Meleleh seperti seharusnya tiap lilin yang
terbakar.
Dan ia jatuh
menghunjam bumi.
Dan babi itu mengerti apa artinya.
Babi Samaat
Perempuan itu menulis dalam sebuah email kepada lelaki yang
ia kenal melalui mIRC: aku pernah mendengar seekor babi yang
menelan air kencing seorang raja. Dan sembilan bulan kemudian,
ia melahirkan seorang putri. Yang tercantik dari semua yang tercantik.
Yang bernaung di bawah lindungan malaikat murung. Sebab sekian
tahun kemudian, seekor anjing membuahinya. Tapi mungkin ia bahagia,
ketika itu, sebab mungkin ia cintai pula si anjing. Namun jauh setelah itu,
seorang anak, seorang anak dari percintaan mereka, memanah si anjing
dan menyuguhkan jantung si anjing untuk menu lauk makan malam.
Si anak yang segera terusir. Namun ia, si anak itu, akan kembali, sekian
lama kemudian. Untuk menikahi si ibu. Memaksa menikahi si ibu.
Itu cerita yang sedih, balas si lelaki. Itu cerita yang sangat sedih.
***
Dan keesokan harinya, lewat Yahoo Messenger, si lelaki bercerita.
“Di sini juga ada seekor babi. Sayangnya, ia tak mengenalmu. Dan karena
itu, ia tak tahu betapa bahaya meminum air kencing orang berada.”
“Aku tak pernah suka cerita sedih,” kata si perempuan. “Cukup Sumbi
dan Anjing Tumang, kukira.”
***
Tapi lelaki itu terus bercerita.
“Mungkin hari hampir senja dan cuaca berwarna sepia, waktu itu. Aku
tak pernah tahu persisnya. Namun itu akan membuat semua seperti
adegan dalam sebuah film yang abadi. Meski barangkali, memang tak
ada yang perlu abadi.”
Dan si perempuan mendengarkan.
“Ia bernama Babi Samaat. Si babi itu maksudku. Yang haus dan menemukan
setangkup air kencing Ama Aji di atas daun toyoop. Dan seperti yang kau duga,
sembilan bulan kemudian, di sudut hutan, dalam seliang gua gelap, ia melahirkan
seorang putri. Yang tercantik dari semua yang tercantik.”
“Tapi,” perempuan itu memotong. “Sumbilah anak babi yang paling cantik.”
“Tapi semua orang punya ukuran sendiri-sendiri,” jawab si lelaki.
“Dan di sini, si yang tercantik itu bernama Buncuuq.”
Dan si perempuan mengangguk.
***
“Sepertinya mereka akan bahagia,”
kata si lelaki.
Tapi tidak,
sebab bertahun-tahun kemudian, dari gelap gua, si babi mendengar
suara gong dan gendang. Dan ia tahu apa artinya.
Upacara belian Ama Aji
di mana ia harus datang
menyerahkan serat-serat dagingnya
pada pesta yang diwarnai darah.
Dan ia datang.
***
“Kenapa ia harus datang?” Si perempuan bertanya.
“Bukankah ia punya pilihan?”
Si lelaki menggeleng. “Aku tidak tahu,” katanya.
“Aku tak pernah menjadi babi. Aku tak pernah menjadi babi yang
menerima panggilan upacara belian dari Ama Aji.
Tapi bagaimana pun, itulah yang terjadi.”
***
“Dan Buncuuq,” kata si perempuan. “Apa yang terjadi kepadanya?”
“Tentu saja ia menangis. Tapi ibunya telah berpesan agar ia mencuri
jantung si ibu dan menanamnya di mulut gua.”
***
Dan itulah yang dilakukan si anak.
Keesokan harinya, ketika Buncuuq terbangun dan
berharap semua hanyalah
mimpi buruk,
ia melihat jantung ibunya tumbuh
jadi beringin gani taliq bulau
yang berbuah helai-helai sutra
sangat banyak.
Sangat banyak.
***
“Dan seorang anak ketua suku,” kata si lelaki, “selalu ada anak ketuasuku yang tampan rupawan dalam kisah seperti ini, menemukan
si Buncuuq tengah menjuluk helai-helai sutra.
Dan mereka saling jatuh cinta.
Dan mereka menikah.”
***
“Begitu saja?” si perempuan bertanya.
Dan si lelaki menggeleng.
“Namun sebelum itu, si perempuan harus membuktikan bahwa ia suci.
Maka orang-orang meletakkan delapan lembar daun olukng
lamak dan si perempuan menginjaknya.
Dan daun-daun itu berubah menjadi piring.
‘Ia keturunan mulia,’ orang-orang berkata.”
***
“Kenapa harus perempuan yang diuji?”
si perempuan mengeluh. “Kenapa harus?
Seperti Sinta dalam unggun api,
seperti Buncuuq si putri babi?”
***
“Bagaimana pun, ini cerita yang bahagia,” kata si lelaki,
“Sebab setelah itu mereka kembali ke gua dan menemukan
beringin itu memekarkan buah
sebiji
besar
sangat besar
dan mereka memetiknya
dan mereka membelahnya
dan di sanalah mereka melihat si ibu,
si babi ibu, dalam wujud perempuan cantik,
yang tercantik dari yang tercantik
yang berkata, ‘berbahagialah anak-anakku’.”
***
“Itu cerita yang membahagiakan,” kata si perempuan.
“Bahkan seekor babi bisa bahagia di sana.”
Lantas, sebelum mereka mematikan Yahoo
Messenger, si perempuan berkata, “Kapan kau akan
membawaku ke tempat di mana semua makhluk
bisa bahagia?”
Dan si lelaki menggeleng.
“Ada memang hal-hal yang tak bisa sepenuhnya
bahagia. Aku dan kamu misalnya. Ada memang
hal-hal yang bisa bahagia. Istriku dan suamimu,
misalnya.”
Perempuan Itu Mematikan Rokok
Perempuan itu mematikan rokok putih di atas segumpal
tisu basah, lalu menatatap si lelaki. “Apa yang akan terjadi
setelah ini?” Ia bertanya. “Aku tak tahu,” kata si lelaki. “Tapi selalu
ada lebih dari satu kemungkinan.
Misalnya: aku akan menjelma Jaka Tarub. Dan kusembunyikan
sayapmu di dalam lumbung, di bawah tumpukan padi, agar kau
tak bisa lari. Sampai suatu saat aku akan melanggar ucapanmu.
Aku akan membuka tanakan nasi dan kudapati kau hanya
memasak satu butir beras. Lantas keajaiban berakhir. Dan
kau mulai memasak sekian ikat padi setiap kali. Dan pada suatu pagi,
ketika lumbung tak lagi berisi, kau temukan sayapmu. Dan kau pergi.
Seperti kehendakmu. Ke bulan. Sebab kau yang telah
ternoda, tak mungkin kembali ke surga.”
“Dan yang lain?” si perempuan bertanya.
“Aku akan menjelma Petawal,” kata si lelaki. “Anjingku akan menemukan
sayapmu, dan tak seperti Tarub yang lihai menipu, kukatakan
kepadamu semua sedari mula. Tapi bagaimana pun,
kita akan menikah.
Kita akan bahagia. Kita akan punya seorang anak yang tak bernama sampai
usia tujuh bulan.
Dan di situlah masalahnya.
Sebab pada upacara pelas tahun, aku akan pergi berburu
dan orang-orang akan memaksamu menari tarian langit,
sebab mereka tahu kau bidadari.
Dan kau tak akan mau,
tapi kau tak bisa mengelak.
Dan karena itu, kau kena tuhing tua.
Kau melayang karena kau harus melayang.
Kau terbang ke langit tinggi dan surga menolakmu
sebab bagaimana pun, kau tak lagi suci.
Tapi aku akan mengejarmu
bersama si bayi tak bernama.
Dan kau terus melayang.
Dan aku terus mengejarmu.
Dan di Pulau Sebatik, di perairan Pulau Sebatik, akhirnya
kudekap kau. Aku, kau, dan si bayi tak bernama.
Dan kita bergulung dalam gelombang asmara,
menjelma dulun, menjelma tiga ombak
yang beriringan selamanya, terus beriringan selamanya.”
“Dan mana yang kau pilih?” si perempuan bertanya.
“Tergantung kepadamu,” kata si lelaki.
Dan si perempuan berjalan ke luar kedai kopi.
Langit seakan memanggil, meski mungkin itu hanya ilusi
dari terik matahari.
Namun si perempuan mengembangkan sayapnya.
“Mungkin aku akan sampai ke bulan,” katanya.
“Mungkin juga hanya melayang-layang sampai Pulau Sebatik.”
Itu pertemuan terakhir mereka.
Dan tak ada lagi yang tahu di mana si lelaki di mana si perempuan.
Masalahnya: tak ada dongeng yang mengekalkan mereka dan
memberi alternatif ketiga, semisal: sayap itu tak pernah benar-benar
mengembang atau si lelaki yang entah bagaimana turut terbang.
Magrib
Magrib tiba bersama riak kecil yang buyar di tanggul
Mahakam. Dan lelaki itu memandang ke tengah, di mana
empat bulan lalu, seorang perempuan tenggelam dan
tak pernah ditemukan.
Seorang Kutai berkata bahwa naga sungai menjerat si
perempuan. Seorang Banjar bersumpah seekor buaya
kuning yang mengundangnya.
“Padahal ia hanya ingin berenang, pada mulanya,”
seorang lain berujar. “Sebelum arus menyeretnya.”
Namun ada juga, seorang Dayak Bahau, yang yakin
jika perempuan itu hendak menuju Telaang Julaan
agar bisa bertemu almarhumah ibunya.
Dan tak ada yang bertanya pada si lelaki dengan fedora tua
di bawah palem ratu yang menyimpan kalimat terakhir si perempuan
dalam kotak pesan ponselnya.
“Aku akan pergi,” kata perempuan itu, “ke mana saja.
Bersama bayi dalam rahimku
Ke mana saja. Selain ke lelaki serong sepertimu.”
Dan lelaki itu menghela napas.
Di kejauhan, ia lihat riak lembut. Mungkin itu si perempuan
yang tengah memandikan si bayi
meski mungkin itu hanya riak
yang disebabkan angin magrib.
Dadang Ari Murtono, lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Bukunya yang sudah terbit antara lain Ludruk Kedua (kumpulan puisi, 2016), Samaran (novel, 2018), Jalan Lain ke Majapahit (kumpulan puisi, 2019), Cara Kerja Ingatan (novel, 2020), Sapi dan Hantu (kumpulan puisi, 2022), serta Cerita dari Brang Wetan (kumpulan cerpen, 2022). Buku Jalan Lain ke Majapahit meraih Anugerah Sutasoma dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur serta Penghargaan Sastra Utama dari Badan Bahasa Jakarta sebagai buku puisi terbaik Indonesia tahun 2019. Buku Cara Kerja Ingatan merupakan naskah unggulan sayembara novel Basabasi 2019. Buku Sapi dan Hantu adalah juara 3 Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta 2021. Ia juga mendapat Anugerah Sabda Budaya dari Universitas Brawijaya tahun 2019. Saat ini tinggal di Samarinda dan bekerja penuh waktu sebagai penulis serta terlibat dalam kelompok suka jalan.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co