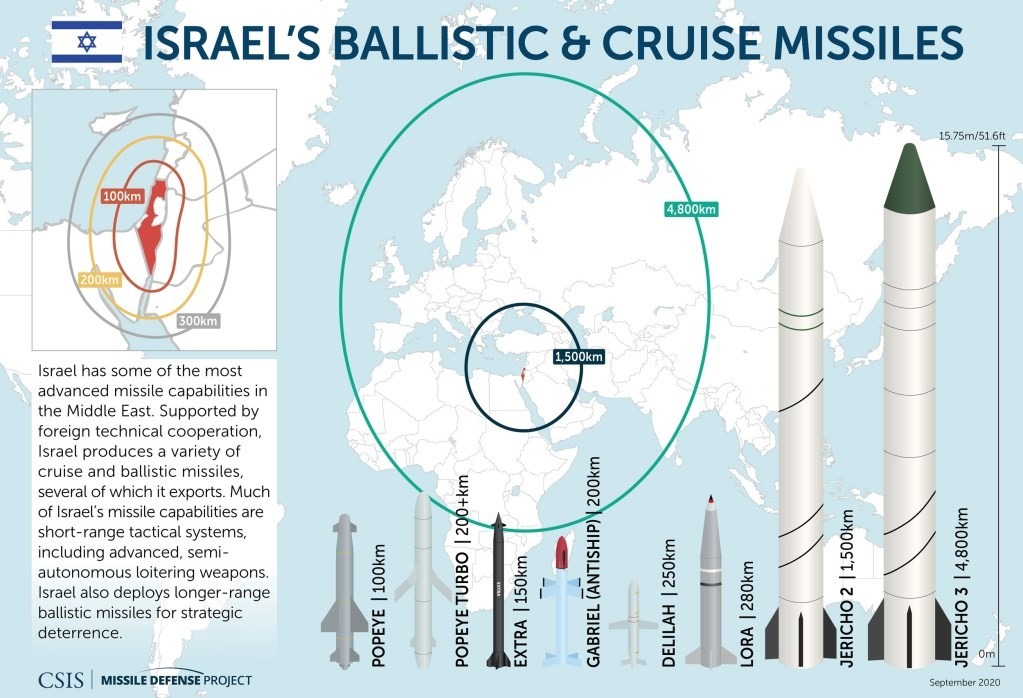Wacana Bentuk Negara dalam Masyarakat Muslim (Perspektif Michel Foucault)
Wacana Bentuk Negara Dalam Masyarakat Muslim (Perspektif Michale Faulcolt)
Oleh : Siti Fatkhiyatul Jannah
(Pengamat Politik Dan Praktisi Kepemimpinan Muslim)
Kitasama.or.id – Ibnu Khaldun Melalui karyanya, Muqodimah berpandangan bahwa landasan awal pembentukan negara (dawlah) adalah ashabiyah (tribalisme), yaitu hubungan pertalian se-darah dalam suku atau sub-suku, atau yang semakna dengannya, misalnya sahabat yang mendapatkan perlindungan atau orang-orang yang terikat perjanjian. Tujuan dari tribalisme adalah superioritas kekuasaan (al-taghallub mulki). Karena wataknya yang seperti itu maka invansi terhadap tribalisme yang lain sering dilakukan untuk memperebutkan tanah dan superioritas kekuasaan tadi, demikian seterusnya hingga terbentuklah sebuah Negara (Dawlah).[1]
Namun demikian ibnu Khaldun belum memberikan tahapan-tahapan yang jelas mengenai proses pembentukan negara secara kronologis. Ia hanya memberikan penegasan pada kebutuhan dan unsur-unsur yang akan membentuk suatu negara.
Elman R. Service meletakkan pembentukan negara pada proses institusionalisasi kepemimpinan pusat. Kepemimpinan merujuk pada kemampuan relatif seseorang atau suatu kelompok untuk memerintahkan kepatuhan dan menundukkan perlawanan. Agar sebuah institusionalisasi berjalan maka organisasi politik harus berkembang sedemikian rupa. Sehingga kekuasaan tidak hanya hidup didasarkan pada hubungan otoritas hierarkis tapi juga oleh otoritas hukum yang mengendalikan monopoli kekuatan fisik.
Institusionalisasi tersebut terbentuk dari sebuah masyarakat yang egaliter (band atau tribe) yang tidak mengenal hierarki, kecuali pucuk pimpinan misalnya kepala suku menuju ke bentuk chiefdom yang telah mengenalkan hierarki kepemimpinan yang fungsional bagi pembagian kerja, harta, dan jasa. Bentuk negara tercapai ketika hierarki pembagian kepemimpinan fungsional semakin komplek, diferensiasi semakin banyak, teritorial semakin luas, dan kekuatan fisik dikuasai oleh kepemimpinan. Fred Halliday menyebut proses ini sebagai pembentukan negara awal.
Secara kronologis Service menegaskan bahwa proses institusionalisasi tersebut berjalan melalui empat tahap[2];
- Tahap Band, disebut juga horde, merupakan kelompok masyarakat pemburu pengumpul yang bergerak. Pada umumnya keanggotaannya berasal dari orang-orang seketurunan berdasarkan perkawinan atau pertalian darah.
- Tahap Tribe, kadang kala disebut masyarakat segmentaris, yakni kelopok masyarakat yang sudah sedikit terorganisir menjadi beberapa segmen-segmen yang berbeda tetapi dipersatukan oleh pertalian darah atau perkawinan.
- Tahap Chiefdom, yaitu merupakan tingkat kesatuan politik yang terbentuk ketika anggota masyarakat sudah semakin banyak jumlahnya dan memiliki komandan permanen (chief) berdasarkan keturunan tetapi belum memiliki birokrasi administratif.
- Tahap State (Negara), dimana masyarakat sudah memiliki tingkat integrasi politik, memiliki organisasi poitik yang terpusat secara permanen, dengan elit penguasa di puncak piramida kekuasaan dan rakyat sebagai bagian terbesar di bawahnya.
Mengkaji Negara tidak bisa dilepaskan dengan masalah pemerintahan. Pemerintah menurut Shively adalah sekelompok rakyat yang didalamnya Negara mempunyai otoritas tertinggi menjalankan aktifitas atas nama Negara[3]. Negara mempresentasikan konsep abstrak sedangkan pemerintah mempresentasikan bentuk kongkret. Otoritas Negara dijalankan oleh pemerintah, fungsi Negara ditegakkan oleh pemerintah, hukum Negara yang dibuat, dideklarasikan dan dilaksanakan pemerintah.[4]
Relasi islam dan Negara menurut Ahmed Vaezi mengemukakan dua aliran terkait relasi Negara atau politik dengan islam, pertama, pendukung relasi islam dan Negara. Sebuah sistem hukum membutuhkan pemerintahan yang akan mengadopsidan seperangkat-seperangkat aparat yang akan mengimplementasikan serta menegakkan sanksi-sanksi. Hukum islam sebagai sistem hukum tentu membutuhkan Negara untuk menegakkannya sehingga dibutuhkan pemerintahan islam[5].
Kedua, aliran yang menolak pemerintahan islam. Ada dua argumentasi yang melandasi penolakannya yaitu pertama, nabi memang membentuk tertib politik di madinah tetapi itu bukan merupakan hubungan instrinsic antara islam dan politik, melainkan karena peristiwa historis semata karena situasi social politik pada saat itu menghendaki terbentuknya tertib politik. Kedua Nabi Muhammad tidak bermaksud mendirikan Negara dan sistem social politik tertentu karena nabi hanyalah seorang Rasul.[6]
Negara Islam kerap kali didefinisikan sebagai sistem hukum yang mengarahkan kualitas hidup dalam masyarakat politik dan organisasi politik menuju pengejawantahan nilai-nilai islam[7]. Vaezi mendefinisikan pemerintahan islam sebagai pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolute dalam islam. Pemerintahan islam berupaya membentuk tertib sosial yang islami, pelaksanaan syariat, sembari terus menerus mengarahkan keputusan politik dan fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai islam.[8]
Awal kemajuan umat Islam ditandai pada tahun 1921 atas gagasan Musthafa Kemal Pasha Kekhalifahan Turki Ustmani yang menjadi kiblat kepemimpinan umat Islam resmi telah runtuh, beberapa wilayah provinsinya terpecah-pecah menjadi beberapa bagian negara kecil yang berbentuk nasionalisme.[9] Pada tahun 1923 Kemal Pasha telah membentuk wilayah disekitar ibukota Ustmani Istanbul, menjadi negara Turki modern.[10] Sedangkan wilayah-wilayah yang lain terpecah-pecah menjadi negara-negara yang didasarkan pada suku bangsanya.
Menjelang keruntuhannya, pada tahun akhir abad 19 M kekhalifahan Turki Ustmani telah menghadapi berbagai tekanan dari dalam maupun luar negeri. Disatu sisi ikut terlibat bersama Jerman di Blok Sentral melawan Blok Sekutu dalam peang Dunia[11], dan di sisi lain menghadapi pemberontakan dari beberapa provinsinya. Salah satunya, wilayah Hijaz dan Nejed berhasil mengalami pergolakan dengan dasyat[12]. Saat itulah terjadi beberapa kali pertempuran antara tentara Ustmani namun pada akhirnya wilayah tersebut berhasil dikuasai oleh klan Saud yang merupakan pemimpin gerakan politik Wahabisme.[13]
Dengan kemenangan tersebut Klan Saud berusaha menghapus tradisi keagamaan yang sudah lama berjalan di tanah Hijaz dengan ajaran baru versi Salafi-wahabi. Beberapa kegiatan keagamaan yang dipandang “tidak murni” Islam dibumi hanguskan. Para ulama hingga mencapai ratusan yang memiliki keyakinan berbeda dengan mereka dibantai[14], penduduk Muslim yang tidak bersalah dibunuh dengan sadis dan beberapa situs bersejarah dan perpustakaan dibakar dan dirusak[15]. Nampaknya suksesi kepemimpinan yang dilakukan Klan Saud lebih banyak melahirkan kehancuran dan kerusakan.
Dibeberapa wilayah lain, Mesir, Syiria, Iran, Iraq, anak benua India dan di asia tenggara mengalami invansi oleh negara-negara barat. Terutama Inggris dan Perancis[16]. Wilayah-wilayah tersebut menjadi medan pertempuran bagi kedua negara dalam memperebutkan sumber daya alam sekaligus wilayah jajahan. Praktis dalam kondisi yang terjajah wilayah-wilayah muslim mengalami kemunduran dan ketertinggalan dari bangsa-bangsa eropa. Persatuan hilang, keefektifan kepemimpinan tidak ada, dan muncul berbagai pergolakan yang mengakibatkan wilayah-wilayah itu semakin terpuruk.[17]
Pada kondisi yang karut marut tersebut di beberapa wilayah Muslim telah melahirkan berbagai pemikir yang berlatar modern, dalam arti mempunyai wawasan Eropa karena Eropa dianggap modern. Mulai dari Muhammad Abduh (w.1905) dan lain-lain. Mereka menawarkan gagasan baru dalam membentuk negara Islam baru. Gagasan-gagasan mereka itulah yang kemudian dikenal sebagai gerakan fundamentalisme oleh kalangan barat.[18]
Di awal abad 20 M wilayah-wilayah muslim telah bangkit dengan lahirnya nasionalisme, beberapa tokoh menawarkan gagasan ideal untuk menentukan bentuk negara. Karena waktu itu bangsa barat dianggap sebagai modern, maka pemikiran-pemikiran baratlah yang dianggap ideal untuk menentukan bentuk ideal dunia Islam. Lahirlah pemikiran Nasionalisme, sebuah pemikiran politik yang didasarkan pada kesamaan suku-bangsa.
Nasionalisme membentuk sebuah negara berdasarkan suku-bangsa yang menduduki suatu wilayah, dan disatukan oleh pemikiran sedarah dan se-tanah air. Gagasan inilah yang kemudian menjadikan wilayah-wilayah muslim jajahan negara barat melakukan gerakan merdeka dan mendirikan negara bangsa. Munculah India, Iraq, Iran, syiria, Mesir, Maroko, Libya, sudan, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain sebagai bentuk negara-bangsa yang didasarkan atas nasionalisme suku-bangsa.
Sayyid Ahmad Khan dari Aligard, seorang intelektual India berpendidikan Inggris berhasil menelurkan ide-ide nasionalisme india. Ia menawarkan gagasan negara Ideal adalah negara Inggris, sehingga ia membentuk India sebuah imitasi dari kerajaan Inggris. Di Aligard ia mendirikan sebuah Universitas yang berkiblat pada Cambrige of University.[19]
Beberapa dekade kemudian muncul tokoh-tokoh yang se-ide dan mempunyai kesamaan gagasan dengan para fundamentalis, gerakannya dikenal sebagai gerakan neofundamentalis atau fundamentalisme kontemporer. Diantaranya Hasan Al-Banna, Sayydi Qutbh, dan Abu ‘Ala al-Maududi. Mereka berpikir bahwa umat Islam harus memiliki negara sendiri yang jauh dari pengaruh pemikiran barat, misalnya Nasionalisme-sekulerisme. Gagasan itu kemudian oleh Maududi diwujudkan dalam bentuk negara Pakistan yang memisahkan diri dari India. Maududi menamakannya demokrasi berdasar ketuhanan.
Namun dalam perjalanannya gagasan negara nasional versi Islam dianggap tidak mampu menjawab kemunduran umat Islam kontemporer. Ide Nasionalisme dianggap sebagai ide barat yang menyesatkan dan perlu ada prototype baru untuk mencari gagasan negara Islam ideal bagi umat Islam. Lahirlah Nasyiruddin an-Nabhani dengan organisasinya, Hizbut Tahrir yang menawarkan gagasan khilafah Islamiyah. Gagasan itu bermaksud mengembalikan bentuk pemerintahan Islam seperti yang pernah dijalankan oleh sejarah peradaban Islam, khusus sistem pemerintahan kekhalifahan.
Mereka beranggapan bahwa terpecah belahnya umat Islam menjadi beberapa negara-Bangsa merupakan faktor utama kekalahan dunia Islam vis a vis barat-Kristen. Dengan khilafah maka martabat dan persatuan umat Islam akan kembali pulih dan mampu bersaing dengan bangsa barat. Khilafah adalah jawaban yang tepat untuk mengembalikan kebesaran Islam seperti yang telah dibangun oleh Bani Abbasiyah dan Bangsa Utsmani.
Hizbut Tahrir mendefinisikan Negara Islam sebagai eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam serta menyebaraknnya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad[20]. Alasan perlunya Negara Islam, menurut al-Maududi berpijak pada tesis bahwa manusia harus berbakti kepada Allah dalm semua bidang kehidupan. Perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang terdiri dari prinsip-prinsip etika, sosial, politik, ekonomi, Pidana dan sebagainya tidak akan dapat di eksekusi secara menyeluruh kecuali di wilayah Negara Islam.[21]
Bertentangan dengan pendapat HTI, Ali Abdur Raziq mengatakan bahwa sistem khilafah bukan merupakan sebuah hal yang diharuskan untuk ditegakkan. Dalam artia khilafah merupakan bentuk negara yang sama dengan bentuk negara/sistem pemerintahan yang lain. Syari’at Islam tidak memberikan penekanan terhadap kewajiban—sebgaimana HTI untuk diwujudkan sebagai bagian dari syari’at Islam, atau sejajar dengan kewajiban rukun Islam.
“Hampir tidak dapat ditemukan adanya orang yang berpendapat tentang tidak wajibnya khilafah ini, baik secara logika maupun secara syar’i, walaupun ada yang tidak menentukan sikap seperti kelompok Mu’tazilah, Khawarij dan lain sebagainya. Wajib disini berarti melaksanakan hukum syara’. Dan apabila umat secara menyeluruh telah mampu merealisasikan keadilan dan melaksanakan syari’at Islam, maka tidak perlu lagi ada seorang imam dan fungsi khilafah”.[22]
Oleh karena itu, Ali Abdur Raziq lebih nekankan pada aspek rasionalitas dan efektivitas penerapan sistem pemerintahan. Artinya bahwa setiap muslim diberi hak untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri tanpa harus berkewajiban untuk menegakkan syari’at Islam.
Orang Muslim boleh menerapkan sisitem khilafah dan boleh pula mengambil bentuk negara yang lain, dengan catatan umat Islam mampu menjalankan syari’at Islam secara benar dan konsisten tanpa harus mendapatkan perlawanan dari pemerintah. Sepanjang umat Islam bisa menjalankan agama, maka bentuk pemerintahan bukan menjadi persoalan yang integral dan urgen untuk dijalankan.
Bahkan menurut Abdullahi Ahmed an-naim, Hubungan antara Islam, negara, dan politik sepanjang sejarah masyarakat Islam jelas merefleksikan ketegangan permanen antara visi ideal penyatuan Islam dan negara dengan kebutuhan pemimpin agama untuk melanggengkan otonominya (agama) dari institusi negara.[23] Oleh karena itulah, usaha untuk menjadikan khilafah sebagai solusi bagi umat Islam secara logis dan rasional sah-sah saja, akan tetapi itu bukan merupakan sebuah bentuk idela yang harus diusahakan dan dipaksakan. Dalam hal ini Khilafah murni sebuah sistem pemerintahan yang terpisah dari agama dan kewajiban syariat Islam.
Diskursus Foucault
Kekuasaan menurut foucault tidak hanya sekedar terbatas pada sudut pandang Negara dan hukum saja. Manuver-manuver kekuasaan kadang menurutnya justru secara efektif mampu mengekstensifkan dan mengintensifkan penetrasinya pada masyarakat sampai unsure-unsurnya yang paling privat dan sensitive, justru apabila kekuasaan diapropisasi individu bukan sebagai penderitaan tapi sebagai sebuah kenikmatan atau sebagai sesuatu yang sifatnya enjoyed. Bukan sebagai ancaman yang menakutkan, tetapi sebaliknya menurut Foucault sebagai sesuatu yang familiar yang bahkan diharapkan dan dinanti-nantikan kedatangannya.[24]
Foucault berpendapat bahwa individu adalah produk kekuasaan. Foucault mengumumkan bahwa pertumbuhan diri atau individu tidak dapat dikatakan hasil pertumbuhan natural atau pertumbuhan organism murni secara biologis, tapi hasil dari persilangan terus menerus dari berbagai konvensi, kode-kode dan diskursus-diskursus sebuah standar wacana tertentu. Baginya subyek maka dari itu tidak lebih dari sebuah a figment of discourse yakni sebuah omong kosong diskursus yang muncul sementara dari sebuah sistem representasi tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimaknai dalam istilah “kepemilikan” dimana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikan dalam suatu ruang lingkup dimana banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain.[25]
Kekuasaan menurut Foucault selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan, menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relsi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi penguasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Setiap kekuasaan disusun, dimapankan dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tersebut kemudian menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran disini oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan pula konsep yang abstrak. Akan tetapi ia diproduksi setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. disini setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.[26]
Menurut Foaucalt setiap ada diskursus resmi, maka ada diskursus alternative. Diskursus muncul dari dua bentuk. Pertama, within the dominan discourse yakni mengkonter diskursus dominan tetapi masih dalam diskursif field atau wilayah yang sama. Kedua outside the dominan discourse yakni membuat diskursif alternatif, di luar ideology dominan[27]. Berdasarkan hal tersebut maka pada kontestasi di Indonesia Nahdlatul Ulama’ sebagai organisasi terbesar menempati wilayah diskursus dominan yang penerapan model Negara berpacu pada keadaan Indonesia pada saat ini. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai kelompok yang menempatkan pada posisi diskursus alternative dengan mengusung konsep Negara islam dengan pemerintahan di pimpin oleh khalifah di Indonesia sebagi Negara yang mayoritas beragama Islam.
[1] Abdul Azis. 2011. Chiefdom Madinah. Salah Satu Paham Negara Islam. Jakarta; pustaka Alfabeta. hal.25
[2] Didasarkan pada hasil penelitiannya di Afrika dan Amerika selatan, lihat Abdul Azis, Chiefdom Madinah, hal 56
[3] W. Philips shively. Power and choice.(new York; McGraw-hill,1993) hlm 29
[4] Mahajan, political theory. Hlm. 134, 136-139
[5] Ahmed, Vaezi. 2006. Agama politik, Nalar politik Islam, terj. Ali syahab Jakarta;citra. Hlm. 8
[6] Ibid. hlm 23
[7] Louay M. safi. “The Islamic state; A conceptual Framework” dalam The American Journal of Islamic Sosial Science,Vol 8 no 2 hlm 223
[8] Op. Cit halaman 10-11
[9] Tamim, Ansary. 2010. Dari puncak Baghdad, Sejarah Dunia Versi Islam. Jakarta: Zaman hal. 397.
[10]Sebelumnya belum pernah di kenal Istilah Turki sebagai negara. Turki pada awal perkembangannya yang berakulturasi dengan budaya Islam hanyalah dikenal sebagai suku-suku yang sedarah dengan bangsa Mongol. Sedangkan bangsa Ustmani yang sekarang menjadi negara-bangsa Turki merupakan penggabungan berbagai etnis yang dulu menjadi warga negara kekhalifahan Ustmani, mereka terdiri atas keturunan Turki, Yunani, Arab, Armenia, Persia, Albania dan lain-lain. Ibid, hal 478.
[11] Di dunia Islam, perang dunia I dipandang sebagai konflik kecil eropa yang tidak memiliki dampak apapun bagi wilayah-wilayah Islam. Kebanyakan negeri-negeri Islam memandang sebagai konflik kecil bangsa Eropa yang sudah lama bermusuhan. Namun dengan keterlibatan Utsmani di perang tersebut membuat beberapa wilayahnya menjadi sasaran bagi pihak sekutu sebagai wilayah jajahan, terutama Inggris dan Perancis.
[12] Dalam kasus inilah seorang orientalis Inggris, Lawrence si orang Arab sangat berperan mengobarkan fitnah dan propaganda terhadap penduduk Hijaz agar mendukung Inggris, sekaligus membantu pemerintahan kerajaan Inggris untuk melakukan penetrasi ke wilayah tersebut.
[13] Syaikh Idaram, Sejarah Brdarah Sekte Salafi-Wahabi, Jogjakarta:Lkis hal. 120. Gerakan wahabisme muncul sebelum terjadinya perang dunia I dan pada saat Ustmani mani dalam posisi kuat. Mereka terus melakukan pemberontakan dan seringkali menimbulkan kerusuhan dan teror bagi umat Islam
[14] Ibid, 96
[15] Ibid, 93
[16] Perancis dan Inggris memang selalu berseteru dalam memperebutkan wilayah jajahan, terutama negara-negara yang berada dibawah kekuasaan kakhalifahan Utsmani
[17] Eropa melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah muslim sudah sejak abad 17 M, kendati secara de jure mereka belum sepenuhnya bisa mengontrol. Namun secara de facto mereka telah menguasai semua kendali sumberdaya dan kelemahan kepemimpinan beberapa sultan-sultan kecil.
[18] Rubaidi. 2010. Radikalisme Islam, NU dan masa depan moderatisme Islam di Indonesia. Jogja, hal.48
[19] Tamim Ansary, Dari Puncak Baghdad.
[20] Ainur Rofiq. 2012. Membongkar Proyek Khilafah Ala HTI. Yogyakarta; Lkis
[21] Abul A’la al-maududi. Sistem politik islam. Menurut HT pemerintahan Islam memiliki 4 pilar yaitu, pertama kedaulatan di tangan syara’, bukan di tangan ummat; kedua, kekuasaan di tangan umat; ketiga, diangkatnya satu orang khalifah; keempat hanya khalifah yang berhak mentabbani hukum syara’. Tesis.
[22] Ali Abdur Raziq, 1985. Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam. Pustaka Bandung.
[23] Lihat Abdullahi Ahmed an-Naim, Islam dan Sekulerisme. Bandung Mizan, hal. 84.
[24] Suyono,seno joko. 2002. Tubuh yang rasis. Yogyakarta:pustaka pelajar Offset .halaman 56
[25] Eriyanto, 2001. Analisis wacana pengantar teks media. Lkis. Yogyakarta. Halaman 65
[26] Ibid, hal 66-67
[27] M. Jacky. 2003. Konsep dan teori diskursus. Jurnal paradigma Vol.I no 2 Juli 2003 halaman 19
Sumber : kitasama.or.id


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co