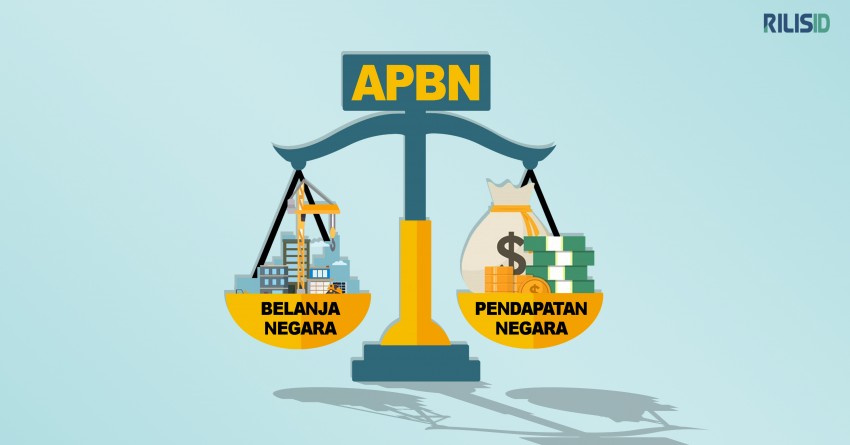Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Indonesia, Harus Bagaimana?
Oleh Ahmad Taufiq*
Revolusi industri yang dipantik dari penemuan mesin uap yang terus dikembangkan sejak abad XVII, membawa perubahan yang signifikan bagi umat manusia. Perubahan itu terus berlanjut hingga sekarang, di mana perkembangan sains dan teknologi membawa umat manusia pada fase revolusi industri mutakhir yang dikenal dengan revolusi industri tahap keempat (IR 4.0).
Namun, revolusi industri yang dicanangkan demi mengejar kesejahteraan manusia itu membawa dua persoalan yang menjadi pekerjaan rumah. Yakni adanya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan kerusakan lingkungan, yang dikenal dengan ekosida.
Mengenai kesenjangan ekonomi, sebagai gambaran, data mutakhir mengungkapkan bahwa jumlah kekayaan 8 orang terkaya di dunia lebih besar dri jumlah kekayaan separoh penduduk bumi. Selain itu, negara-negara belahan dunia utara seperti Amerika utara, atau Eropa, tetap merupakan negara maju, sementara negara-negara selatan masih tergolong tertinggal. Padahal, dari sisi kekayaan sumber daya alam (SDA), negara-negara yang tergolong maju tersebut tergolong miskin. Sementara negara-negara selatan seperti Indonesia tergolong kaya SDA.
Kenyataan tersebut seperti membuktikan suatu teori mengenai “kutukan SDA”, yang mana semakin kaya suatu negara, akan terjebak dalam ketertinggalan. Secara kasar, kemajuan negara-negara utara adalah berkat dari kemajuan industrialisasi, sementara negara-negara yang kaya SDA terjebak pada infant industry belaka, yang sekedar menjual bahan mentah, sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi barang jadi tinggal impor dari luar.
Adapun mengenai kerusakan lingkungan, sejauh ini masifnya industrialisasi masih berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Negara-negara yang tergolong maju dalam industrialisasi, contohnya Amerika Serikat dan China, adalah penyumbang emisi karbon terbanyak, yang berimplikasi pada pemanasan global (global warming). Adapun negara seperti Indonesia masih berkubang dalam jebakan industri ekstraktif, yang secara langsung merusak lingkungan.
Selain itu, industrialisasi memunculkan persoalan sampah atau limbah, yang semakin lama semakin besar. China adalah penyumbang sampah terbanyak yang terbuat di lautan. Sementara Indonesia menduduki ranking ke-3, suatu “prestasi” yang memprihatinkan.
Kerusakan lingkungan tersebut dampaknya mulai terasa saat ini, di mana berbagai macam fenomena bencana alam begitu mengancam. Seperti banjir, kemarau yang lebih panjang yang memicu kebakaran hutan, juga berbagai penyakit akibat persoalan sampah yang semakin menggunung tak teratasi.
Dalama berbagai penelitian, berbagai bencana alam tersebut muncul dari kenaikan suhu global. Dalam laporan Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) yang berjudul “Special Report on Global Warming of 1.5C” tercatat bahwa bumi akan mengalami kenaikan suhu global melewati ambang batas minimum yang ditetapkan pada 2030, yakni 1,5 derajat celcius.
Angka 1,5 nampak kecil, tetapi dalam skala bumi efeknya sangat besar dan merusak. Apalagi negara Indonesia tergolong negara tropis, sehingga ancaman berbagai macam bencana semakin besar, seperti hujan dengan intensitas tinggi, banjir, siklon tropis, kepunahan terumbu karang, kemarau yang semakin panjang yang menyebabkan kebakaran hutan dalam skala besar. Mengenai kebakaran, fenomena kebakaran hutan di Siberia yang merupakan bentangan daerah yang dikenal sangat dingin, untuk pertama kalinya mengalami kebakaran hutan yang parah, yang asapnya sampai kutub utara. Suatu fenomena yang menunjukkan bahwa bumi tempat tinggal umat manusia sedang tidak baik-baik saja.
Pemanasan global tersebut adalah akibat langsung emisi karbon dari industrialisasi yang masih dominan saat ini. Emisi karbon terbanyak masih negara-negara industrial, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, sementara Indonesia adalah negara yang bukan negara maju yang masuk 10 besar penghasil emisi karbon.
Kedua pekerjaan rumah tersebut memantik berbagai macam kalangan secara global untuk mengatasinya. Persoalan kesenjangan secara global memunculkan gagasan-gagasan yang sempat mewarnai jagad dunia pada abad XX, antara liberalisme dengan sosialisme, yang dinamikanya saat ini memunculkan model negara kesejahteraan (seperti negara-negara di Jazirah Skandinavia), jalan ketiga (Inggris), sosialisme pasar (Tiongkok), dan sebagainya.
Sementara itu, persoalan kerusakan lingkungan membuat berbagai negara mengkampanyekan pengurangan emisi karbon, pengembangan teknologi hijau, pengembangan industri ramah lingkungan, dan sebagainya, yang semua tercakup dalam konsep green economy. Bahwa pengejaran pertumbuhan ekonomi harus juga memperhatikan aspek keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih sehat.
Dalam konteks Indonesia, masalah kesenjangan berkait-kelindan dengan persoalan lingkungan hidup. Kesenjangan ekonomi penduduk Indonesia masih tergolong tinggi dengan rasio gini 3,7 dan kerusakan lingkungan masih terus berlangsung seperti deforestasi besar-besaran akibat industri ekstraktif dan perkebunan monokultur, sementara negara masih terus mengejar pertumbuhan ekonomi, sebagaimana nampak dalam pengeahan UU Cipta Kerja Omnibus Law, sebuah regulasi “ramah bisnis” tapi kurang ramah terhadap pekerja dan kelestarian lingkungan.
Oleh sebab itu, dibutuhkan agar pengejaran pertumbuhan ekonomi sebagai suatu jalan yang realistis untuk ditempuh agar tetap sejalan dengan pengurangan tingkat kesenjangan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam berbagai kajian, yang pertama dikenal dengan pertumbuhan ekonomi inklusif sementara yang kedua dikenal dengan ekonomi hijau. Jika keduanya dipakai secara terpadu, akan tercipta suatu pendekatan holistik.
Namun, mengenai keadilan ekonomi secara garis besar sudah termaktub dalam berbagai perundang-undangan, bahkan UUD 1945 seperti pasal 33 ayat 3. Adapun mengenai eksekusinya sudah terjalankan dalam berbagai kebijakan negara, seperti regulasi pasar, subsidi atas berbagai kebutuhan strategis, keberadaan berbagai jaminan social dan sebagainya. Sementara itu, mengenai persoalan kerusakan lingkungan masih tergolong baru bagi Indonesia. Sehingga memerlukan suatu tekanan secara lebih khusus agar negara kita turut andil bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan sebagai bagian dari keberlangsungan umat manusia itu sendiri dari generasai ke generasi.
Tanggung jawab pelestarian lingkungan tentu saja harus dilaksanakan bersama-sama, baik dari kalangan pemerintah maupun warga. Untuk itu, dukungan anggaran khususnya dari pemerintah menjadi penting dalam mendorong berbagai macam aspek yang bertujuan melestarikan lingkungan, misalnya dalam hal konservasi hutan, pengolahan sampah atau limbah, penghijauan kota, pengembangan teknologi hijau, dan sebagainya.
Secara global, saat ini mulai marak ecological fiscal transfer (EFT), insentif fiscal berbasis ekologi, yang memasukkan ekologi sebagai sapek penting dalam insentif fiscal, demi mendorong pelestarian lingkungan. Pada mulanya, EFT dilaksanakan Brazil khususnya dalam menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya, yang kemudian disusul berbagai negara seperti Portugal, Tiongkok, India, Prancis, menyusul kemudian Indonesia, Uganda, dan seterusnya.
EFT ala Indonesia
Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia. Namun, karena pemerintah pusat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, hal tersebut membuat daerah-daerah yang memiliki hutan yang luas menghadapi dilema. Satu sisi pertumbuhan ekonomi harus dikejar, sementara sisi lain hutan yang ada harus dijaga karena merupakan sumber daya yang memberikan banyak manfaat seperti penyerapan karbon dan pengaturan iklim. Padahal, penjagaan hutan memerlukaan biaya yang tidak sedikit.
Oleh sebab itu, sejauh ini yang berlangsung adalah agenda konservasi hutan masih tergolong lambat, sehingga hutan yang ada terus mengalami penyusutan. Sementara itu, penyusutan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya berbagai persoalan seperti adanya banjir bandang ketika hujan deras, kelangkaan air pada musim kemarau, sebagaimana yang terjadi dalam berbagai daerah di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jika hal tersebut terus berlangsung, diperkirakan luas wilayah kritis air akan meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 9.6 persen pada tahun 2045. Selain itu, secara global tutupan hutan tersebut sangat bermanfaat bagi penyerapan emisi karbon sehingga menghambat peningkatan efek rumah kaca.
Di samping menuntut biaya sekaligus sumber daya yang tidak sedikit, daerah-daerah yang fokus pada penjagaan hutan juga kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan sumber daya hutan, misalnya untuk aktivitas pertambangan atau perkebunan monokultur sawit yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Padahal beban biaya penjagaan hutan tersebut ditanggung oleh daerah itu sendiri, sementara manfaat yang dihasilkannya jauh melebihi daerah tersebut, bahwa bisa sampai ke seluruh dunia, sebab keberadaan hutan secara langsung menyerap emisi karbon yang secara besar disumbangkan oleh aktivitas industri dalam skala global.
Hal tersebut menyebabkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antar daerah di Indonesia, antara yang lebih banyak aktivitas industri dengan yang lebih banyak tutupan hutan. Misalnya di Jawa Barat, daerah-daerah bagian utara yang lebih banyak industri ditinjau dari pendapatan daerah lebih sejahtera daripada daerah-daerah bagian selatan yang lebih banyak tutupan hutannya. Apalagi hal tersebut berkaitan erat dengan adanya peraturan di tingkat provinsi harus menyediakan adanya alokasi konservasi hutan 70% sehingga jika suatu daerah dibangun industri, daerah yang lain dipaksa megalah menjadi penjaga hutan. Kalau pun daerah yang banyak tutupan hutannya tersebut hendak membangun industri, dalam prosesnya harus mengalami peraturan yang lebih rigid daripada daerah yang minim tutupan hutannya. Hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan antar daerah yang perlu diatasi dalam skala nasional, atau minimal skala proivinsi.
Oleh sebab itu, transfer anggaran berbasis ekologi bisa menjadi alternatif jalan keluar bagi pemerintah daerah yang tutupan hutannya luas untuk mendapatkan anggaran yang sepadan dengan kerja-kerja penjagaan hutan dan hilangnya kesempatan untuk melakukan pengambilan manfaat dengan jalan industrialisasi ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan monokultur demi pendapatan daerah. Tingkat luasan tutupan hutan dan kinerja daerah dalam menjaga kelestariannya, bisa dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pemberian insentif tersebut.
Pemberian tersebut perlu dilakukan demi mengatasi adanya penyusutan tutupan hutan yang terus menerus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Data IPBES 2018 menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680 ribu hektar, yang mana merupakan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara data yang dirilis Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin dalam di masa depan. Indikasinya antara lain adalah tutupan hutan primer yang semakin hari semakin menyusut dan diproyeksikan pada tahun 2045 hanya akan tersisa sekitar 18,4% dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha). Padahal, urgensi hutan sangat dibutuhkan dalam hal penurunan emisi karbon sebesar 29% yang menjadi target nasional pada tahun 2030.
Sementara itu, di berbagai negara negara, skema insentif bagi konservasi hutan khususnya, yang kemudian diperluas menjadi skema insentif berbasis ekologi yang meliputi persoalan pemeliharaan kualitas air sungai, pengolahan limbah, pengembangan teknologi hijau, dan sebagainya, telah dikembangkan lewat transfer fiskal dari pemerintah pusat pada pemerintah di bawahnya, seperti provinsi atau negara bagian. Hal tersebut merupakan penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan atau pelestarian lingkungan hidup yang di dalamnya mencakup konservasi hutan.
Contoh yang paling spektakuler adalah yang di negara bagian Parana, Brasil yang sudah menerapkan skema insentif EFT. Dalam waktu hanya 8 tahun, Parana sukses meningkatkan total kawasan hutannya dari 637 ribu ha pada 1991 menjadi 1,69 juta ha pada 2000, yakni mengalami peningkatan sekitar 165%. Keberhasilan itu menginspirasi negara-negara bagian lainnya di Brazil untuk menerapkan EFT tersebut, lalu berbagai negara lain seperti Portugal (2007), India, Tiongkok, Jerman, Swiss, menyusul. Dalam banyak kajian para peneliti menyimpulkan mengenai efek yang dihasilkan. Di Brasil dan Portugal, pemerintah daerah telah menetapkan lebih banyak kawasan lindung. Di Cina, EFT telah berkontribusi pada penurunan polusi, tetapi bukan peningkatan lahan yang dilestarikan. EFT India belum menghasilkan peningkatan tutupan hutan, tetapi telah menjadi bagian resmi dari pembiayaan komitmen iklim nasional. Adapun mengenai pertumbuhan EFT secara global menunjukkan betapa cepat pertumbuhannya, di mana pada tahun 2007 EFT hanya sebesar US$300 juta per tahun; pada tahun 2020 ini telah tumbuh menjadi US$23 miliar per tahun.
Adapun dalam skema EFT tersebut, yang menarik adalah bagaimana variasi antar negara mengenai indicator penerapannya. Beberapa EFT dibayar berdasarkan indikator “hijau” seperti kawasan hutan; sementara sebagian lainnya dibayar berdasarkan indikator “coklat” seperti pengolahan air atau pengurangan tingkat pencemaran. Selain itu, beberapa EFT dibayarkan berdasarkan dana abadi (misalnya, tutupan hutan di negara bagian Minas Gerais, Brasil), sementara yang lain dibayarkan berdasarkan perubahan status dana abadi (misalnya, pencegahan deforestasi di Pará) atau tindakan untuk melestarikan dana abadi tersebut (misalnya, pemadam kebakaran di Tocantins).
Skema EFT biasanya berlangsung secara vertical dalam arti pemerintah pusat member i insentif pada pemerintah di bawahnya, baik itu provinsi atau negara bagian, hingga pada tingkatan daerah bahkan pedesaan. Yang unik adalah Tiongkok, yang mencoba skema EFT yang selain vertical juga horizontal, antar provinsi atau antar daerah. Contohnya sebagaimana dipelopori oleh provinsi Anhui dan Zhejiang. Zhejiang yang merupakan provinsi hilir sungai membayar Anhui yang merupakah hulu sungai atas peningkatan kualitas air Sungai Xin’an yang berada di atas patokan. Namun, jika kualitas air memburuk di bawah patokan yang ditentukan, maka sebaliknya Anhui harus membayar Zhejiang. Adapun pemerintah pusat memposisikan diri sebagai pemantau yang menegakkan aturan tersebut, selain itu juga memberikan kontribusi 300 juta yuan (sekitar US$43 juta) per tahun dari EFT horizontal yang jumlahnya 700 juta yuan (sekitar US$100 juta). Hal tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah pusat demi meringankan biaya transaksi yang mahal yang harus ditanggung.
Adapun dalam konteks negara Indonesia, skema EFT begitu gencar digaungkan oleh berbagai kalangan tahun-tahun terakhir. Beberapa sudah mulai diterapkan, dalam skala provinsi misalnya sudah diterapkan di Kalimantan Utara, sementara dalam skala daerah tingkat dua, sudah diterapkan pada berberapa daerah. Wacana EFT tersebut mulanya digalakkan oleh Research Center for Climate Change University of Indonesia/RCCCUI yang menginisiasi penambahan variabel luas kawasan hutan dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Kemudian The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) yang digagas oleh UNDP mendorong ada skema Dana Insentif Daerah (DID) untuk keanekaragaman hayati. Hingga kemudian The Asia Foundation (TAF) dengan koalisi masyarakat sipil mempromosikan EFT dalam bentuk tiga skema, yakni Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE),Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
TAPE mengedepankan skema insentif yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang menjaga kelestarian lingkungannya, dengan sumber dana berasal dari bantuan keuangan pemerintah provinsi. Seperti yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Utara, kebijakan skema transfer bantuan keuangan berbasis ekologi tersebut telah dikeluarkan sebagai bagian dari Peraturan Gubernur (Pergub) No. 6/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 49/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Adapun TAKE diadopsi oleh Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan memberikan skema insentif kepada desa yang menjaga kelestarian lingkungan melalui formula penghitungan Anggaran Dana Desa (ADD). Kebijakan Kabupaten Jayapura itu termaktub dalam Peraturan Bupati No.11/2019 tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2019. Dalam pengembangannya, TAKE yang mereformulasi Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) untuk memberikan insentif kepada desa-desa yang menjaga kelestarian lingkungannya. Selain di Jayapura (Papua), skema TAKE ini telah diadopsi juga oleh Kabupaten Nunukan (Kalimantan Utara) melalui, masing-masing Peraturan Bupati No. 11/2019 tentang Alokasi Dana Kampung Tahun 2019 dan Peraturan Bupati No. 59/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 15/2015 tentang Alokasi Dana Desa. TAKE ini juga sedang dikembangkan di daerah-daerah lain, termasuk Kabupaten Bener Meriah (Aceh), Keerom dan Supiori (Papua), Kubu Raya (Kalimantan Barat), dan Manokwari Selatan (Papua Barat).
Adapun untuk TANE, sejauh ini masih menjadi wacana yang diusulkan untuk diadopsi pemerintah pusat. Kalau TANE nantinya diadopsi, maka Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang punya visi ekologis dengan tanggungjawab pelestarian atas cakupan hutan yang luas dan menjadi negara raksasa dalam bidang kehutanan. Penerapan TANE akan banyak mengatasi persoalan kesenjangan antar daerah akibat ketidakmerataan industri yang ada.
Skema-skema seperti TAKE, TAPE dan TANE tersebut nampaknya sangat diminati oleh daerah-daerah dengan kawasan dengan tutupan hutan yang luas. Sehingga yang menjadi pelopor adalah Kalimantan Utara, Jayapura, dan sebagainya. Tidak di daerah padat seperti Jawa atau Bali. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian khusus mengenai skema yang cocok dengan melihat konteks Jawa dan Bali.
Di desa-desa Jawa, misalnya, mayoritas adalah petani gurem dengan lahan sepetak. Inentif fiscal berbasis ekologis itu butuh melirik apa yang menjadi problematika petani-petani gurem tersebut, yang ada kaitan langsung dengan persoalan ekologis. Misalnya, pertanian para petani gurem tersebut sejauh ini mayoritas adalah petani tradisional dalam arti menggunakan bibit hasil membeli dari pabrik, lalu penggunaan pupuk kimia sintetik berikut pestisidanya, dan seterusnya, yang menunjukkan ketergantungan petani atas sesuatu diluar dirinya alias petani tidak berdaulat. Untuk itu, perlu adanya penggalakan pertanian organic atau bahkan pertanian alami di tingkatan desa-desa, selain demi mengakhiri ketergantungannya, juga turut andil dalam kelestarian lingkungan.
Adapun dalam konteks masyarakat urban yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja dan pegiat UMKM, perlu adanya insentif anggaran untuk pengelolaan sampah atau limbah di kampung-kampung padat penduduk untuk menciptakan lingkungan perkampungan urban yang terkenal kumuh menjadi perkampungan yang layak huni.
Strategi Penerapan EFT
Bahwa pengejaran terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks Indonesia dimana perekonomian negara masih bersandar pada industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan monokultur akan berakibat pada penyusutan kawasan hutan dan secara umum pada perusakan lingkungan, sehingga perlu adanya pendekatan baru yang lebih mendukung adanya kelestarian lingkungan.
Kebijakan “ramah bisnis” yang diterapkan pemerintah pusat melihat kondisi berbagai daerah yang sangat bervariasi, menciptakan kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Daerah dengan tutupan hutan lebih luas akan lebih banyak beban dalam penjagaan hutan dengan anggaran ditanggung sendiri, sementara manfaat dari hutan bisa dinikmati banyak daerah lainnya bahkan sampai skala global.
Mengingat Indonesia punya kawasan hutan yang tergolong terluas ketiga di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk menjaganya. Selain itu, merupakan peluang tersendiri sebab kekayaan biodiversitas yang ada di dalam hutan belum banyak tereksplorasi, misalnya tanaman-obat-obatan, yang terkadang terburu punah sebelum diteliti. Ini peluang dalam pengembangan industri farmasi yang lebih ramah lingkungan daripada industri ekstraktif.
Skema EFT yang sudah berlangsung dan berhasil di berbagai negara seperti Brazil, India atau Tiongkok, dan kemudian dicobakan di Indonesia dalam tiga bentuk TAPE dan TAKE, dan diusulkan dalam TANE, harus mengikuti konteks yang ada. Selain itu, belajar dari kasus Tiongkok tentang penerapan EFT Horizontal perlu dicobakan. Misalnya dalam konteks Bengwan Solo yang membentang dari Jawa Tengah sebagai hulu ke Jawa Timur sebagai hilir. Jika sampai perbatasan Jateng/Jatim kualitas sungai bagus, Jatim patut memberi insentif, sebaliknya jika kualitas airnya buruk, Jateng patut member insentif pada Jatim.
Untuk pulau Jawa yang padat penduduk dengan mayoritas adalah petani gurem di desa-desa, yang paling dibutuhkan adalah penumbuhan kesadaran untuk menjadi petani dan berdaulat dengan mengatasi ketergantungannya atas pupuk kimia sintetik dan pestisida, dengan mengembangkan jenis pertanian organic atau bahkan pertanian alami, yang selain menekan biaya produksi besar-besaran, juga turut andil besar dalam mengurangi emisi karbon. Pemerintah daerah wajib memberikan insentif fiskal bagi para petani yang beralih menjadi petani organik dan petani alami.
Sementara itu, untuk kawasan industrial, perlu adanya pengurangan pemakaian teknologi yang memakai sumber daya fosil. Selain itu, perlu adanya insentif bagi pengolah sampah yang semakin hari semakin menggunung seperti tak tertangani secara baik.
* Penulis aktif di Gerakan Alternatif 21


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co