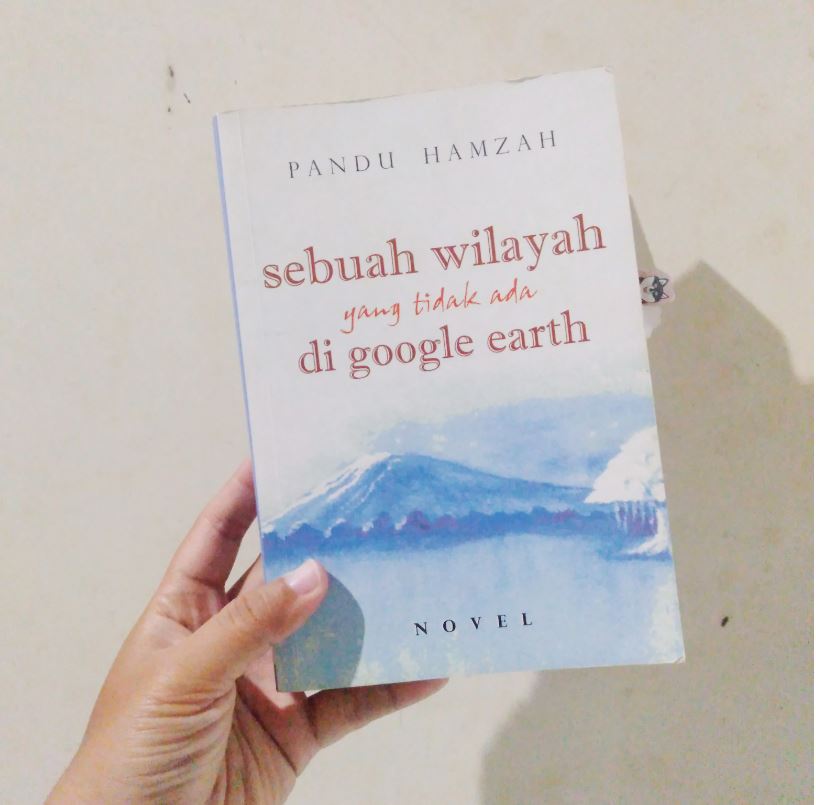Melepas Hantu-Hantu Pergi | Cerpen : Rafii Syihab
Yang selalu jadi masalah ketika seorang hantu jatuh sakit ialah: kami tak tahu harus berbuat apa. Kami tahu alasan kenapa mereka sakit, tetapi kami tak tahu sakit jenis apa yang mereka derita, dan apa yang bisa kami lakukan dengan semua itu selain hanya berpasrah diri melepas mereka ke tempat lain yang jauh dari pemukiman—sesuatu yang sesungguhnya amat menyedihkan bagi penduduk Murakambang. Hantu-hantu yang pergi itu ialah hantu-hantu yang sama yang menemani kami sejak pertama kali mengenal dunia. Bagaimana pun, dari merekalah kami mengenal pijakan kami, cerita-cerita tentang tanah yang kami tinggali. Dan tak ada keributan dengan itu, setidaknya jauh sebelum orang-orang kota itu datang. Bahkan jika hantu-hantu tanpa nama dengan atribut perang menembus dinding kami, bicara ngawur tentang kerasnya perjuangan di masa yang jauh, meminta belas kasih untuk menetap sebentar di pojok rumah, atau untuk sekadar meminta air pelepas dahaga, kami akan tetap melayani mereka sebagaimana kami melayani manusia.
Adalah biasa, misalnya, anak-anak kami bermain petak umpet dengan hantu Tuan Militer, tidur dalam dekapan Nik Marsiah dengan Mars Romusha yang selalu dinyanyikannya, dan hal-hal semacam itu yang sungguh, dalam banyak hal, amatlah membantu kami untuk bekerja ke ladang tanpa harus dibebani rengek tangis anak-anak. Tetapi kini wabah itu datang menyerang, seperti gelombang perang yang lain, membikin sakit hantu-hantu, memaksa mereka angkat kaki dari tanah yang mereka bikin berdarah-darah jauh sebelum kelahiran kami—aku, generasiku, dan orang-orang setingkat di atasnya.
Sudah banyak hantu yang minggat, tetapi tadi malam adalah petaka terbesar bagiku terkait kepergian ini: Nik Kuyang, hantu yang tanpa letih menceritakan muasal Murakambang, mengalami sakit dan ia, bersama dengan Nik Marsiah, terpaksa pergi menuju lembah jauh di hulu hutan. Aku mengutuki nasib buruk ini dengan pikiran-pikiran kasar terkait siapa nanti yang bakal menceritakan leluhur kami kalau ia tiada. Selagi hidup, kami mungkin bisa, itu pun tak bisa sedetail dirinya yang secara langsung mengalami semua hal itu. Kelak jika aku mati, jika kami semua mati, kami pun harus angkat kaki dari Murakambang untuk menyusul mereka ke tanah yang jauh itu.
Betapa mengerikannya semua ini, begitu Nik Kuyang berkata sesaat sebelum kepergiannya, dan aku setuju padanya.
Nik Kuyang—terlepas dari fakta bahwa ia sebatas kepala terbang semata—adalah ibu bagiku, bahkan mungkin bagi semua hantu. Melepasnya pergi bukan perkara mengucapkan selamat tinggal, semoga kita bertemu lagi belaka, tetapi lebih terasa seperti melepas kepala kami untuk ikut terbang mengikutinya ke tanah usiran. Cerita-ceritanyalah dulu yang menjadi hiburan kami, tentang tanah terkutuk bernama Rawa Rantau tempat nini datu kami berasal; perang-perang panjang yang silih berganti datangnya; tentang mars romusha yang selalu dinyanyikan Nik Marsiah; juga perjalanan jauh hingga akhirnya menemukan Murakambang.
Dulu, begitu ia selalu memulai, dulu sekali, ada satu masa di mana perang begitu akrab di telinga kami. Jauh sebelum Negara merdeka, Rawa Rantau selalu dilanda perang: Belanda, Jepang, Garumbulan, dan perang lainnya dari perompak-perompak yang terjadi di masa-masa di antara ketiganya. Kami selalu terlibat dalam perang meski kami tak pernah melibatkan diri. Nyawa-nyawa melayang tanpa dapat dihitung. Pada satu waktu, ketika Jepang datang, orang-orang dijemput paksa untuk bekerja sukarela di suatu tempat bernama Maluka—Komandan Udar adalah satu dari orang yang terlibat dalam kerja sukarela tersebut—itu adalah masa-masa kepenatan kami terhadap perang mulai timbul. Ketika Jepang pergi, dan gegap gempita kemerdekaan sesaat datang ke Rawa Rantau, kami pikir semuanya telah berakhir, tetapi kemudian ada perang lagi. Itulah masa garumbulan. Masa di mana orang-orang berperang melawan Negara dan Rawa Rantau berada di antara kecamuk itu. Komandan Udar, waktu itu belum kami panggil komandan, mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin dan mengusulkan bahwa kami harus pergi mencari tanah lain, pergi serentak meninggalkan tanah kutukan, membawa segala yang bisa kami bawa termasuk arwah leluhur kami—yang saat itu masih tinggal di Rawa Rantau—untuk berjalan kaki selama berbulan-bulan menerabas hutan. Dan dengan cara itulah Murakambang ditemukan. Tanpa bantuan hantu-hantu, tanah ini tak mungkin ditemukan. Maka atas kesepakatan, begitulah hantu-hantu itu—dan kini aku—bisa hidup berdampingan dengan mereka yang hidup.
“Aku mendapatkan lagu jelek itu dari Komandan Udar, ia bilang lagu itu simbol bagi perjuangan kami,” Nik Marsiah berkata.
Aku pernah mendengar kisah itu, tetapi sebab ia akan pergi, kudengarkan saja ia bercerita. Dulu Komandan Udar mendengar lagu itu dari Si Orang Jawa di barak kerja sukarela Jepang, jauh di Maluka sana. Ia menghapalnya sebagai satu-satunya hiburan yang bisa didapat di tempat penyiksaan itu, menertawakannya, dan kemudian mengajari Nik Marsiah melantunkannya sebagai penyemangat kala letih datang di zaman pelarian mereka. Nik Marsiah suka bernyanyi, dan itulah satu-satunya lagu yang pernah didengarnya ketika masih hidup, bahkan ketika Jepang sudah pergi, dan Murakambang sudah ditemukan—ia terus saja menyanyikannya saban waktu.
Aku meneteskan air mata mendengar ulang cerita itu, meski disampaikan secara singkat saja, namun sudah cukup menjelaskan bahwa di sini kami tak punya permusuhan antara hantu dan manusia. Tidak seperti di kota—sebagaimana kami lihat di televisi— di mata mereka, entah dengan alasan apa, hantu selalu jahat lakunya. Di Murakambang kami tak tahu konsep itu. Cara hidup kami yang berdampingan dengan hantu-hantu belakangan kerap diartikan sebagai keterbelakangan zaman bagi mereka yang baru datang ke Murakambang. Berbagai macam alasan konyol pun dilontarkan demi mengusir mereka: teknologi, kemakmuran, agama, perkembangan zaman, dan banyak alasan lainnya yang alih-alih membikin mereka terlihat pintar, malah nampak seperti orang bodoh yang tak tahu cara bicara. Tetapi terlepas dari kebodohan mereka, mereka punya kelebihan yang menegaskan nilai mereka: mengusir hantu-hantu. Orang-orang ini punya cara yang begitu efektif: menebang pohon-pohon. Dan begitulah hantu-hantu itu sakit, kemudian pergi dari Murakambang.
Sayangnya kami tak tahu cara mengobati hantu-hantu yang jatuh sakit itu, kami pun tak mengerti bagaimana caranya mencegah orang-orang kota agar berhenti menebang pohon-pohon. Yang jelas bagi kami sekarang hanya ada selamat tinggal bagi hantu-hantu yang pergi dan hanya itu saja, tak akan pernah ada selamat datang bagi siapa pun yang kemudian datang membawa petaka ke Murakambang. Atas alasan apapun. Takkan pernah ada.
Rafii Syihab berasal dari desa kecil di Banjar, Kalimantan Selatan, dengan keseharian bekerja sebagai petani karet. Menulis cerpen dan esai, beberapa karyanya dimuat di beberapa media terpisah, salah satunya esai tentang kopi Pengaron yang diterbitkan oleh Perpusnas Press dalam antologi esai Inkubator Literasi Pustaka Nasional berjudul Jalan Tengah Kopi Pengaron pada 2022 silam.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co