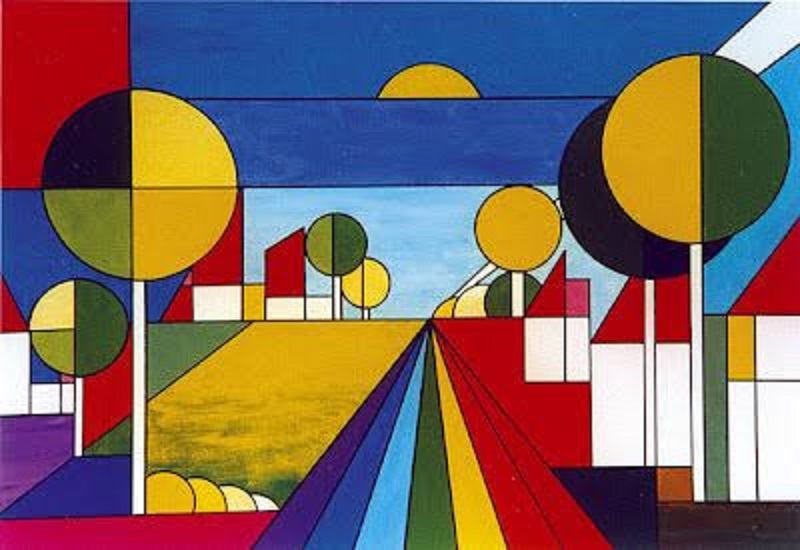
Suatu Tempat di Mana Tuhan Tiada | Cerpen Abul Muamar
Sempat terpikir olehnya untuk mengurungkan rencana saat ditatapnya wajahnya di cermin. Selama hampir 15 menit—dia sendiri tak sadar telah melamun selama itu—dia menimbang-nimbang kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika dia tetap pergi, maupun seandainya dia batal pergi. Berdiri dalam keadaan belum berbusana, berhadap-hadapan dengan bayangannya sendiri, dia merasa bukan dirinya yang terpantul pada cermin itu.
Dia, bernama Atik, usia 27 tahun, berkenalan dengan lelaki itu sembilan hari lalu lewat aplikasi kencan daring. Lelaki itu bernama Harley. Tampangnya pas-pasan untuk ukuran seseorang yang narsistik, tapi dari obrolan via ponsel sejak pertama kali berkenalan, tahulah dia bahwa lelaki itu punya pekerjaan bagus. Fakta yang satu ini sudah cukup baginya untuk melanjutkan hubungan, tetapi lelaki itu justru selalu mengumbar kelebihan tanpa ditanya.
“Bagiku, hidup ini harus dijalani dengan kerja keras. Ya, seperti kata presiden kita—kerja, kerja, kerja. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan penghasilan yang bagus,” kata lelaki itu, pada hari kedua mereka berkomunikasi lewat aplikasi obrolan.
Atik tidak memberi banyak komentar setiap kali lelaki itu bicara.
“Kamu tahu, tidak? Dari gajiku sebagai manajer HRD,” kata lelaki itu, “aku bisa membeli rumah di usia muda.”
“O ya?”
“Dan juga mobil.”
“Waaah.”
Berkali-kali Atik memberikan kesan kagum yang dilebih-lebihkan untuk menyenangkan lelaki itu. Namun, seandainya obrolan mereka hanya berkutat pada soal karier, uang, dan prinsip-prinsip hidup klise, lelaki itu mungkin tak akan mau mengajaknya berkencan. Lelaki itu mulai penasaran padanya, mula-mula ketika dia bertanya, “Untuk apa, pada akhirnya, semua uang dan harta yang kamu peroleh itu?”
Setelah berpikir agak lama, lelaki itu menjawab, “Untuk mencapai kebahagiaan.”
“Yakin, dengan itu semua, kamu akan bahagia?”
“Sejauh ini, aku yakin.”
“Yakin, bahwa kamu akan terus bahagia dengan harta dan uangmu?”
“Hari ini aku yakin. Entahlah kalau besok. Tapi, aku tahu bahwa untuk menjadi bahagia, aku mesti pernah merasakan penderitaan.”
“Memangnya kamu pernah menderita?”
“Hmm, tidak, sih. Tapi aku pernah tidak bahagia.”
“Kalau begitu, berarti kamu tidak yakin.”
Lelaki itu cengar-cengir mengakui kekalahannya dalam obrolan melalui panggilan video pada malam ketiga pe-de-ka-te mereka.
***
Rasa gugup bercampur takut masih meliputi benak Atik hingga setengah jam kemudian saat dia mencondongkan wajahnya ke cermin untuk meratakan olesan lipstik di bibirnya. Atik memilih mengenakan gaun tiga perempat berwarna coklat krim yang selama ini hampir tak pernah dipakainya. Gaun itu bau apek karena sudah lama tak dipakai.
“Aku OTW, Honey.”
Pesan teks dari lelaki itu masuk.
“Oke, Sweetie,” balas Atik dengan emoticon senyum. Mereka sudah saling menyapa dengan panggilan mesra sejak hari keenam pe-de-ka-te via ponsel.
“Di kedai kopi yang kamu bilang itu, kan?”
“Ya, jemput di situ, ya.”
“Siap.”
Atik mengecek jam tangannya dan memperkirakan bahwa lelaki itu akan tiba sekitar 40 menit lagi. Masih ada waktu baginya untuk menguasai pikiran. Dia ambil sebatang rokok dari dalam kotak yang ditaruh di dekat bedak dan lipstik, menyulutnya, dan beranjak dari depan cermin, berjalan ke arah jendela kamar. Dia resapi asap tembakau yang diisapnya, tarikan demi tarikan, sambil melamun memandang ke luar jendela. Di atas tembok yang membatasi kontrakannya dengan kontrakan sebelah, terlihat olehnya seekor kucing kuning jantan sedang mendekati kucing betina berwarna putih bercampur cokelat. Kucing jantan itu maju mundur karena yang betina tak mau dikawini. Kucing betina itu beberapa kali menggeram, memberi isyarat bahwa belum waktunya baginya untuk kawin.
Tak ingin larut dalam lamunan yang membuat pikirannya terganggu, dimatikannya api rokok ketika baru diisap separuh, dan bersiap-siap pergi ke kedai kopi yang jaraknya sekitar 200 meter dari kontrakannya.
Saat berjalan menuju kedai kopi, Atik teringat uang sewa kontrakannya yang belum dia bayar. Jika bukan karena dia sudah tiga tahun tinggal di rumah itu, pastilah si pemilik sudah mengusirnya. Apalagi, bukan sehari dua hari dia telat membayar, tetapi sudah dua pekan. Si pemilik kontrakan memberi waktu seminggu lagi sebelum benar-benar akan mengeluarkan barang-barangnya.
Atik belum juga mendapat pekerjaan usai di-PHK empat bulan lalu. Sebulan yang lalu, dia sebetulnya sudah diterima sebagai operator layanan pengguna kartu seluler, namun dia bikin ulah saat baru bekerja lima hari. Dia nekat mencuri ponsel rekan sekantornya. Hari itu juga, perbuatannya langsung ketahuan. Selain diminta untuk mengembalikan ponsel itu, dia juga langsung dipecat dan tak digaji sama sekali sebagai ganti dirinya tak dilaporkan ke polisi.
Atik tak tahu bisa meminta bantuan kepada siapa. Adapun pria yang tinggal bersamanya di kontrakan itu, yang kepada pemilik kontrakan diperkenalkannya sebagai suami, hanya mampu memberinya makan sebungkus nasi padang murahan sekali sehari dari hasil berkeliling kota sebagai penarik ojek daring. Pria itu sendiri sudah punya istri dan seorang anak perempuan berumur 3 tahun, namun ditinggalkan begitu saja.
***
Di kedai kopi itu, Atik memesan secangkir kopi yang paling murah. Kopi hitam berampas. Berkali-kali dia melepeh ampas kopi yang nyangkut di giginya. Sudah 50 menit berlalu, lelaki itu belum juga sampai.
“Jam berapa kalian jalan?” seorang pria bertanya di ujung telepon.
“Katanya, sih, dia jemput aku jam 11.”
“Ya sudah, tunggu saja. Aku sudah di sini. Nanti kamu ajak dia langsung ke sini, ya.”
“Oke, Sayang.”
Duduk sendirian menunggu lelaki itu datang, menyeruput kopi penuh ampas dengan enggan-engganan, dikeluarkannya sisa rokok yang belum habis diisapnya di kontrakan. Rokok itu memberinya ketenangan dalam lamunan, dan pada saat itu dia merasa Tuhan mampir dalam dirinya.
“Kamu percaya Tuhan?” tanya lelaki itu, dalam obrolan mereka pada malam kelima.
“Aku percaya Tuhan ada.”
“’Percaya Tuhan ada’, dengan ‘Percaya Tuhan’, itu dua hal yang berbeda. Yang aku tanya, apakah kamu memercayai Tuhan?”
“Kamu sendiri?” dia bertanya balik alih-alih menjawab.
“Kalau aku percaya Tuhan, mungkin aku tidak perlu bekerja keras mencari uang seperti ini. Seperti kata dokter Rieux dalam novel Albert Camus, aku tinggal ongkang-ongkang kaki saja menunggu Tuhan mengantarkan uang untukku. Bahkan mungkin aku tak perlu membuka aplikasi kencan ini untuk berkenalan denganmu.”
“Berarti, kamu tak percaya Tuhan?”
“Bukan begitu…”
“Tak perlu takut,” dia memotong sebelum lelaki itu sempat menjelaskan, “aku juga tidak percaya.”
Mereka tergelak bersama.
“Ssstt, jangan sampai kedengaran tetanggamu,” katanya.
“Tapi, apakah kamu percaya bahwa di dunia ini, ada tempat di mana Tuhan tiada*?”
“Menurutku tidak ada. Bukankah, seperti kata para filsuf pantheisme, Tuhan ada di mana-mana?”
“Aku pikir tidak. Tuhan tidak hadir di semua tempat.”
“Misalnya?”
“Di dalam toilet, atau di septic tank. Apa menurutmu Tuhan juga ada di tempat seperti itu?”
Lelaki itu terbahak-bahak mendengar perkataannya.
Segera setelah mengakhiri topik itu, obrolan malam kelima itu pun ditutup dengan kesepakatan untuk berkencan empat hari berikutnya.
***
Lelaki bernama Harley itu akhirnya tiba setelah Atik menghabiskan tiga setengah batang rokok. Secangkir kopi penuh ampas itu hanya terminum setengah. Mereka berpelukan hangat layaknya sejoli yang lama tidak bertemu.
“Bisakah kita langsung ke apartemen saja?” pinta Atik.
“Baiklah. Ayo,” jawab lelaki itu.
Tak sekadar kencan biasa, mereka berencana menghabiskan waktu berduaan selama seminggu, dan untuk keperluan itu, lelaki itu telah menyewa sebuah unit di Apartemen A di Pasar Baru untuk tujuh hari, sesuai usulan Atik.
Atik tersenyum memandang lelaki di sampingnya. Dia jauh lebih tenang sekarang dibanding sebelum bertemu lelaki itu. Tidak ada lagi rasa takut di benaknya. Pikirannya kini terpusat pada bagaimana dia akan membuat lelaki ini bergairah.
“Kami sudah di jalan.” Dia mengirim pesan singkat kepada pria yang tadi mengiriminya pesan.
Semenit kemudian, pesan balasan masuk: “Oke. Pokoknya, jangan sampai dia masuk ke kamar mandi.”
Sambil menatap Harley di sampingnya yang fokus menyetir, Atik mengetik, “Oke, Sayangku.”
SUV hitam itu berhenti di parkiran apartemen. Mereka langsung menuju kamar setelah menemui resepsionis.
Di dalam lift yang naik menuju lantai kamar mereka, yang kebetulan tak ada orang lain selain mereka, Atik mengalungkan lengannya ke pundak lelaki itu, mencondongkan dadanya ke dada lelaki itu, dan mereka berciuman panjang. Trik ini berhasil membuat lelaki itu langsung menggumulinya begitu mereka masuk ke dalam kamar. Tidak sempat ada obrolan filsafat di kamar itu seperti yang pura-pura tokoh kita kehendaki saat sepakat untuk kencan. Tidak pula sempat ada makan bareng romantis sebagaimana yang mereka peragakan secara virtual dalam beberapa hari sebelumnya.
Menindihi tubuh Atik yang telentang di kasur, Harley bagaikan harimau kelaparan yang tak makan berhari-hari. Gaun tiga perempat yang dikenakan Atik memudahkan Harley menelanjanginya.
***
Enam jam kemudian. Lelaki bernama Harley itu terbagi menjadi potongan-potongan. Sebagian tubuhnya dimasukkan ke dalam dua koper, dan sisanya ke dalam ransel. Dengan taksi yang dipesan lewat aplikasi daring, potongan-potongan tubuhnya dibawa ke apartemen lain. Apartemen K, namanya.
Dompet lelaki itu kini berada di tangan Atik. Di dalam dompet itu, selain beberapa lembar uang, ada enam kartu yang diselipkan pada slot-slot kecil di sisi kanan dan kiri dompet, termasuk ATM, yang isinya dia kuras habis bersama kekasihnya—pria yang dengannya ia saling berkirim pesan teks, yang tinggal bersamanya di kontrakan.
Segera setelah adegan percintaan yang tak tuntas itu, Atik bergegas berpakaian, memakai jins hitam dan kaos oblong putih yang telah disiapkannya di dalam tas. Gaun tiga perempat yang dipakainya sebelumnya, dijadikan lap untuk membersihkan darah yang berceceran.
Sebelum menghabisi nyawa Harley, Atik sempat berkata, “Jika kamu percaya bahwa ada tempat di mana Tuhan tiada, kamar ini adalah salah satunya.”
Harley, si lelaki manajer HRD itu, terkulai setelah kepalanya tiga kali dihantam dengan batu dan punggungnya ditikam oleh seorang pria yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Pria itu keluar dari persembunyian tepat sebelum ia hendak melakukan penetrasi ke tubuh Atik.
“Sebutkan password HP-mu,” bentak pria itu usai melayangkan tikaman kedua.
Meringis kesakitan memegangi luka tusukan pada pinggangnya, terpojok di sudut kamar dalam keadaan telanjang, Harley memberitahu kata sandi ponselnya. Ia tak sempat berpikir untuk berteriak meminta tolong.
“Sekarang, berapa PIN ATM-mu?”
Menangis ketakutan, Harley menyebutkan PIN ATM-nya, dan memohon agar dirinya tidak dibunuh.
“Kau tahu siapa aku?”
Ia tidak bisa menjawab. Ketakutan benar-benar melumpuhkannya.
“Kalau kau kami biarkan hidup, apa kau tak akan melapor ke polisi?”
“Saya enggak akan melapor. Saya janji,” ucapnya, memelas.
“Mana mungkin!”
Setelah berkata demikian, pria itu langsung menikam Harley berkali-kali. Dan Atik, betapapun dia telah mengumpulkan keberanian untuk mewujudkan rencana yang telah dia siapkan matang-matang bersama kekasihnya, tetap saja merasa ngeri saat menyaksikan lelaki yang dengannya dia mengobrol seru lewat panggilan video dalam beberapa hari terakhir, dihabisi dengan cara sesadis itu.
Walau begitu, sebelum kekasihnya memotong-motong mayat lelaki itu menjadi sebelas bagian seperti seekor sapi yang hendak dijual ke pasar, untuk membuktikan kepada kekasihnya bahwa dia tidak sempat main hati dengan lelaki itu, Atik memungkasi penyiksaan itu dengan sebuah tikaman di leher. (*)
Keterangan:
*Tempat di Mana Tuhan Tiada adalah salah satu judul bab dalam novel ‘Salju’ karya Orhan Pamuk.
Abul Muamar, lahir di Perbaungan, Serdangbedagai, 6 November 1988. Alumnus Pascasarjana Filsafat UGM. Saat ini bekerja sebagai redaktur media online berbasis di Jakarta. Menulis buku kumpulan cerpen bertajuk ‘Pacar Baru Angelina Jolie’ (Gorga, 2019).


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





