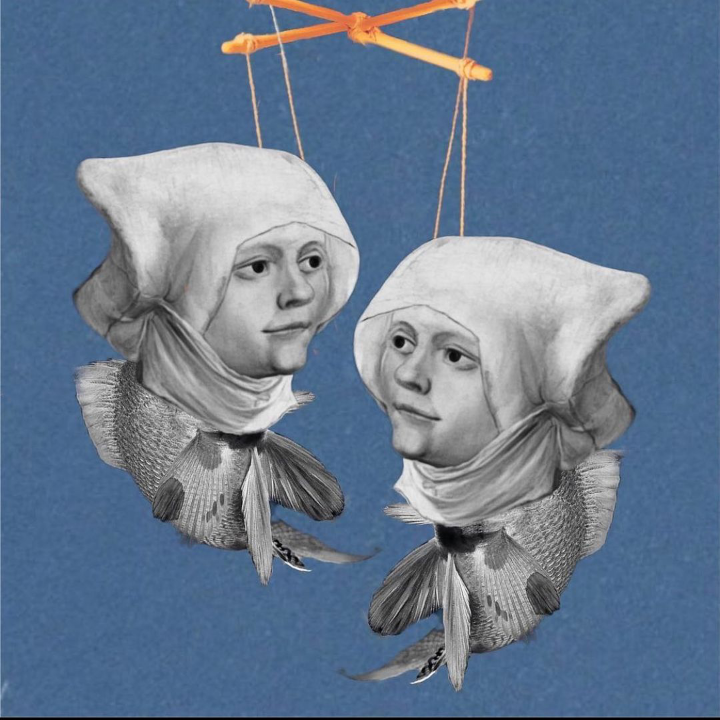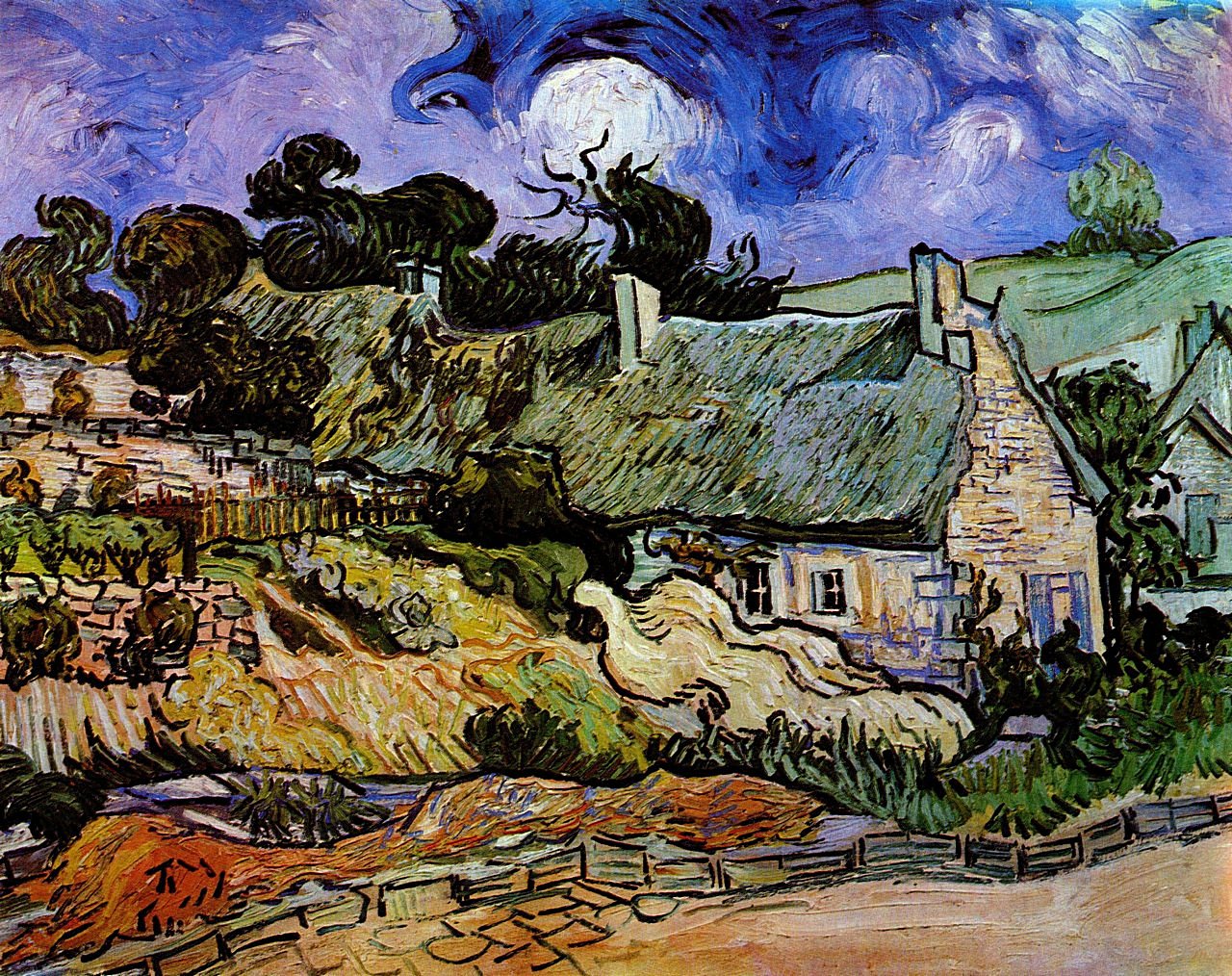Rencana Bunuh Diri Ke-187 | Cerpen: Tiqom Tarra
Ini adalah rencana bunuh diriku keseratus delapan puluh tujuh. Sejauh ini aku telah merencanakan ratusan percobaan bunuh diri dalam hidupku. Dan yang mengesankan adalah bahwa semua rencana bunuh diriku itu selalu gagal; nyawaku masih saja tidak mau enyah dari tubuhku yang tidak berharga ini. Apakah bunuh diri memang sesulit itu?
Aku lihat di televisi, orang lain mudah saja bunuh diri; hanya menenggak larutan racun tikus mereka langsung meregang nyawa dengan mulut berbusa dan terkejang-kejang menyedihkan. Sayangnya, bagi tubuhku racun tikus tidak bekerja sebagaimana mestinya dan dokter selalu bisa menyelamatkan nyawaku; membuatku harus menjalani hidup yang tidak aku inginkan untuk kemudian kembali merencanakan bunuh diri selanjutnya.
Harus kuberitahu bahwa kegagalanku dalam bunuh diri bukan disebabkan karena aku takut menghadapi kematian. Aku telah siap lahir batin untuk mati. Akan tetapi, agaknya Tuhan masih ingin aku hidup dan menjalani kesengsaraan dunia. Aku pernah meminta saran dari seorang kakek tua yang tinggal di gang sempit dekat pasar mengenai cara bunuh diri. Kakek Tua yang sekilas terlihat seperti orang gila itu telah membantu banyak orang untuk bunuh diri dengan saran-sarannya. Namun, saran untukku tidak berjalan lancar. Dia memberiku saran untuk bunuh diri di rel kereta; membiarkan tubuhku tertabrak gerbong tanpa ampun kemudian terseret atau terlindas hingga tak berbentuk lagi. Itu adalah cara bunuh diri terbaik dan termudah untuk orang yang sudah sangat putus asa sepertiku.
Aku yakin cara itu akan berhasil membuatku mati. Aku sudah membayangkan kematian yang indah. Aku sudah membayangkan nikmatnya meninggalkan hidup yang menyengsarakan ini. Namun, rencana yang sudah kususun itu hancur berantakan ketika temanku menghalangi dengan tangis yang memilukan. Temanku bersikeras aku harus hidup. Ini tidak semenyengsarakan yang kau pikir, begitu katanya diikuti semua kata-kata yang membuatku bingung dan aku menyerah.
Baiklah untuk kali ini aku menyerah demi temanku yang cengeng, begitu kataku dan kami pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa.
Esoknya aku kembali ke gang sempit dekat pasar untuk meminta saran lagi pada Kakek Tua. Namun, yang kutemui adalah kerumunan orang yang sedang berdesakan di gang sempit di mana Kakek Tua harusnya berada. Setelah aku merangsek dengan susah payah, barulah aku tahu kalau Kakek Tua yang seperti orang gila itu telah menjadi korban pembunuhan semalam. Tubuh tua terbalut baju dan sarung kumal itu terbujur bersimbah darah di dekat gerobak tempatnya biasa tidur.
Sial, makiku. Orang yang harusnya memberiku saran bunuh diri justru meregang nyawa lebih dulu sebelum bunuh diriku sukses.
Dari bisik-bisik kerumunan kuketahui kalau Kakek Tua ditusuk seorang pemuda semalam. Pemuda itu beberapa hari yang lalu menemui Kakek Tua untuk meminta saran bunuh diri, namun rencana bunuh dirinya gagal entah apa sebabnya. Dan karena kesal pemuda itu melampiaskannya pada Kakek Tua.
Dasar sinting! Aku ingin memaki pemuda bodoh itu. Kalau Kakek Tua mati lalu bagaimana aku dan dia meminta saran bunuh diri?
Pemuda bodoh itu dijebloskan ke penjara setelah persidangan, sedangkan aku—yang sudah sangat putus asa dengan hidup ini—dijebloskan ke tempat yang lebih mengerikan oleh keluargaku; di mana seluruh ruangan berwarna putih, dan orang-orangnya memakai baju dan jubah putih. Setiap pagi dan malam hari mereka membawakanku obat berwarna putih yang pahitnya luar biasa. Di hari lain mereka menusuk lenganku dengan jarum berisi cairan yang membuatku lemas kemudian kesadaranku menghilang.
Aku dikurung di ruang putih itu sendirian dengan kamera pengintai yang terus mengawasiku. Keadaanku bahkan lebih menyedihkan dibanding pemuda bodoh yang telah menusuk Kakek Tua hingga tewas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ingatanku juga sedikit kacau karena sering kehilangan kesadaran setelah orang berbaju putih menyuntikkan cairan ke tubuhku. Terakhir aku ingat aku mencoba bunuh diri dengan cara menenggelamkan diriku di bak mandi. Aku mendengar teriakan ayah dan ibuku, juga suara pintu yang didobrak tepat sebelum aku kehilangan kesadaran. Aku pikir aku telah berhasil bunuh diri.
Ah, akhirnya aku berhasil, pikirku. Namun, ketika aku membuka mata, bukannya surga atau neraka yang aku lihat, melainkan ruangan putih dengan bau antiseptik yang menyengat. Aku menemukan diriku dalam keadaan terikat di ranjang dan tepat di sudut ruangan kamera pengintai itu mengawasi seolah di sebelah ruangan sana ada sekumpulan orang yang menjadikanku nontonan. Dan di antara mereka berdiri Ayah, Ibu, dan saudaraku—dan mungkin juga temanku yang pernah mengagalkan rencana bunuh diriku. Temanku mungkin akan menangis melihatku dari layar monitor seperti yang biasa dia lakukan ketika mengetahui aku mencoba bunuh diri.
Dan ini adalah rencana bunuh diriku keseratus delapan puluh tujuh. Aku telah mencoba bunuh diri beberapa kali di ruang putih ini, tapi selalu gagal karena kamera pengintai selalu membuat orang-orang berbaju putih berhasil menyelamatkanku sebelum nyawaku enyah. Aku benci benda bulat yang seperti mata itu.
Ini adalah rencana bunuh diriku yang keseratus delapa puluh tujuh. Aku telah banyak mempelajari aktivitas orang-orang berbaju putih. Sekitar puluh enam pagi, di mana embun di luar sana mulai menguap, seorang wanita kurus akan membawakanku sarapan dengan menu bubur dan abon sapi. Jujur aku katakan itu adalah bubur paling tidak enak sedunia. Sepertinya pembuatnya tidak tahu takaran garam karena rasanya selalu keasinan. Namun, aku harus menghabiskan bubur itu di bawah tatapan wanita kurus yang membawanya.
Setelah bubur habis tanpa sisa dia akan memberiku obat pahit. Aku tidak tahu itu obat apa. Obat itu memiliki efek yang hampir sama dengan cairan yang disuntikkan ke lenganku. Keduanya sama-sama membuatku kehilangan kesadaran. Hanya saja obat ini efeknya tidak separah cairan. Jika yang cair langsung membuatku kehilangan kesadaran seketika, maka pil ini hanya membuatku mengambang seperti setengah terbang. Sulit untuk menjelaskannya. Aku hanya seperti tidak berada di tempatku. Aku benci obat itu sama seperti aku benci bubur keasinan yang harus aku makan.
Setelah prosesi sarapan dan minum obat selesai, wanita kurus itu akan keluar diikuti suara kunci pintu. Mereka tidak membiarkanku kabur. Aku hanya akan sendirian di ruangan itu. Sepi sekali. Kadang aku menangis ketika teringat teman-temanku di sekolah. Aku rindu sekolah. Aku rindu pelajaran Fisika yang memusingkan. Aku rindu kakak kelas yang membuatku senyam-senyum kasmaran. Aku rindu temanku yang cengeng dan cerewet. Dan aku rindu percobaan bunuh diriku. Ketika semua kerinduan itu membuncah dalam diriku dan aku tidak bisa mengendalikannya, orang-orang berbaju putih akan masuk dengan tergesa. Mereka segera menangkapku, memegangi lenganku kuat-kuat sebelum menyuntikkan cairan yang membuatku melemah dan kehilangan kesadaran.
Ketika kesadaranku menghilang, aku melihat teman-temanku yang sedang bermain di lapangan sekolah. Mereka tertawa dengan riang, sedangkan aku tidak bersama mereka. Tangan dan kakiku terikat, kemudian muncul pria-pria berbadan besar. Mereka melucuti pakaianku dengan tawa yang mengerikan. Aku berteriak, menangis, tapi mereka justru makin senang. Aku takut. Aku memanggil teman-temanku, tapi tidak ada yang mendengar. Lalu satu per satu pria berbadan besar dengan tawa mengerikan itu membuka kakiku. Mereka memasukiku. Rasanya sakit luar biasa. Aku seperti ditusuk dengan besi panas. Aku berteriak lebih keras hingga aku tidak bisa mendengar teriakanku sendiri. Dan di sinilah aku berada; di sebuah bilik rumah sakit jiwa.
Ini adalah percobaan bunuh diriku keseratus delapan puluh tujuh. Aku sudah bosan hidup, tapi aku harus bersabar untuk mengelabuhi orang-orang berbaju putih dan kamera pengintai yang bisa menggagalkan rencanaku. Aku makan dengan teratur dan minum obat tanpa ada lagi paksaan.
“Bagus. Kalau kau menurut seperti ini terus, kau bisa keluar dari sini lebih cepat.” Wanita kurus yang membawakanku obat tersenyum semringah setelah aku meminum obat.
Wanita itu bilang keadaanku mengalami perkembangan pesat. Terhitung sudah sebulan ini aku tidak lagi mengalami serangan panik. Kau menunjukkan perkembangan, begitu katanya. Aku hanya mengangguk dengan senyum sebelum mengambil sebuah buku cerita berjudul The Little Prince.
Selain wanita kurus yang membawakanku makanan dan obat, ada juga wanita berjilbab yang menemuiku tiga hari sekali. Biasanya dia akan bertanya tentang mimpiku semalam, juga apa hal yang ingin kulakukan. Sebenarnya aku benci wanita berjilbab ini, dia banyak bertanya. Tapi demi rencana bunuh diriku, aku harus bersabar.
Aku mengarang cerita tentang mimpiku; aku bertemu dengan teman-teman sekolahku. Aku juga bilang kalau aku berharap bisa bertemu dengan kakak kelas yang aku sukai. Di lain waktu cerita itu sedikit kuubah dengan mengganti teman menjadi keluarga, atau kakak kelas menjadi pelajaran Fisika. Wanita berjilbab tersenyum senang mendengar jawabanku.
Ini adalah rencana bunuh diriku keseratus delapan puluh tujuh. Aku yakin tidak akan gagal meski kamera pengintai itu masih terus mengawasiku. Aku senang melihat orang-orang berbaju putih percaya bahwa aku tidak akan mencoba bunuh diri lagi hanya karena aku bersikap baik dan meminum obat seperti perintah mereka. Namun, mereka tidak tahu kalau obat-obat itu tidak pernah melewati kerongkonganku. Obat itu hanya aku sembunyikan di bawah lidah untuk kemudian aku simpan di bawah bantal.
Aku sudah mengumpulkan obat-obat itu sejak sebulan terakhir. Jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk membuatku overdosis. Kalau obat itu bisa membuat setengah kesadaranku menghilang dengan dosis yang tepat, artinya dengan dosis yang melebihi batas obat itu bisa membuatkku kehilangan kesadaran selamanya. Maka, malam ini, beberapa jam setelah wanita kurus itu memberiku obat dan mengunci pintu, aku berbaring di ranjang dengan selimut menutupi hingga kepala. Di bawah selimut aku menelan satu per satu obat yang telah aku kumpulkan.
Ini adalah rencana bunuh diriku keseratus delapan puluh tujuh, dan aku yakin kali ini aku berhasil ketika semua yang kulihat bukan lagi ruangan putih, melainkan gelap dan aku damai di dalamnya. Hidup, selamat tinggal. Aku bebas!
Tiqom Tarra, lahir dan besar di Pekalongan. Kini tinggal di Jembrana, Bali. Cerpen-cerpennya pernah dimuat di Kompas id, Majas, Media Indonesia, Detik.com, Gogirl, Tribun Jabar, Denpasar Post, Harian Solopos, Radar Surabaya, Fajar Makassar, Apajake id, dan ideide id. Buku kumpulan cerpen perdana Anak Kecil yang Memamerkan Bayinya dan Orang Dewasa yang Menyimpan Biji Mentimun di Saku Celana (2018).


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co