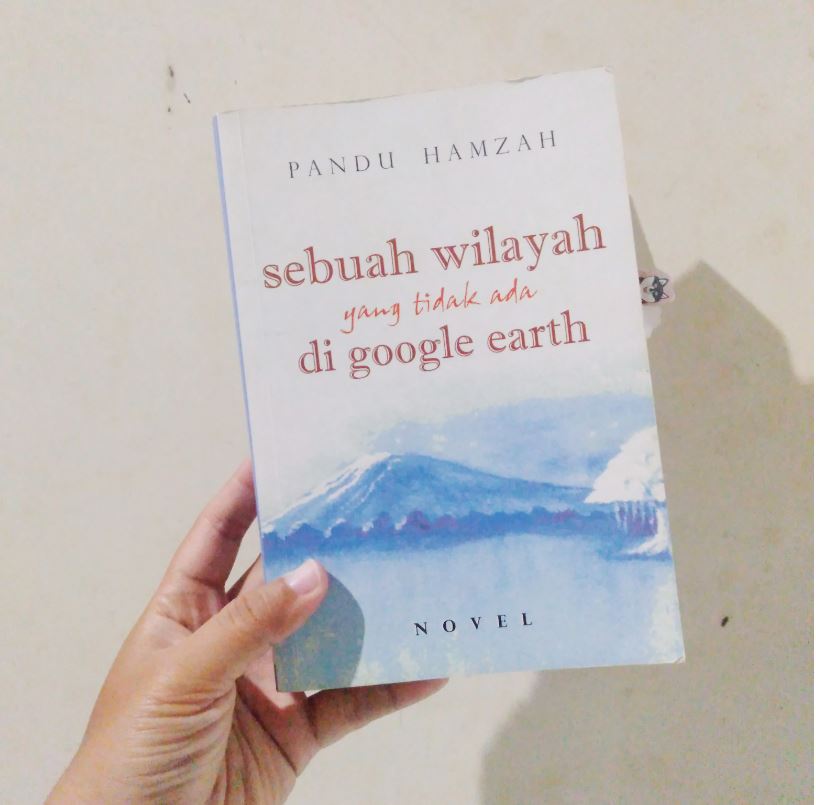
Novel “Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth”: Kritik Lingkungan via Sastra
Berita Baru, Novel – Sastra dapat menjelma jadi sarana bermacam hal. Melarikan diri dari putus cinta, mengabadikan momen romantis, membagikan kisah-kisah lucu, dan banyak lagi. Salah satu jelmaan sastra adalah menjadi bentuk kritik, perlawanan, dan perjuangan menghadapi ketidakadilan di masyarakat.
Itu kiranya yang ingin Pandu Hamzah lakukan ketika menulis “Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth.” Novel ini digadang-gadang sebagai sastra ekokritik, yakni sastra yang memuat kritik mengenai isu ekologis atau isu lingkungan.
Mengambil judul yang cukup dramatis, novel ini berniat mengisahkan apa-apa yang terjadi ketika dan setelah Chevron menjajaki Gunung Ciremai, Kuningan, sebagai area proyek pembangkit listrik geothermal miliknya. Kita tahu, hal itu merupakan kisah nyata.
Tentu saja masuknya Chevron menimbulkan kontroversi. Warga menolak karena mempertimbangkan dampak proyek tersebut terhadap potensi kerusakan lingkungan di sekitar Gunung Ciremai.
Sinopsis Novel “Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth”
Laksmi stress. Seperti warga Pajambon, Cisantana, Palutungan, dan sekitarnya. Rasa khawatir mereka memuncak gara-gara takut jika desas-desus itu benar: mereka akan dipindahkan, sementara lahan dan ladang mereka akan digunakan untuk pembangunan instalasi pemanfaatan energi geothermal oleh Chevron, pemodal dari Amerika sana.
Pengikisan ini nyata. Warga sekitar bakal kehilangan hak atas hutan sebagai sumber penghidupan, padahal Ciremai di bawah sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHMB) sudah berjalan bagus, partisipatif, dan tak memiliki kecenderungan memiskinkan warga. Dalam kondisi rentan stress ini, investor mulai menjilat-jilat telinga warga, menggoda warga agar sudi tanahnya dibeli. Tentu investor jadi gila begini demi kecipratan untung dari proyek Chevron. Mereka seperti bremara mencari cahaya; bedanya, bremara satu ini jelas terbuat dari api keserakahan neraka.
Stress tak hanya dialami warga yang takut kehilangan tanah, tapi juga seorang Lelaki Penebang Pohon. Disebut demikian karena dia telah menebang satu-satunya Pohon Kiara besar di kawasan Gunung Ciremai. Penebangan itu semata-mata dilakukan untuk mendirikan pemancar televisi.
Karena pohon Kiara ditebang, mata air di sekitar menjadi kering. Untungnya Lelaki Penebang Pohon ini masih punya rasa malu dan kesadaran bahwa tindakannya itu merusak alam. Dia merasa kerdil di hadapan puisi-puisinya yang kerap menggunakan idiom alam tapi justru demi pemancar itu, dia tega menebang pohon.
Risaunya kian membuncah ketika dia didatangi makhluk Ulu-Ulu yang biasa tinggal di gunung. Ulu-ulu itu muncul dalam bentuk seorang laki-laki bernama Zasu. Hidup Lelaki Penebang Pohon semakin tak tenang: mengapa Ulu-ulu mencarinya? Apakah ia telah melakukan kesalahan?
Lelaki Penebang Pohon itu takut, namun rasa penasarannya lebih tinggi. Desakan-desakan di hati menuntunnya pergi mendaki Ciremai, sendirian, mencari solusi.
Sementara itu, gara-gara Pohon Kiara ditebang, Gadis Ajag (anjing hutan) dan anak laki-laki bisu bernama Si Hitam kehilangan tempat bermain. Keduanya pun meminta pertolongan Malaikat Kebahagiaan dan Ibu Burung Walik agar Pohon Kiara bisa tumbuh lagi di sana, mata airnya hadir lagi, para ajag bisa melaksanakan ritual mereka di sana seperti biasa, juga semesta alam kembali menikmati kesegaran alami Ciremai.
Kritik Lingkungan Melalui Karakter-karakter Alam
Dari judulnya saja, “Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth” sudah bikin jatuh hati dan tinggi ekspektasi. Tentu saya jadi menduga, wilayah mana yang dimaksud tak muncul di Google Earth? Sebuah pelosokkah? Apa yang menjadikannya tak ada di Google Earth? Kekuatan mistis? Keterbatasan teknologi?
Ternyata tidak, kita diajak bicara soal Ciremai. Kawasan Gunung Ciremai jelas bukan wilayah pelosok, meski cita-cita kapitalis hampir menjadikannya tak familiar lagi.
Novel ini mengisahkan manusia yang sering kalah di tanahnya sendiri gara-gara manusia lain lebih berbinar melihat dolar-dolar di saku para pemodal daripada mengusur warga tak mampu.
Yang membedakannya dari tulisan lain mengenai kritik atas naik gunungnya para pemodal adalah, Kang Pandu menggunakan narasi dengan kisah dan tokoh yang tidak biasa; menjadikannya unik dan enak dinikmati.
Sudut pandang yang dipakai pun menarik, misalnya binatang. Kehadiran Malaikat Kebahagiaan, Desa Para Pembuat Hujan, juga makhluk alam seperti Ulu-ulu menjadi bagian dari perlawanan yang Kang Pandu lakukan; sebuah perlawanan yang tenang namun kuat; perlawanan budaya. Dan kita dibawanya melawan bersama sebenar-benarnya entitas dari alam.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





