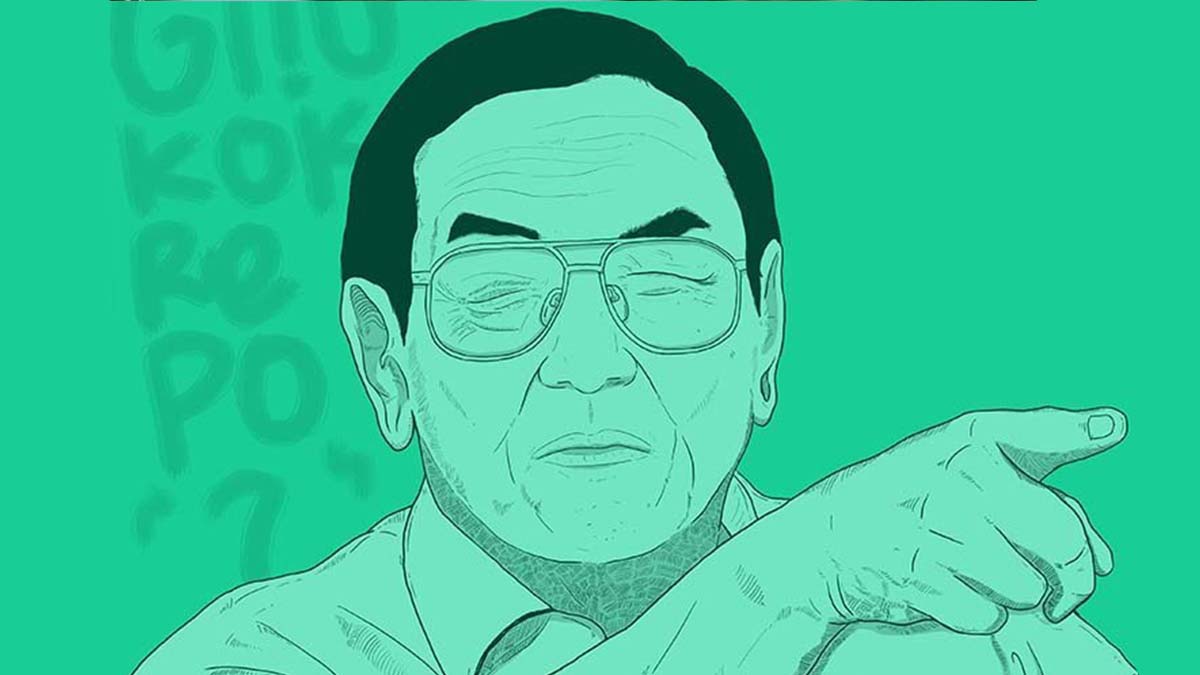
Gus Dur Dalam Sebait Puisi
Gus Dur Dalam Sebait Puisi
Oleh: Lev Widodo
Gus Dur dalam sebait puisi dan selaksa kerinduan. Gus Dur tidak pergi, hanya kembali
Yā man tabḥatsu ‘an marqadinā
Qabrunā hādzā fī shudūr al-‘ārifīn
Wa qulūb al-majrūḥīn
Duhai kalian yang mencari tempat tidurku
O, lihatlah… aku ada di dalam palung jiwa para bijak bestari
Dan mereka yang hatinya terluka
Itulah jawaban Gus Dur atas puisi rindu yang dibacakan sahabatnya, Kiai Husein Muhammad, pada peringatan lima tahun kematiannya. Kiai Husein mencatat jawaban tersebut dalam Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus (Noura Books, 2016), sebuah buku yang membicarakan Gus Dur dari sudut pandang Gus Mus.
Bahwa manusia yang telah meninggal berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup, hal itu wajar-wajar saja dalam jagad spiritual. Kita tentu ingat dengan adagium ini: betapa miskinnya penempuh jalan spiritual yang hanya berguru kepada yang hidup. Dan Kiai Husein dan Gus Dur adalah penempuh jalan spiritual yang berdialog dengan puisi.
Berangkat dari bait yang pendek, ringkas, dan padat di atas, kita bisa mengenang Gus Dur dengan perspektif yang bening dan dalam. Selain membayangkan gerakan sosial Gus Dur yang sifatnya lahiriah, bait tersebut juga menggoda kita untuk menapaktilasi jejak gerakan spiritual Gus Dur yang sifatnya batiniah dan amat personal.
Setelah Gus Dur meninggal, lebih kurang tujuh tahun lalu, kita merasa kehilangan, merasa ditinggalkan. Tiba-tiba kehadiran Gus Dur jadi sangat berharga. Kita jadi seperti sekumpulan anak ayam yang sekonyong-konyong ditinggal pergi sang induk untuk selamanya.
Maka, tanpa komando dari siapa pun, anak-anak ayam yang bingung itu mencari-cari induknya. Ada kerinduan yang semakin lama semakin meluap kepada Gus Dur. Ada keinginan untuk berjumpa dengannya. Orang-orang pun, dari berbagai latar belakang sosial, berduyun-duyun membicarakan Gus Dur, membolak-balik lembaran tulisannya, dan menziarahi kuburannya. Tapi, apakah yang mereka temukan? Apakah kerinduan kita terjawab?
Nyatanya, sepeninggalan Gus Dur, barangkali kita tidak (mau) maju selangkah pun dalam kebudayaan, apalagi dalam agama, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, kita malah berjalan mundur. Hingga sekarang, belum juga reda puspa ragam bencana: bencana alam, bencana ekonomi, bencana politik, bencana hukum, bencana pendidikan, bencana kebudayaan, bahkan bencana agama.
Di mana-mana orang berebut menang, berebut benar, berebut tinggi. Ketika keakuan menyesaki kehidupan, tanpa sadar kita pun menjauh dari tritunggal kudus: cinta, damai, dan persatuan. “Aku” tidak menyapa “engkau” dan “engkau” pun tidak menyapa “aku”. “Kami” tidak menghampiri “mereka” dan “mereka” pun tidak menghampiri “kami”. Akibatnya, “kita” jadi sesuatu yang jauh.
Hikmah perbedaan, yaitu ta’āruf, yaitu jihad untuk saling mengenal, mulai dilupakan. Ketakwaan dilucuti dimensi sosialnya. Aku memang kenal engkau, kami memang kenal mereka, tapi sebatas nama, sekadar paras. Tidak ingin, juga tidak perlu, lebih. Maka, wajar kalau kita serasa hidup di gurun yang gersang. Wajar pula kalau sumbu konflik gampang terbakar. Benci balas benci. Marah balas marah. Tampar balas tampar. Ah, kehidupan ini rupanya telah sepanas neraka. Bahkan air pun jadi panas, jadi api, jadi azab, jadi bencana.
Di mana sikap ihsan, yang merupakan hulu dan hilir sungai keadilan, bersembunyi kini? Di mana murid-murid Isa yang rela memberikan pipi kanannya setelah pipi kirinya ditampar? Di mana penerus Sokrates yang pada bekas tamparan di wajahnya menulis kalimat jenaka: “seseorang telah menamparku dan inilah balasan dariku”? Di mana anak-anak ideologis Gus Dur yang berani menertawakan keakuan pribadi, yang siap mengalah demi persatuan?
Di mana pengikut Baginda Muhammad yang membesuk orang yang meludahinya, yang dengan sabar menyambung tali cinta (silaturahmi) yang terputus? Masihkah kita percaya bahwa hari kiamat pasti datang? Masihkah kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Cinta dan Maha Adil? Masihkah kita menyaksikan-Nya dengan mata hati, atau paling tidak merasa diawasi oleh-Nya?
Barangkali, jumlah kaum muhsin, orang-orang pemaaf yang dicintai Tuhan itu, semakin sedikit saja. Yang semakin banyak justru orang-orang yang merasa lebih, yang merasa bisa dan tidak bisa berempati dengan orang lain. Yang juga semakin banyak adalah barisan korban mereka: kaum dhuafa, subaltern, marjinal, terdiskriminasi, tertindas, terpinggir, tersingkir, tersisih, terlupakan. Siapa kini yang memperhatikan mereka, menemani mereka, membela mereka?
Kata ‘maaf’ pastilah sukar keluar dari mulut para korban yang tinggal dalam goa gelap kebencian, dendam, dan keputusasaan tersebut, kecuali jika mereka ditemani, dianggap ada, dibantu dengan tulus, dimanusiakan, dicintai. Gus Dur, dalam bait puisi di atas, menyebut mereka sebagai orang-orang yang hatinya terluka. Yang dilukai adalah kemanusiaan mereka. Dan luka itu akan semakin menganga dan semakin perih jika tak segera diobati.
Demokrasi, sebagai prinsip sekaligus mekanisme keadilan, sebenarnya adalah obat untuk mengobati luka tersebut. Tapi, bagaimanakah demokrasi kita sekarang? Ah, betapa sulitnya membedakan pemimpin dan pencuri. Betapa payahnya memilah manusia dan binatang.
Kita merindukan kemanusiaan. Kita merindukan politik yang bersendikan kemanusiaan. Kita merindukan pemimpin yang arif, yang mengenal Tuhannya, juga mengenal hakikatnya sebagai manusia, sebagai hamba sekaligus mandataris Ilahi. Dalam bait di atas, Gus Dur menyebut pemimpin dengan derajat spiritual tinggi seperti ini sebagai kaum bijak bestari, kaum ‘ārifīn. Mereka adalah induk bagi anak-anak ayam, adalah ibu bagi umat, adalah pa(mo)mong, adalah bocah angon.
Seperti Sunan Kalijaga, bocah angon menyeru umat menuju balai paseban, tempat yang membahagiakan, terasa lapang, dan terang oleh cahaya rembulan. Seperti Sunan Gunung Jati, bocah angon mendayagunakan potensi demokratis tajug dan memberdayakan fakir miskin. Seperti Sunan Drajat, bocah angon memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, memberi payung yang kehujanan, menuntun yang buta. Seperti Semar dan anak-anaknya, pa(mo)mong menemani rakyat, juga pemimpin, bahkan hidup bersama rakyat dan sebagai rakyat.
Mereka, kaum arifin itu, berpihak kepada golongan yang lemah dan kalah secara struktural. Kaum arifin melantunkan tembang cinta untuk mengobati luka kemanusiaan, untuk meruwat libido raksasa yang mendekam dalam dada, untuk meredakan berbagai bencana, untuk meninggalkan malam kalabendu demi menyongsong fajar kalasuba. Optimisme kolektif mesti dibangun dari bawah dengan keberpihakan sosial yang tulus. Tanpa cinta, mungkinkah sistem yang korup dan struktur yang zalim direformasi? Cinta itulah yang tersimpan sebagai rahasia dalam palung jiwa para bijak bestari, dalam lubuk dada kaum arifin.
Karena itu, pada bait di atas, Gus Dur berpesan: jangan hanya mencariku di tempat tidurku. Jangan berpuas hati dengan hanya menziarahi kuburanku. Tapi ziarahi pulalah lubuk dada kaum arifin dan hati manusia yang terluka. Aku sejatinya masih hidup di sana. Di dalam liang kuburku hanya terpendam jasad yang tak bisa menjawab.
Ya, Gus Dur sesungguhnya masih hidup, selama kemanusiaan masih terluka dan selama kaum arifin masih bergerak untuk menyembuhkan luka itu. Sejatinya Gus Dur tak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa hadir bersama kita.
Bumi Mataram, malam Senin, 25 Dulkangidah 1437 H [TubanJogja]


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





