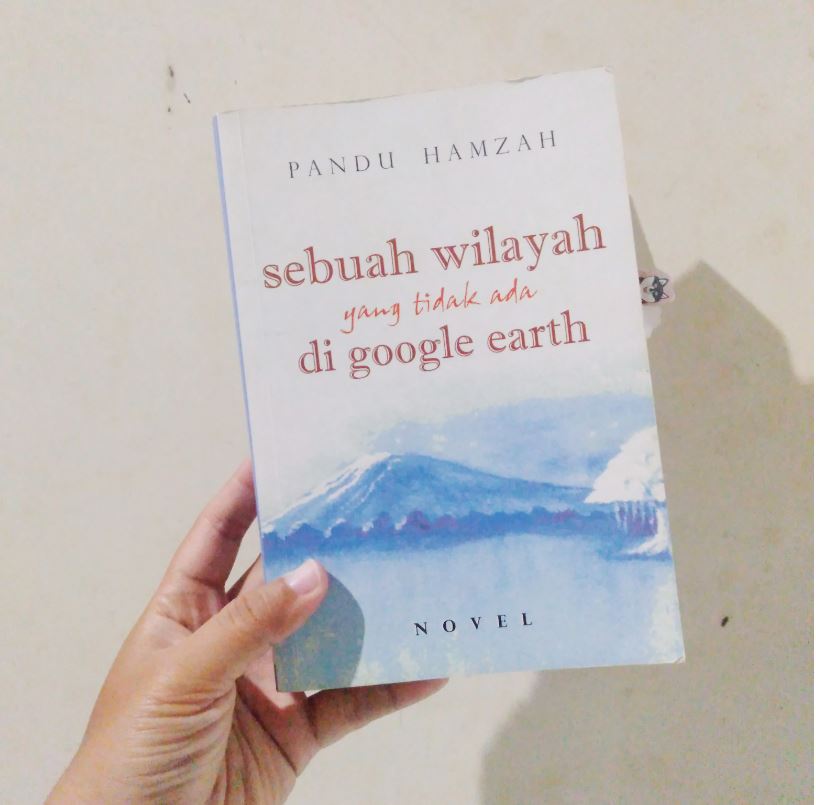Aroma Tanah Liat | Cerpen Polanco S. Achri
MENDUNG dan pekerjaan ini hari sudahlah rempung—
Tadi, saat masih mengapur dinding perkuburan, kau mendapati seorang perempuan ayu yang berziarah sambil membawa seikat kembang. Seharian tadi tiada yang berziarah; dan karenanya, kedatangan itu, kehadiran perempuan itu, begitu terasa dan teringat di kepalamu. Di depan sebuah makam yang bernisan indah, perempuan itu berdoa dan meletakkan seikat bunga berwana merah. Dan saat pulang, pandang mata kalian bertemu: ia mengangguk tanda sopan, dan kau pun membalasanya dengan sepontan.
Alat-alat sudah kau bereskan, sudah kau simpan di dalam sebuah bangunan, yang ada di sudut di dekat pintu masuk perkuburan, sebab esok hari kau mesti melanjutkan agar genap selesai pekerjaan. Di depan sebuah makam, yang mana diziarahi oleh perempuan tadi, kau berdiri terdiam: membaca nama pada nisan dan membaca sebuah epitaf pada sebuah batu yang tidaklah benar-benar bisu. Lantas, kau pun menyatukan sepasang tangan: berdoa. Dan tersebab mendapati si empunya makam meninggal di kala masih muda, di kala masih kanak berusia, maka kau pun merendah dan menceritakan sebuah pendek kisah. Selepasnya, selepas rambung pendek sebuah kisah, kau pun pamit kepada si empunya makam.
Kau mencuci tangan dan kaki, serta membasuh muka; berganti pakaian dengan kemeja bersih dan celana jin panjang. Dan sambil membawa sebuah tas berisi buku dan juga beberapa naskah, kau segera berjalan untuk melanjutkan urusan . . . .
LANGIT makin gelap dan dingin menyergap.
Didorong naluri, selepas selesai urusan di rumah seorang kawan, kau bergegas pulang kembali; kau takut kehujanan, takut naskah puisi yang kau bawa jadi kebasahan. Akan tetapi, hujan sudah terlebih dahulu turun!
Hujan turun terlampau deras dan kau lupa memasukan sebuah payung ke dalam tas. Untunglah, di depan ada sebuah rumah dengan gapura yang beratap dan bisa dipakai untuk berteduh. Akan tetapi, meski dapat berteduh lekas, hujan yang terlampau deras sudahlah berhasil membuatmu kuyup. Dan meski begitu, kau tetap bersyukur, sebab naskah dan buku-buku yang kau bawa tidaklah basah.
Untung tas ini tahan air, ucapmu lega.
Dan hujan masih deras, masih belum mau pergi lekas.
Sambil menahan dingin dan juga gigil, sebab pakaianmu telah basah, kau memandang jalanan. Matamu mendapati seorang perempuan makin mendekatimu, makin mendekati rumah yang ada di belakangmu itu. Dan betapa terkejutnya kau sebab mendapati perempuan itu adalah perempuan yang sama dengan yang tadi, yang berziarah seorang diri. Kau bergeser ke samping dengan semacam perasaan canggung, dengan senyum yang hadir amat nanggung.
Perempuan itu membuka pintu!
Selepas melewati pintu gapura, sambil memegang payung berwarna gelap, perempuan itu berkata padamu lembut:
Mari masuk, Tuan—
Kau hendak menolak, tetapi perempuan itu segera memecah benak!
Di luar hujan deras, dan mungkin akan lama reda. Mari masuk. Saya ada pengering dan air panas; juga kalau Tuan berkenan, saya juga bisa memberikan secangkir kopi ataupun teh hangat.
Kau mengangguk pelan, lantas mengikuti langkah kakinya perlahan.
Di dalam rumah itu, kau begitu terpukau. Di mana dan ke mana pun kau memandang, kau mendapati keramik dan gerabah, kau mendapati piring dan guci berwarna cerah, serta kau mendapati meja putar dan alat-alat untuk membuat serangkaian hal itu berujud-berbuah. Aroma tanah liat hadir dan menghinggapi hidungmu! Perempuan itu pun menunjukan arah kamar mandi, dan kau mengangguk canggung.
Tasmu kau tinggalkan di ruang tamu yang juga menyatu dengan ruang kerja ataupun ruang pameran karya. Kau pun memasukan pakaian basahmu ke dalam mesin cuci dan juga pengering. Lantas kau mandi dengan air panas. Saat mandi, kau tertunduk, termenung dalam di bawah shower, dan ingin sekali berkata:
Agaknya aku terjebak di dalam suatu dunia fiksi . . .
Selepas mandi, kau mengenakan pakaian yang telah kering; dan kau segera menuju ke ruang tamu. Di sana, di ruang tamu itu, kau duduk dan masih terpukau pada sekeliling. Dari suatu ruang, yang amat mungkin itu dapur, perempuan itu bertanya kau mau minum apa; dan kau lekas saja berkata: segelas kopi panas.
Kau membuka tasmu dan meski tahu hasilnya akan sama, yaitu buku dan naskah tidaklah basah, kau tetap saja melakukannya. Dan kau merasa lega—sebab jawaban ataupun kenyataan itu tidak berubah sama sekali.
Ini, ucap perempuan itu lembut sambil meletakkan secangkir kopi panas di depanmu. Silakan, sanggap saja seperti rumah sendiri.
Terima kasih, balasmu lekas sambil membenarkan posisi cangkir.
Hujan masih deras, ucapnya sambil menuju meja putar yang dipakai membuat guci atau kendi. Ada baiknya Tuan berteduh dahulu, tak usah malu; tapi bila Tuan hendak lekas, saya bisa meminjamkan payung.
Saya sedang tidak tergesa, ucapmu selepas meminum kopi. Saya hanya merasa tidak enak saja—
Tak apa, sahut perempuan itu lekas. Saya sama sekali tidak merasa direpoti.
Terima kasih.
Kau menatap luar dari jendela.
Selepas reda atau saat kopi sudah habis, batinmu, aku akan pamit pulang.
AROMA tanah liat, aroma kopi, aroma tanah terkena hujan, aroma kembang, aroma wangi dari perempuan; suara hujan, suara lirih meja putar, suara musik dari mesin pemutar, suara lembut napas seorang perempuan. Ah! itu semua membuatmu begitu terpukau. Dan selepas memandang perempuan itu hanyut pada pekerjaannya, membuat guci atau malah kendi, kau mengambil sebuah buku dari dalam tas dan membacanya.
Sendhyakala ning Majapahit karya Sanoesi Pane.
Dan waktu terasa pelan, mengalun. Dan kau telah sampai saja pada bagian akhir.
PEREMPUAN itu menyimpan pekerjaannya, mencuci sepasang tangan, dan lantas melepas celemeknya. Dilepas pula kucir dari rambutnya yang tergelung itu; dan kau pun terlampau terpukau pada hal yang demikian. Perempuan itu duduk di depanmu dan berkata:
Tuan suka membaca?
Kau meletakkan bukumu, sebab paham itu perempuan hendak memulai percakapan, sebab kau lumayan tahu cara berlaku sopan. Toh, buku itu juga sudah kau baca berulang dan berulang dan baru saja kembali kau rampungkan dan selesaikan. Dan kau pun mengiyakan pertanyaan sederhana perempuan itu.
Ah, iya, saya lupa memperkenalkan diri, ucapnya sambil menyodorkan tangan kanan. Nama saya Melati—
Kau menyambut tangan itu dan mengatakan namamu pula kepadanya. Tangan kanan yang lembut, batinmu. Dan kau pun kembali menarik tanganmu pelan.
Salam kenal, ucapnya lembut.
Dan kalian pun bercakap pelan, bercakap selumrahnya seorang yang baru kenal—
Sampai kau melontarkan tanya:
Nona . . . , bukan bermaksud lancang dan tak sopan, tapi kalau boleh tahu, siapa yang dimakamkan di sana, di tempat perkuburan yang baru saja saya kapur ini hari?
Perempuan itu tertunduk sesaat, dan kau seketika merasa bersalah serta yakin bahwa kau memang tak genap memiliki suatu sopan-santun atau sejenisnya. Akan tetapi, perempuan itu lekas bangkit, mengangkat kepalanya, dan memberi senyum tipis yang begitu halus.
Itu adik saya, ucapnya pelan. Tepatnya, kembaran saya.
Nona kembar?
Ya. Tapi adik saya mati terlebih dahulu sebab suatu penyakit. Dan semenjak itu, saya mengambil jalan untuk menggenapi harapan dan impian adik saya yang belum tercapai. Adik saya berbakat dalam membuat keramik dan gerabah, dan disiapkan menjadi pewaris dari kakek yang adalah juga seniman keramik dan gerabah. Anak kakek hanya Ibu, dan karenanya pewaris keahlian kakek begitu sempit. Tapi semua itu pupus. Sebagai kakak, yang berusaha menjadi kakak yang baik, saya menjelma dirinya: saya adalah ujud dewasa adik saya. Toh, sejak semula, saya memang kembarannya.
Selepas tersadar dari keterhanyutan mendengarkan cerita, kau lekas meminta maaf—sebab sadar benar bahwa kau telah membuka luka, telah mengorek derita lama.
Tak apa, jawab perempuan itu tulus.
Saar hendak pulang, hendak pergi dari perkuburan untuk suatu urusan, ucapmu pelan, saya menyempatkan berdoa kepada penghuni itu makam, dan menceritakan sebuah kisah pendek—
Ah, sahutnya antusias, apa Tuan tahu adik saya suka sekali pada cerita-cerita, pada buku gambar-cerita penuh warna. Bahkan, dia mau menjadi penerus kakek sebab membaca sebuah buku cerita.
Dan perempuan itu menyebut sebuah judul buku!
Adik saya begitu menyukai buku itu . . .
Ya. Saya tahu buku itu.
Adik saya suka sekali. Dan andaikan ada kelanjutannya, pastilah dia senang dan ingin sekali membaca atau mendengarnya.
Dengan nada malu-malu, kau mengatakannya:
Apa Nona tahu siapa pengarangnya—
Perempuan itu mengangguk.
Ia adalah kakek saya.
Perempuan itu terdiam sesaat. Ia mengingat-ingat namamu; dan baru tersadar bahwa kau adalah cucu dari seorang penyair-pengarang kenamaan, bahwa kau juga adalah seorang penyair-pengarang!
Jadi, Tuan . . .
Ya. Seperti dugaan Nona.
Dan perempuan itu tersenyum senang.
Ah! senyuman yang terlampau indah, batinmu.
Cerita itu, ucapmu melanjutkan, ditulis Kakek ketika masih seorang lajang. Ia menulis cerita itu untuk anak yang bahkan belum lahir, bahkan belum diketahui siapa calon ibunya. Dan ketika saya kanak, Kakek menceritakan kelanjutan ceritanya—kelanjutan daripada versi itu buku. Dan Kakek pun berkata bahwa lanjutan itu hendak dituliskan dan dibukukannya; tapi hingga ia menghilang, buku itu tidak kunjung terselesaikan.
Dan perempuan itu begitu hanyut! Lantas selepas tersadar, ia berkata:
Betapa senang adik saya bisa tahu lanjutan ceritanya.
Ya. Walau versi sederhana dan pendeknya.
Dan hujan mulai reda! Langit tampak kembali berwarna.
Di bagian akhir, ketika diceritakan oleh Kakek, dengan bahasa yang liris, Kakek suka sekali mengajukan tanya, mengajukan tanya sambil memandang jauh terkenang: Jika sebuah permintaan bisa terwujud, kau ingin menjadi apa, Nak?
Perempuan itu seolah menyadari sesuatu!
Dan perempuan itu tersenyum begitu manis. Dan kau terpukau pada hal itu.
Pandangan matamu pun mendapati luar yang terang; dan selepas genap menghabiskan minuman, kau pun mengatakan hendak pamit pulang. Maka perempuan itu mempersilakan, lantas mengantarkan hingga gerbang dan menyerahkan sebuah payung ke tanganmu.
Bukankah sudah reda, Nona?
Agar Tuan punya alasan kemari lagi.
Mendapati itu kau tersenyum dan mengiyakannya. Kau pun berjalan pulang; dan pada langkah kesekian, perempuan itu memanggilmu, memanggil namamu! Kau pun berbalik.
Saya ingin membahagiakan adik saya; dan saya sama sekali tidak menyesal menjadi seorang seniman keramik dan gerabah . . .
Kau mengangguk pelan, tersenyum, berbalik, dan melanjutkan perjalanan. Dan kau merasa lega: sebuah kendi atau guci tak lagi dicipta hanya untuk menyimpan luka dan duka diri.
(2021)
Polanco S. Achri lahir dan tinggal di Yogyakarta. Seorang lulusan jurusan sastra yang kini menjadi pengajar di sebuah sekolah menengah kejuruan di Sleman. Menulis prosa-fiksi dan juga esai-esai pendek. Dapat dihubungi via FB: Polanco Surya Achri dan/atau Instagram: polanco_achri.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co