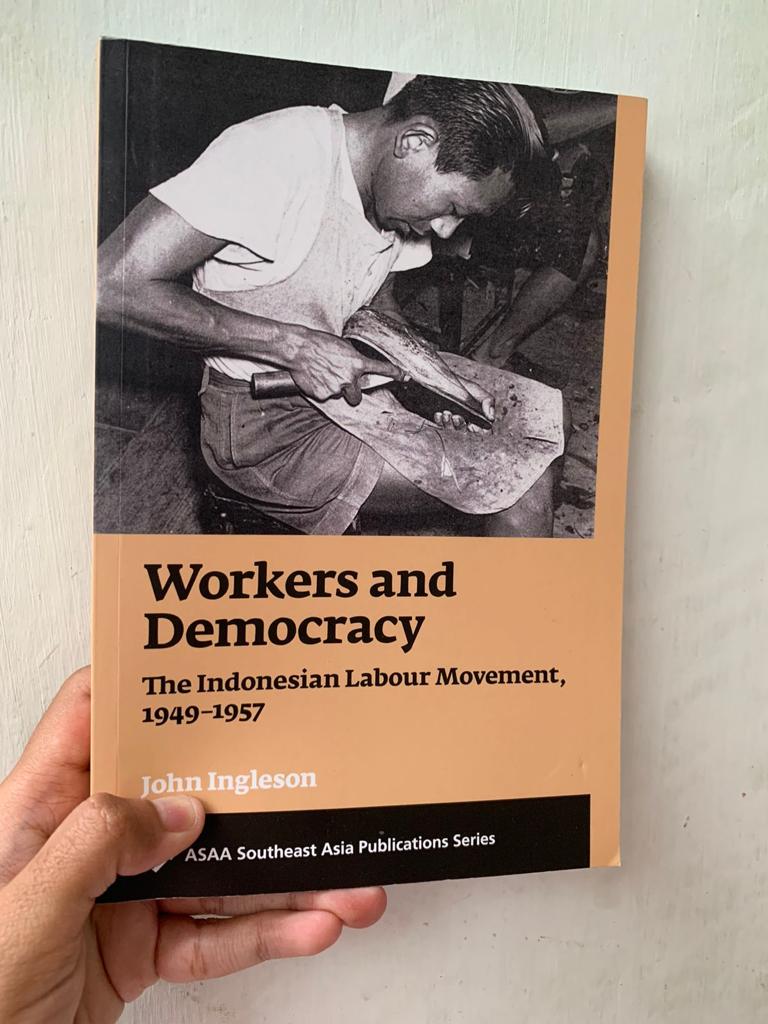
Aktivisme Buruh dalam Cengkraman Partai Politik | Resensi: Virdika Rizky Utama
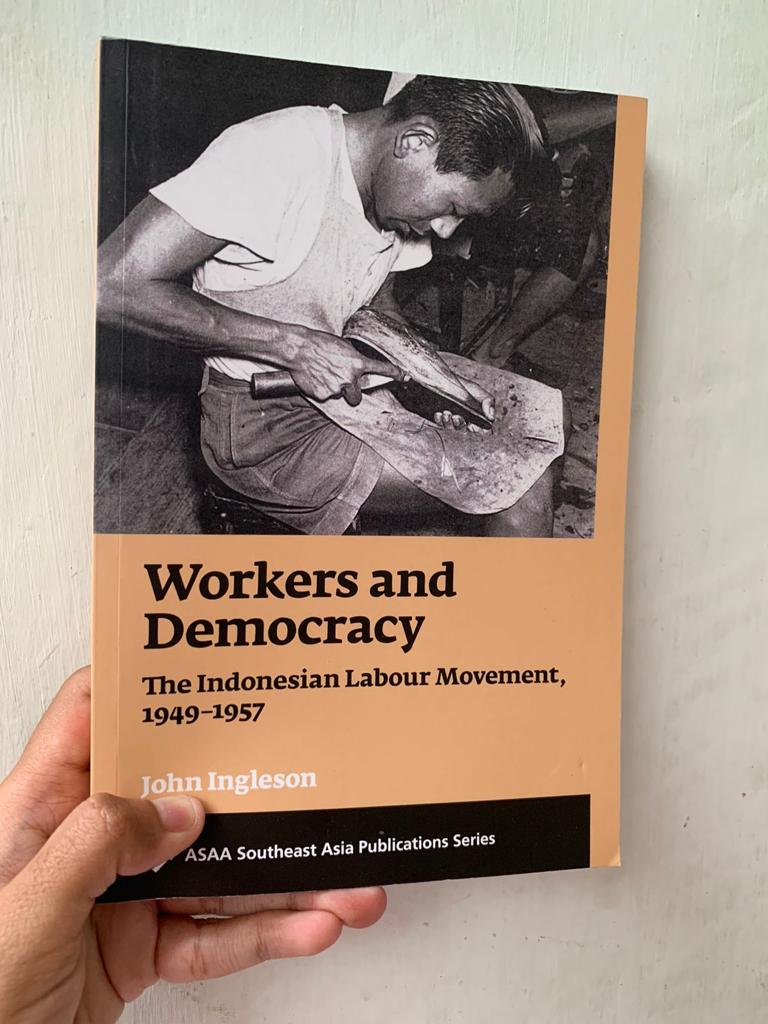
Judul Buku: Workres and Democracy, The Indonesian Labour Movement 1949—1957
Penulis: John Ingleson
Penerbit: NUS Press
Tahun Terbit: Cetakan I, 2022
Tebal: xvii+363 Halaman, ISBN 978-981-325-160-1
Perjuangan buruh dalam perkembangan sejarah Indonesia, tak bisa dipisahkan dari sejarah perpolitikan di Indonesia. Oleh sebab itu, John Ingleson dalam buku terbarunya ini memaparkan dinamika perjuangan buruh dan perpolitikan Indonesia pada periode demokrasi parlementer atau liberal 1950—1957.
Periode demokrasi liberal, kata John Ingleson, merupakan sebuah fase penting dalam perjuangan buruh Indonesia. Sebab, pada fase ini, buruh baru bisa kembali berserikat dan memperjuangkan nasibnya, setelah mengalami fase mati suri pada periode akhir kolonialisme Belanda hingga revolusi fisik 1949.
Diiringi dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, ada rasa euforia dan cita-cita serta harapan untuk menyejahterakan kehidupan buruh setelah sekian lama dijajah. Hal tersebut yang membuat buruh banyak membentuk serikat untuk dapat menekan perusahaan yang sewenang-wenang.
Sebab, meskipun Indonesia merdeka, para perusahaan-perusahaan yang pada umumnya merupakan perusahan milik Belanda. Baik itu perkebunan, industri, maupun pelabuhan. Para pemimpin perusahaan, ujar Ingleson, masih bermental kolonial dan menganggap bahwa orang atau buruh Indonesia itu status sosialnya masih di bawah orang Eropa (hlm.26).
Hal itu tercermin dalam perbedaan upah, fasilitas, dan makanan antara buruh Indonesia dengan buruh asing. Hal ini kemudian diperparah dengan belum adanya standar jam kerja yang jelas, gaji minimum, dan tunjangan-tunjungan untuk para buruh—terutama tunjangan kesehatan dan lebaran. Dengan demikian, buruh merasa kemerdekaan yang sudah diraih oleh Indonesia hampir tidak terasa atau berarti di dunia kerja.
Perasaan demikian itu membuat buruh untuk membuat serikat-serikat pekerja, dengan harapan dengan berserikat dapat menaikkan posisi tawar mereka terhadap perusahaan. Bila tuntutan-tuntutan terhadap perbaikan nasib buruh tak dipenuhi, mereka dapat melakukan pemogokan kerja. Pada 1950—1957 tercatat kurang lebih ada 20.000 konflik buruh dengan perusahaan, dengan mayoritas melakukan pemogokan (Hlm.152).
Harapan para buruh agar mendapatkan perbaikan nasib, ditangkap dengan jeli oleh para partai politik yang ada. Partai politik saat itu merasa sangat perlu untuk memperjuangkan buruh dalam program kerja partai. Kemudian, para partai politik membentuk organisasi sayap (underbouw) untuk para buruh. Tujuan akhirnya, partai bisa mendapatkan suara yang besar untuk pemilu dari para buruh.
Tercatat ada empat serikat pekerja besar yang berafilisasi dengan partai politik: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dengan PKI, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dengan Masyumi, Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dengan PSI, Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) dengan PNI. Semuanya mendesak negara atau pemerintahan untuk hadir dalam setiap perselisihan yang dialami buruh dengan perusahaan. Pada intinya, mereka mendesak agar pemerintah, buruh, dan perusahaan dalam posisi yang setara.
Atas desakan tersebut, pemerintah membentuk Panitya Penjelesaian Pertikaian Perburuhan Pusat (P4P) untuk menjadi arbritase dalam konflik buruh dengan perusahaan. Ini merupakan keuntungan dari serikat buruh, karena berafiliasi dengan partai politik, mereka dapat dengan mudah berkomunikasi dan negosiasi dengan pemerintah.
Tak cukup P4P, pemerintah pun mengeluarkan beragam aturan lebih merinci dan menjawab hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Aturan-aturan pemerintah yang menjadi masalah, karena sering berubah-ubah dan tak konsisten. Hal itu dilatarbelakangi oleh politik Indonesia yang tidak stabil: Perdana Menteri (PM) yang berganti, begitu pula kabinet-kabinetnya.
Lebih dari itu, karena organisasi buruh berkelindan dengan partai politik, kebijakan yang dikeluarkan perdana menteri biasanya dianggap hanya menguntungkan serikat buruh milik partai perdana menteri (hlm 141—144). Sebagai contoh, Perdana Menteri Sukiman yang berasal dari Masyumi hanya akan menguntungkan SBII. Tak hanya itu, kebijakan Sukiman juga dianggap cenderung lebih berpihak kepada perusahaan daripada buruh.
Sedangkan, pada masa Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo yang berasal dari PNI dan berkoalisi dengan PKI, kebijakannya hanya menguntungkan SOBSI. Bahkan setiap keputusan yang diambil Ali terkait buruh, tak pernah mendengarkan serikat-serikat buruh yang ada (hlm.138).
Sifat-sifat partai politik ini juga terjadi di serikat buruh. Sifat partai yang sentralistik, menurut Ingleson, menjadikan serikat buruh di akar rumput atau di daerah-daerah tak bisa leluasa bergerak. Tak hanya itu, keputusan yang diambil para buruh di akar rumput pun menjadi terlambat, karena harus menunggu instruksi atau keputusan pusat. Perjuangan buruh tak lagi murni untuk perbaikan nasibnya, tetapi menaikkan elektabilitas partai dan ajang cari muka para pemimpin buruh agar dipilih menjadi petinggi partai.
Kendati demikian, pembangkangan-pembangkangan oleh aktivis atau anggota serikat buruh di daerah pun tak terelakkan. Selain itu, hal yang menjadi kekurangan serikat buruh adalah keuangan. Buruh biasanya tak memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar iuran serikat, karena penghasilannya untuk sehari-hari pun tak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lainnya, sering kali anggota serikat yang diminta mengumpulkan iuran dari para buruh, justru mengkorupnya (hlm.215-216).
Terakhir, penggunaan hasil iuran anggota serikat acap kali tak digunakan untuk kepentingan buruh. SOBSI, misalnya, menggunakan uang anggotanya untuk membiayai beberapa petinggi SOBSI dan PKI untuk konferensi di luar negeri. Hal itu dianggap pemborosan dan tidak memiliki dampak langsung untuk buruh. Kepentingan buruh menjadi kepentingan nomor dua, setelah kepentingan partai.
Meski begitu, pencapaian para serikat buruh selama 1950—1957 terbilang signifikan. Menteri Ketenagakerjaan pada 1957 mencatat ada 2,295,066 anggota serikat buruh, 56,5 persennya merupakan anggota Sobsi (hlm.74). Sebab, SOBSI-PKI yang memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan buruh. Dengan anggota organisasi yang sangat besar, mencapai 1,2 juta anggota. SOBSI dapat dengan mudah mengagitasi dan menekan perusahaan serta untuk mewujudkan tuntutan-tuntutannya. Tentu saja hal tersebut menguntungkan PKI dalam pemilu.
Namun, ketika 1957 pemerintah melakukan nasionalisasi aset dan beberapa tahun kemudian menerapkan demokrasi terpimpin. Dampak nasionalisasi aset membuat kegamangan bagi buruh. Sebab musuhnya, bukan lagi perusahaan yang diwakili oleh kapitalisme asing, melainkan negara yang para pemimpin peusahannya adalah militer. Selanjutnya, serikat-serikat buruh berjatuhan dengan dibubarkannya partai-partai yang tak sejalan dengan penuguasa. Hal itu berlangsung sampai jatuhnya Soeharto pada 1998.
Buku yang terdiri dari sembilan bab ini, terbagi menjadi dua bagian; konteks sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, dan serikat buruh di berbagai macam sektor ekonomi ini dapat dengan gamblang dinamika perburuhan saat itu. Selain itu, buku ini melengkapi kekosongan narasi sejarah pada era demokrasi parlementer—yang biasanya dipenuhi oleh berbagai macam persaingan elite politik.
Buku John Ingleson ini juga melengkapi dua buku sebelumnya, yaitu In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926 dan Workers, Unions and Politics: Indonesia in the 1920s and 1930s. Dengan data primer yang melimpah, buku ini sangat wajib dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada sejarah perburuhan di Indonesia.

Virdika Rizky Utama – Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





