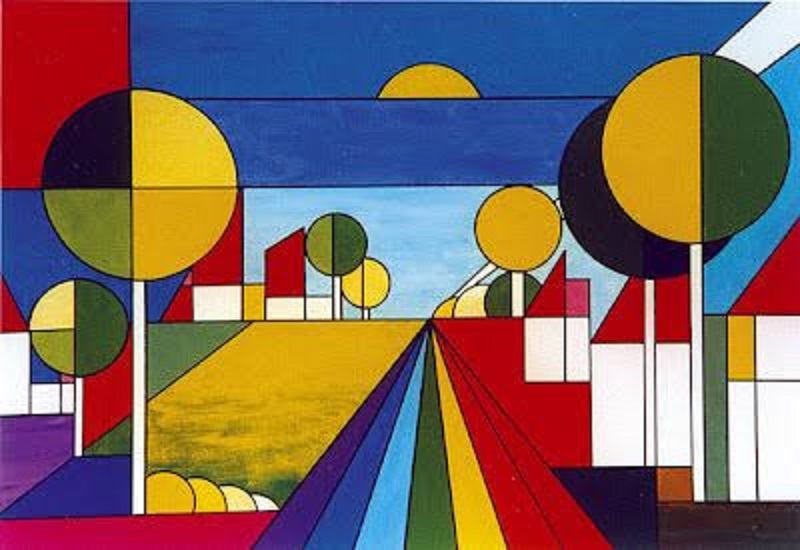Penjual Waktu

Penjual waktu tak pernah datang tepat waktu. Jika aku menunggu pada jam tujuh, ia bisa jadi datang pada jam delapan atau jam sembilan. Atau bahkan kadang-kadang ia tak pernah datang. Jika telat datang ke rumahku, ia akan mengatakan: pembelinya sangat ramai. Hampir semua orang ingin punya waktu dalam sehari yang lebih panjang dari dua puluh empat jam. Jika tidak datang ke rumahku sama sekali, esoknya ia akan mengatakan: kemarin waktunya habis. Waktu memang selalu diburu.
Sudah agak lama aku berlangganan kepada lelaki penjual waktu itu, sekitar setahun yang lalu. Biasanya, aku membeli waktu ketika kesibukanku melebihi batas normal. Misalnya, pagi hari aku harus berangkat ke kantor dan pasti sore harinya baru bisa pulang, lalu malamnya harus lembur memikirkan kerjaan lain, dan itu ditambah mengurusi anak-anak yang sudah lama kehilangan ibunya. Aku membeli waktu agar aku lebih leluasa bekerja. Tentu, jika dalam satu hari saja waktuku lebih dari dua puluh empat jam, bukan tidak mungkin aku bisa mengerjakan kesibukanku yang melebihi batas itu sambil santai, tidak terburu-buru dan menyiksa otakku.
Hari ini aku tidak terlalu sibuk. Kantorku libur karena hari Minggu. Tetapi entah kenapa aku butuh sekali perpanjangan waktuku ini. Aku sedang bahagia bersama dua anakku di depan rumah. Oh, sebenarnya bahagiaku bukan terletak di sini. Tetapi, kami akan liburan. Aku tidak mau liburanku terganggu oleh bayang-bayang hari Senin. Ya, aku butuh perpanjangan waktu. Ah, maksudku, perpanjangan waktu liburanku.
Tepat ketika aku mengharapkan si penjual waktu itu datang, ternyata ia benar-benar datang dan kali ini malah tepat waktu.
“Lho, tumben tepat waktu?”
“Iya, lagi sepi pembeli.”
“Lah, bukannya hari libur biasanya tetap ada yang beli?”
“Hari ini orang-orang lebih suka memperpanjang waktu bekerja ketimbang waktu berlibur.”
“Maksudnya?”
“Ah, tidak perlu kujelaskan lagi. Nanti waktumu berkurang.”
“Hmmm. Bukannya nanti bisa beli waktu di kamu?”
“Iya, sih. Tapi itu mubazir namanya.”
Aku mengangguk-anggukkan kepala. Baru kali ini aku bicara agak lama dengan penjual waktu ini. Biasanya aku membeli waktu dengan terburu-buru, bahkan tidak sempat menyapa, tidak sempat bertanya-tanya lebih lanjut tentang dirinya. Biasanya aku hanya beli waktu saja dan memakai waktu itu di kehidupanku.
Aku baru satu tahun tinggal di sini dan baru setengah tahun yang lalu tahu ada penjual waktu. Itu karena aku diberi tahu oleh teman sekantor. Ia sudah lama langganan pada penjual waktu itu.
Lelaki itu menjual waktu dengan cara mengecer. Artinya, ia menjual waktu per-jam. Misalnya aku ingin memperpanjang hariku menjadi dua puluh tujuh jam dalam sehari semalam, maka aku harus beli tiga waktu.
“Mas, aku beli dua puluh empat waktu.”
“Memangnya Bapak mau ke mana?”
“Aku mau liburan. Aku ingin liburanku tidak terlalu pendek.”
“Oh, oke.”
Kemudian lelaki itu mengeluarkan dua puluh empat waktu dan memberinya padaku setelah aku menyerahkan kepadanya segepok uang. Waktu yang asli, maksudku, waktu yang permanen, ah, maksudku, waktu yang dua puluh empat jam dalam sehari itu memang tidak bisa dibeli dengan uang. Akan tetapi, lelaki itu menjual waktu dengan mahar beberapa uang.
Ini artinya, aku punya waktu dua kali lipat di hari Minggu. Aku akan leluasa ke mana-mana.
**
Kota ini memang padat penduduknya. Kalau bukan karena pekerjaanku di sini, aku sudah kembali ke kampung. Kembali ke rumah orangtuaku. Di sana tentu suasananya lebih nyaman. Maksudku, tidak banyak polusi udara, tidak banyak orang berkendara, tidak banyak rumah-rumah. Tetapi, aku berpikir ulang, tidak mungkin aku yang sudah dewasa dan punya anak dan punya istri (maaf, pernah punya istri) ini mau tinggal bersama orangtua. Sebenarnya tidak apa-apa kalau aku tinggal bersama orangtua dan aku bekerja. Masalahnya, di kampung sana aku tidak bisa mencari pekerjaan. Aku tidak mungkin jadi petani. Tubuhku ringkih dan tidak tahan kena sinar matahari. Aku tipe orang-orang kantoran, dan memang kerjaku saat ini di kantor.
Aku mengendarai mobil bersama dua anak dan mobil ini sudah dihentikan kemacetan sejak setengah jam yang lalu. Meskipun hari Minggu, kota ini tetap mencintai kemacetan.
Di tengah perjalanan, tepat di lampu merah, kaca mobilku diketuk oleh pengemis. Aku tidak menggubris. Aku tidak mau waktuku habis hanya karena membuka jendela. Tetapi, ketika tidak kugubris, pengemis itu masih tetap mengetuk kaca mobil. Ah, ini orang tidak tahu diri banget, sih.
Akhirnya, aku buka kaca mobilku dan tepat ketika kaca mobil terbuka, ia buru-buru berkata, saya tidak minta uang, Pak. Saya mau meminta sedikit waktu Bapak.
Aku terhenyak. Aku segera bertanya, kenapa Kakek minta waktu?
Waktu saya terlalu sedikit untuk istirahat, Pak. Waktu saya habis untuk mengemis.
Belum sempat aku membalas, mobil dibelakangku memencet klakson berkali-kali. Aku baru sadar, lampu merah sudah berganti hijau. Aku meluncur meninggalkan pengemis itu.
**
Di tempat liburan, aku tidak fokus. Harusnya aku bahagia menikmati hari libur yang dua kali lipat ini bersama kedua anakku. Akan tetapi, omongan pengemis itu benar-benar menghantui. Aku baru sadar ketika waktu liburku habis dan aku sudah tepar di rumah pada malam Senin: Oh, iya, ternyata tidak semua orang bisa membeli waktu. Tidak semua orang punya uang banyak. Tidak semua orang punya waktu istirahat dari pekerjaan, bisa dalam bentuk liburan ke mana-mana maupun berdiam diri di rumah sambil menonton televisi atau memainkan telepon pintar.
Sekali lagi kuberi tahu, omongan pengemis itu terngiang-ngiang di telingaku.
Bahkan, omongan itu mampir dalam mimpiku. Banyak orang-orang dengan pakaian yang lusuh dan tubuhnya kurang terawat meminta waktu yang kumiliki. Mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Waktu mereka habiskan untuk bekerja sehari-hari dan itu hanya cukup untuk makan, kadang malah tidak cukup sama sekali.
Aku bangun tidur pada pagi yang hening di jam enam. Aku butuh penjelasan lebih lanjut mengenai waktu dari si penjual waktu. Segera. Aku memilih tidak masuk kantor hanya untuk menunggunya.
Penjual waktu tak pernah datang tepat waktu, itu benar. Ia datang ketika matahari sudah tepat di ubun-ubun.
Maaf, Pak, pembelinya sangat ramai, katanya.
Maaf, Mas, sebelumnya, aku mau tanya. Sebenarnya siapa yang biasa beli waktu di Mas?
Hmm, ya, orang-orang kantoran seperti Bapak.
Aku berpikir sejenak. Apa tidak ada yang lain sepertiku?
Ia menggelengkan kepala dan kemudian mengatakan sesuatu: ada, Pak. Tapi tentu mereka membelinya tidak di saya. Mereka membeli waktu di pusat penjualan waktu. Mereka memborong waktu sebanyak-banyaknya untuk memperpanjang waktu normal mereka. Supaya mereka punya banyak waktu untuk berleha-leha. Saya kan cuma penjual waktu eceran. Jadinya target penjualan saya ya orang-orang kantoran seperti Bapak. Tidak mungkin ke mereka.
Aku penasaran, mereka siapa?
Penjual itu pun mengatakan sesuatu yang mengubah pola pikirku di kemudian hari: mereka ya seperti Bos Bapak, atau para pejabat tinggi, anggota-anggota DPR, dan lain sejenisnya.[]
*pernah dimuat di koran Minggu Pagi 1 November 2019


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co