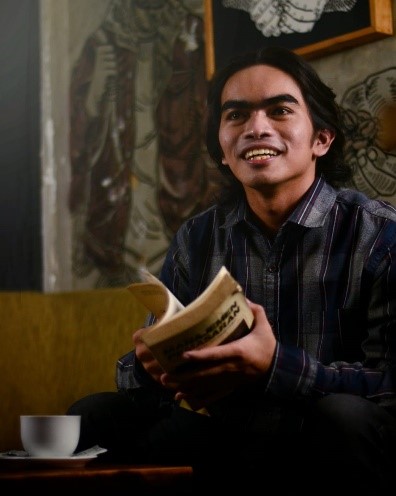Sebuah Surat yang Dilipat menjadi Perahu Kertas
Oleh: Polanco S Achri
Pak Sapardi yang mencintai dan dicintai puisi,
Saya ingin menulis, dan mengirimkan, sebuah surat kepada Anda dengan sederhana: dengan tulisan yang mudah dipahami dan yang enak dinikmati. Akan tetapi, menuliskan surat yang sederhana, agaknya, bukanlah sesuatu yang benar-benar sederhana bagi saya; dan hal itu membuat saya teringat bahwa saya ini lebih sering memperumit dibanding menyederhanakan. Karenanya, saya pun memilih dan mengupayakan untuk menulis surat ini dengan apa adanya: dengan semampu dan sebisa saya, dengan sejujur-jujurnya.
Saya sadar, saya bukanlah seorang, atau mungkin sesuatu, yang tabah, bijak, dan arif seperti hujan pada bulan keenam yang telah indah Anda sajakkan. Saya ini hanyalah seorang pemuda yang suka mengumpulkan, memungut, maupun memulung apa-apa yang membuat saya tertarik—dan juga terusik. Akan tetapi, saya ini bukanlah seorang yang rajin ataupun tekun dalam mengumpulkan sesuatu; sehingga dengan lekas-lekas saja saya bisa berkata, dengan meminjam ungkapan indah Anda yang mahsyur itu, bahwa ada yang senantiasa luput. Meskipun begitu, saya tidaklah yakin benar-benar bisa berkata: Nanti dulu, biarkan aku…
Memalui surat ini, saya begitu ingin menyapa Anda, begitu ingin bertanya: Ada berita apa hari ini, Pak Sapardi? Saya tak menuntut balasan, sebab sajak-sajak Anda mengajarkan begitu kepada saya. Saya pun begitu yakin, surat ini akan sampai kepada Anda, akan Anda baca—di bawah sebuah pohon yang teduh, agaknya. Karenanya, saya pun ingin lekas-lekas menyampaikan-berkata: Terima kasih, Pak, terima kasih sudah membaca tulisan ini. Lantas, bersamaan dengan ucapan itu, atau mungkin lebih tepat mengatakan sesudahnya, saya ingin meminta maaf: Sebab apa-apa yang saya pungut tak dapat hadir di hadapan Anda seperti, dan sebagai, karangan bunga. Akan tetapi, meski begitu, saya dapat berkata lekas-lekas pula, sampai kini, sampai pada suatu hari, saya ini masih berupaya mengingat—sehingga, agaknya, saya belum ingin mengajukan tanya: untuk apa.
*
Pak Sapardi yang mencintai dan dicintai puisi,
Dalam surat ini, saya hendak bercerita saja, saya tak ingin menyampaikan apa-apa selain apa yang Anda sebut-sebut sebagai dongeng. Karenanya, ketika Anda membaca tulisan ini, saya berharap Anda membayangkan: seperti halnya seorang kakek yang mendengar kisah (karangan-khayali) dari cucunya yang berhasil menerobos hutan—yang mana sebenarnya adalah taman atau kebun milik tetangga. Bersamaan dengan hal itu, saya ingin sekali berkata kepada Anda bahwa wajah Anda serupa dengan wajah kakek saya, wajah ayah daripada ayah saya; bahkan, ketika ayah saya melihat foto Anda yang sepuh itu, tiba-tiba ayah saya berkaca-kaca: sebab teringat pada ayah yang sangat dicintainya. Ayah saya dan kakek saya adalah seorang tukang cukur, sedangkan saya adalah seorang kurir yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyair, seorang yang menempuh pendidikan di jurusan sastra dan memiliki suatu angen-angen bisa masuk sebuah kelas yang diajar oleh And—dan saya membayangkan: duduk di sebuah bangku lantas dikisahkan oleh kakek sendiri.
Perjumpaan dengan sajak-sajak Anda, yang dapat saya ingat dengan cukup tepat, adalah ketika bangku sekolah menegah (baik menengah pertama maupun menengah atas). Saya tak tahu mesti senang atau bersedih saat berkata bahwa buku ajar bahasa Indonesia, tepatnya pada bagian puisi, memiliki contoh puisi yang itu-itu saja; tetapi, seperti yang sering diajarkan oleh ibu saya, saya tetap bersyukur. Di buku itulah, agaknya, saya menjumpai sajak Anda. Saat itu, saya hanyalah seorang remaja yang bercita-cita menjadi seorang pahlawan, atau tokoh utama, dari sebuah lakon-cerita. Seperti halnya Naruto. Saat itu, saya jatuh cinta pada seoran gadis yang adalah adik kelas saya. Seorang gadis yang memiliki pipi kemerahan dan memiliki nama yang indah, sebuah nama yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti: kekal-abadi.
Membaca sajak-sajak Anda, tepatnya, yang berkenaan dengan waktu (fana-abadi) membuat saya berpikir, mungkin merasa, dan mungkin pula merenung, tentang kisah cinta saya. Betapa kata-kata “abadi” yang ada di dalam sajak-sajak Anda dengan serta merta saya baca dan maknai sebagai sosok—tepatnya: sosok gadis yang saya cintai tapi terlalu sulit guna saya miliki itu. Membaca sajak-sajak itu membuat saya menyadari bahwa saya takut kepada abadi maupun keabadian, menyadari pula bahwa saya tak seberani untuk memilih menjadi fana; bersamaan dengan itu, saya pun menyadari bahwa saya juga mencintai abadi dan kebadaian—bahkan seperti para Alkemis: saya ingin menjadi abadi—tetapi saya juga menyadari bahwa saya perlahan-lahan, yang mana saya rasa begitu tiba-tiba, mencintai apa-apa yang fana. Karena itulah, ketika membaca dan membaca berulang kali sajak-sajak Anda berkait waktu atau kewaktuan itu, saya menjadi bertanya-tanya: Apakah seorang manusia itu membutuhkan kebadian?—dan bersamaan dengan itu, saya bertanya pula: Apakah saya membutuhkan gadis yang dinamai abadi itu?
Ah! saya tak tahu bagaimana wajah Anda ketika membaca soalan di atas; saya tak memiliki pengalaman bercerita kepada kakek saya—sebab kedua kakek saya, dari pihak ibu atau ayah, telah menginggal ketika saya kanak. Akan tetapi, saya mencoba membayangkan. Saya membayangkan Anda manthuk-manthuk, mengangguk-anggukkan kepala, dengan pelan ketika membaca soalan di atas; dan seperti yang saya katakan sebelumnya, sungguh, saya menyampaikan itu dengan sejujur-jujurnya. Betapa saya terdiam dan terpukau pada frasa, mungkin pula kalimat, yang mana berbunyi: Kita abadi. Bahkan, saya semakin terdiam ketika membaca: Sesaat adalah abadi. Bagaimanakah rasanya menjadi abadi,duh, Pak Sapardi? Di samping soalan fana-abadi, sungguh saya tetaplah terpukau pada apa-apa yang Anda kerjakan dengan sepenuh hati. Bahkan, saya sering iri sambil bercampur suatu kepongagan anak muda: betapa saya rasa-rasanya bisa membuat hal semacam itu; tetapi lekas-lekas saja saya menjadi sadar, bahwa dari rerasan itu saja sudah menunjukan saya masih belum mampu—saya belum tabah, bijak, dan arif seperti hujan di bulan keenam yang Anda sajakkan.
Adapun perjumpaan pertama saya dengan Anda (saya cukup bimbang dan bingung untuk memakai kata “kita”) secara langsung adalah ketika acara bincang-bincang buku Anda di sebuah toko buku besar, yang mana acara itu dipandu oleh seorang esais, penyair, dan redaktur kenamaan—yang senantiasa dan masih setia menolak kiriman tulisan saya. Saat itu, saya meminta tanda tangan Anda dan meminta berfoto seperti yang lainnya; tetapi soalan yang berkesan adalah bahwa saya merasakan kedekatan, saya merasa bahwa Anda adalah sosok kakek saya. Saat itu, ketika meminta tanda tangan, entah kenapa, bahasa yang keluar dari bibir saya bukanlah bahasa Indonesia yang lumrah saya pakai; tetapi yang keluar adalah bahasa Jawa Krama, yang lekas-lekas Anda jawab dengan: “Sebelah endi, Le?”. Mendengar itu, saya terdiam sejenak, terhenyak mungkin. Lantas, saya menyalimi tangan Anda dan berkata—dengan bahasa Jawa Krama—semoga Anda baik-baik dan sehat-sehat saja. Saat itu, saya cukup ingat Anda menyampaikan sesuatu, tetapi malangnya saya lupa bagaimana perisnya kata-kata Anda, dan karenanya saya hanya bisa mereka-reka bahwa yang Anda katakan adalah agar saya tetap menjadi diri saya, tetap menulis dan membaca. Lantas, sebagai seorang cucu ataupun sebagai generasi penerus, setidaknya saya merasa begitu, saya pun berupaya menjalankan wejangan itu. Hal-hal itulah yang membuat saya makin yakin:
Sesaat adalah abadi!
*
Pak Sapardi yang mencintai dan dicintai puisi,
Saya rasa, saya mesti menyudahi tulisan ini, menyudahi surat yang sebermula ingin saya tulis dengan sederhana, tetapi saya putuskan menulisnya dengan apa adanya—saya rasa Anda pasti ingin segera ngobrol dengan teman-teman Anda di sana. Akan tetapi, mungkin, nanti, pada suatu hari yang lain, saya akan menulis surat lagi; dan untuk itu saya harap Anda tidaklah bosan membacanya. Adapun sebagai penutup, biarkan aku sejenak berkata:
Pada suatu hari nanti,
yang mungkin telah terjadi kini,
sesaat adalah abadi—
dan mungkin memanglah abadi.
Yogyakarta, musim kemarau 2020.
Tertanda, seorang kurir beralis tebal.
(Adapun tulisan ini berutang besar pada puisi Sapardi Djaka Damono; di antaranya adalah “Aku Ingin”, “Yang Fana adalah Waktu”, “Hatiku Selembar Daun”, dan beberapa yang lain).
Polanco S Achri lahir dan tinggal di Kota Yogyakarta. Lulusan jurusan sastra, menulis prosa dan drama. Dapat dihubungi via FB: Polanco Surya Achri atau IG: polanco_achri.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co Server
Server