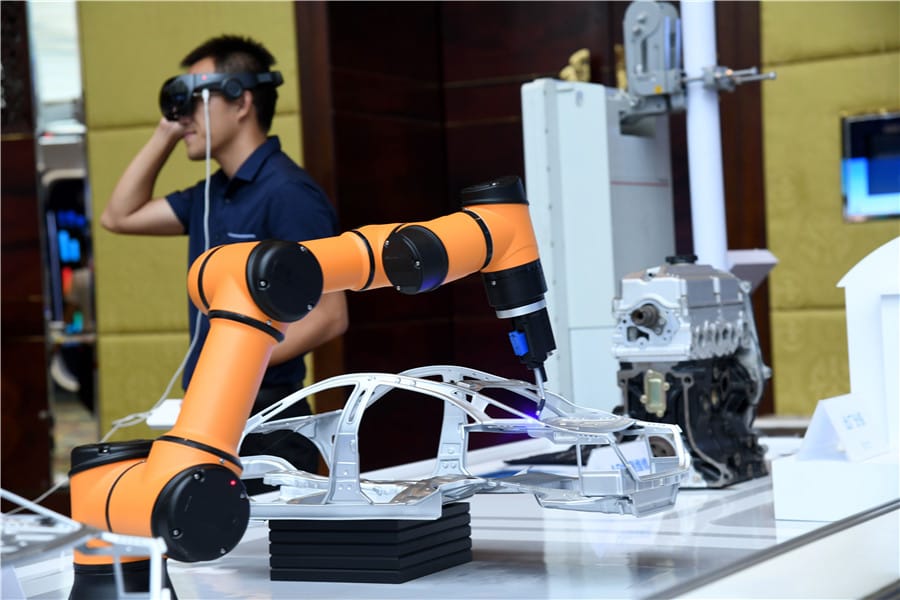Perdana Menteri Mali Mengutuk Praktik Neokolonial Prancis di Negaranya
Berita Baru, Internasional – Pada sesi ke-77 Majelis Umum PBB pada hari Sabtu, Perdana Menteri Mali, Letnan Kolonel Abdoulaye Maiga, menyampaikan kritiknya kepada Prancis dan Sekjen PBB dengan mengatakan bahwa negaranya telah ditikam dari belakang oleh pihak berwenang Prancis, yang secara sepihak memutuskan untuk menarik Pasukan Barkhane dari Mali.
Seperti dilansir dari Sputnik News, Maiga secara terang-terangan mengutuk praktik Prancis yang neokolonial, merendahkan, paternalistik, dan revankis terhadap Mali.
“Setelah lebih dari 10 tahun ketidakamanan yang menyebabkan ribuan kematian, bukankah merupakan penistaan untuk menempatkan penduduk Mali di negara yang terkurung daratan di bawah embargo selama tujuh bulan, menutup perbatasan dan menyita rekening keuangan Mali?” kata Maiga.
Maiga juga menuduh junta Prancis melakukan obskurantisme dengan mengeksploitasi perselisihan etnis dan melupakan tanggung jawabnya dalam genosida terhadap Tutsi di Rwanda. Tidak hanya itu, Maiga mengatakan: “Prancis melanggar wilayah udara Mali dengan menerbangkan vektor udara seperti drone, helikopter militer, dan pesawat tempur lebih dari 50 kali dan memberikan informasi, senjata dan amunisi kepada kelompok teroris”.
Maiga juga mengatakan bahwa meski mendapat kecaman dari seluruh Afrika, Prancis ikut campur tangan dalam urusan Libya, di mana ribuan orang Afrika berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, terlibat dalam perdagangan budak yang berada di balik keberhasilan ekonomi banyak negara maju.
Saat berbicara tentang pasukan penjaga perdamaian PBB di negara Afrika, Maiga menyatakan bahwa: “Hampir 10 tahun setelah pembentukannya, tujuan MINUSMA (Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Mali) dikerahkan di Mali belum tercapai.”
Penarikan Pasukan Prancis dari Mali
Pasukan Prancis telah ditempatkan di Mali selama sembilan tahun dengan tujuan memerangi terorisme di Sahel sebagai bagian dari Operasi Barkhane.
Bulan lalu, Prancis menarik pasukan terakhirnya dari negara Afrika, setelah berselisih dengan pemerintah militer Mali. Proses penarikan dimulai pada Desember 2021.
“Hari ini pukul 1:00 siang (13:00 GMT), detasemen terakhir pasukan Barkhane yang hadir di tanah Mali melintasi perbatasan antara Mali dan Niger,” tulis siaran pers dari Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis.
Setelah meninggalkan Mali, Prancis mengirim pasukannya ke negara tetangga Niger, di mana serangkaian demonstrasi anti-Prancis pecah baru-baru ini.
Berakhirnya operasi di Mali berjalan seiring dengan tuduhan Mali bahwa Prancis membantu teroris di negara Afrika itu.
“Pemerintah Mali memiliki beberapa bukti bahwa pelanggaran mencolok wilayah udara Mali ini digunakan oleh Prancis untuk mengumpulkan intelijen untuk kepentingan kelompok teroris yang beroperasi di Sahel dan untuk menjatuhkan senjata dan amunisi ke mereka,” kata Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus.
Tumbuh Ketidakpuasan
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa demonstrasi anti-Prancis dan anti-PBB telah terjadi di Mali, serta di negara-negara lain di Sahel – wilayah semi-kering dan sarang Islamisme, di mana pasukan Prancis berada.
Pada 22 September, protes terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB pecah di ibu kota Mali, Bamako. Gelombang pengunjuk rasa dengan bendera Mali berbaris di jalan-jalan, meneriakkan slogan-slogan anti-PBB. Banyak pengunjuk rasa juga membawa bendera Rusia.
“MINUSMA (Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali) tidak melakukan apa pun di sini. Kami ingin mereka pergi, kami ingin tentara kami, dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta (Presiden sementara Mali sejak 2021),” kata salah satu pengunjuk rasa. , dikutip oleh AfricaNews.
“Mereka bisa kembali ke rumah mereka dan tinggal di sana. Kami tidak membutuhkan bantuan mereka lagi. Assimi Goïta sudah cukup bagi kami. Pemuda Mali sudah cukup bagi kami,” tambah seorang lagi yang ikut dalam demonstrasi.
Pada 14 Mei, warga Mali berdemonstrasi di Bamako dengan tuntutan serupa. Mereka menyerukan Prancis untuk mundur dan membantu Rusia.
Gelombang protes juga melanda negara-negara Afrika lainnya. Pada 18 September, banyak penduduk Niger turun ke jalan-jalan di ibu kota Niamey, menentang pasukan Prancis yang dikerahkan ke Niger setelah meninggalkan Mali.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co