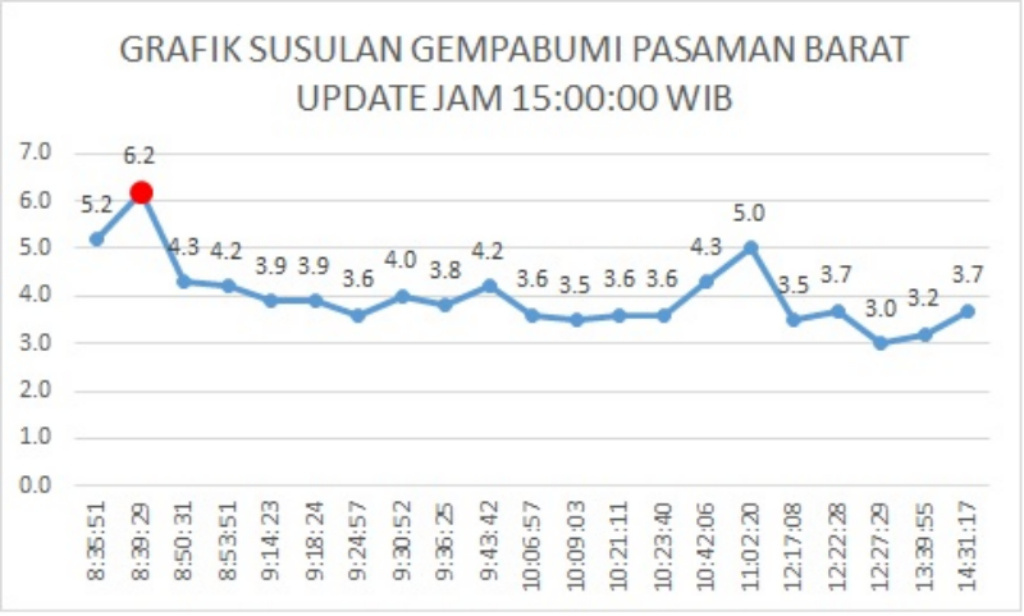Menyoal Kekerasan Seksual di Luwu Timur: Cari Bukti Bukan (Cuma) Tugas Korban
Berita Baru, Jakarta – Kasus kekerasan seksual yang dialami tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan banyak pihak. Kasus yang terjadi sejak tahun 2019 ini kembali menjadi perhatian publik setelah Project Multatuli menerbitkan liputan berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan” pada 6 Oktober lalu.
Kasus ini bermula pada Oktober 2019, ketika Lydia (bukan nama sebenarnya), seorang ibu tunggal, mendapati anaknya mengeluh kesakitan pada area kewanitaan. Diketahui kemudian bahwa ketiga anak Lydia yang semuanya masih berumur di bawah 10 tahun telah dilecehkan oleh ayah kandungnya yang merupakan mantan suami Lydia, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang kini menjabat di kantor pemerintahan daerah.
Untuk melihat apakah sistem hukum terkait kasus ini sudah baik atau belum, Ai Rahmayanti selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Rumah Perempuan dan Anak menyatakan kasus ini dapat ditelaah melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman dengan ukuran 3 indikator, yakni substansi hukum (aturan hukum), struktur hukum (penegak hukum yang bertugas melaksanakan substansi hukum), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat).
“Realitas yang terjadi di kasus ini menunjukan kultur hukum sudah baik, yaitu korban atau pelapor sudah sadar dan berani melapor. Namun lemah di indikator nomor 1 dan 2, yakni substansi hukum dan struktur hukum,” ujar Ai. Kelemahan yang dimaksudkan adalah aturan mengenai konsep pembuktian yang menyulitkan korban dan justru membuat polisi memilih untuk menghentikan kasusnya.

Political will dibutuhkan dalam penanganan kekerasan seksual
Secara khusus, Ai menyoroti political will para Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai belum kuat dalam menyelidiki kasus kekerasan seksual ini. Dalam kasus yang terjadi di Luwu Timur, penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dengan alasan kurangnya bukti yang ada terkait adanya kekerasan seksual.
“Ini menunjukkan lemahnya aturan yang mengarah pada kepentingan korban dalam hal pembuktian, saksi harus 2, visum harus positif dan lain-lain, sedangkan penyidik dalam kasus ini baru menggali bukti dari pelapor saja. Penyidik tidak berusaha menggali dengan aktif alternatif alat bukti lain,” ujar Ai, menyiratkan bahwa kepolisian dalam hal ini belum mampu memfasilitasi korban kekerasan seksual.
Ai juga menyitir tugas penyidikan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Selain itu, Ai juga menggarisbawahi perlunya kerja polisi untuk turut mencari bukti yang dibutuhkan. “Dengan viralnya kasus ini, polisi akan melanjutkan jika ada bukti baru. Padahal, kewajiban membuktikan bukan tanggung jawab korban atau pelapor saja. Jadi, butuh political will penyidik dengan segala kewenangannya untuk membuat terang suatu perkara,” tukas Ai.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co