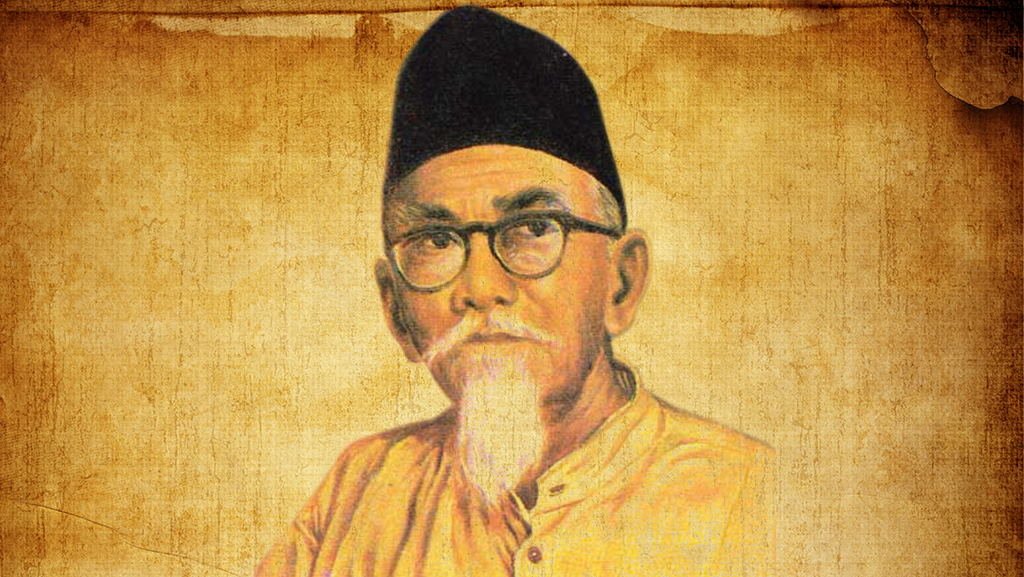Menahan atau Menyerbu | Sofiyatul Ahmadah
Sofiyatul Ahmadah
Tibalah umat islam pada usaha menahan diri dari makan, minum, dan segala perilaku buruk untuk mencapai ridha Allah. Usaha yang bagi sebagian orang biasa saja, ada pula menantang. Praktiknya, menahan diri tidak sebiasa yang kita bayangkan di tengah banjir diskon di pinggir jalan.
Bulan puasa menjadi bulan yang istimewa bagi umat islam. Pada bulan ini semangat keberagamaan umat islam sangat semarak. Masjid-masjid ramai, Langar-langgar pun ramai, sepanjang jalan pun ramai. Umat islam berharap agar bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah bagi dirinya dan keluarganya.
Sayangnya, terjadi problem yang cukup serius khususnya di Indonesia. Bayangkan saja jika menilik makna dari puasa yang berarti menahan. Menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu lainnya, serta menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan orang lain, seperti berkata kotor, sombong, adu domba, dan kegiatan tidak terpuji lainnya. Persoalannya ialah jika ritual puasa merupakan ritual sakral agar umat islam tidak makan berlebihan, agar umat islam bisa mengendalikan diri dari sifat tak terpuji, dan agar umat islam bisa lebih baik secara individu atau kelompok.
Akan tetapi, perilaku konsumtif ini hampir setiap tahun menggerogoti kehidupan kita di kala Ramadan. Dari penjual es campur hingga penjual gorengan yang berjejer panjang. Semuanya ramai dikunjungi. Bisa dikatakan, tidak ada jualan yang tidak laku di bulan Ramadan. Bahkan, tak jarang toko pakaian, permainan, bahan makanan, atau perlengkapan sekunder lainnya pesta diskon, tebar promo dengan fantastis. Alhasil, orang mana yang tidak tertarik.
Jean P. Baudrillard dalam galaksi simulakra menjelaskan bahwa dalam memproduksi budaya media sangat berperan dalam hal itu. Seperti halnya budaya konsumtif, orang mengonsumsi barang bukan semata karena kebutuhan pada barang itu, melainkan karena barang itu mampu membawa promisi dan gengsi bagi orang yang memiliki (mengonsumsinya).
Ada juga orang yang tidak sadar telah terjebakdalam refleksi budaya komoditas. Pada posisi ini, konsumen mengalami kenikmatan konsumsi atas produk-produk yang melimpah ruah. Sebagaimana yang tampak ketika kita keluar rumah dan melihat berjajar kios-kios, mall, atau supermarket yang ramai itu.
Mark juga melihat bahwa ada waktu kerja yang dimaterialkan dalam nilai-guna komoditas. Orang yang bekerja untuk mencari uang justru dia memiliki daya konsumsi yang cukup besar. Meskipun anak muda zaman sekarang belum sepenuhnya bekerja untuk mendapatkan materi, namun mereka berada dalam lingkungan yang konsumtif.
Budaya konsumsi bisa terjadi di mana saja, tidak memandang area perkotaan ataupun pedesaan. Letak perbedaannya lebih pada perputaran dan pola pikir manusia untuk mengonsumsi dalam bentuk simbol sesuai dengan sistempengetahuannya masing-masing. Kondisi ini terkait dengan prinsip hidup dari masing-masing orang memandang kepentingan melalui status sosial ekonomi yang berujung pada pancapaian identitas. Kondisi ini dibentuk dalam sistemyang kadang tidak disadari oleh masyrakat karena pengaruh promosi, citra, dan imajinasi melalui gambar, tanda, maupun simulasi.
Oleh karena itulah, perhatian dari Lee yang terinspirasi dari Marx melihat ciri komoditas berada pada pada masyarakat modern. Masyarakat modern bukan pada letak kehidupan secara
geografis di perkotaan atau di pedesaan, melainkan sistem pengetahuan orang tersebut dan ideologinya. Sistem pengetahuan dan ideologi itulah yang merupakan perwujudan dari praktik sosial yang dapat menjadi penelitian interdisipliner bagi cultural studies.
Kenyataan saat ini banyak orang yang dikelilingi oleh barang, jasa, dan material lain yang sangat mudah. Terlebih di era metavers ini, untuk berbelanja menggunakan teknologi sangatlah mudah, efektif, dan murah. Melaui marketplace semua orang dengan mudah menuruti keinginan dan ambisinya akan kepemilikan barang.
Berdasarkan realitas yang demikian, orang yang memiliki banyak uang cenderung hasrat konsumsinya tinggi. Orang yang bekerja dengan penghasilan tinggi cenderung seenaknya membelanjakan uangnya guna menuruti keinginan dan gengsi. Budaya konsumsi memang tidak kenal musim. Tapi di bulan Ramadan ini konsumerisme meningkat tajam dalam segala aspek; makanan, minuman, pakaian, dan properti.
Bahkan, bulan Ramadan juga menjadi bulan yang sibuk untuk memperbaiki rumah, menghias rumah, dan berganti pakaian. Memang, dalam ajaran islam keindahan atau kebersihan Sebagian dari iman. Dan ketika menggunakan pakaian baru terlebih ketika Idulfitri merupakan sesuatu yang disukai Rasul, atau Sunah Nabi.
Refleksi kita sebagai umat islam khususnya yang ada di Indonesia ialah konsumsi adalah kebutuhan hidup manusia sebagai homo economicus, akan tetapi konsumerisme atau giat konsumsi yang tinggi seperti perilaku rakus, serakah, dan bermewahan berlawanan dengan semangat islam itu sendiri. Jika kembali pada hakikat puasa sebagai ikhtiar menahan diri dari kerakusan dan lainnya, maka meminimalisir budaya konsumsi untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan menjadi penting.
Jikalau orang kaya mah bebas, apalagi tidak mempedulikan orang-orang yang lemah, maka puasa kita hanyalah untuk diri kita sendiri. Puasa sebagai agenda revolusi diri agar diri dan orang lain menjadi lebih baik, maka semangat puasa adalah semangat kebersamaan. Senang bersama dan Lebaran bersama. Jangan lantas baju baru yang dikenakan menjadi bahan pamer kepada mereka yang lemah.
Penulis adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Seni Unnes dan pegiat literasi kebudayaan yang tinggal di Semarang.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co