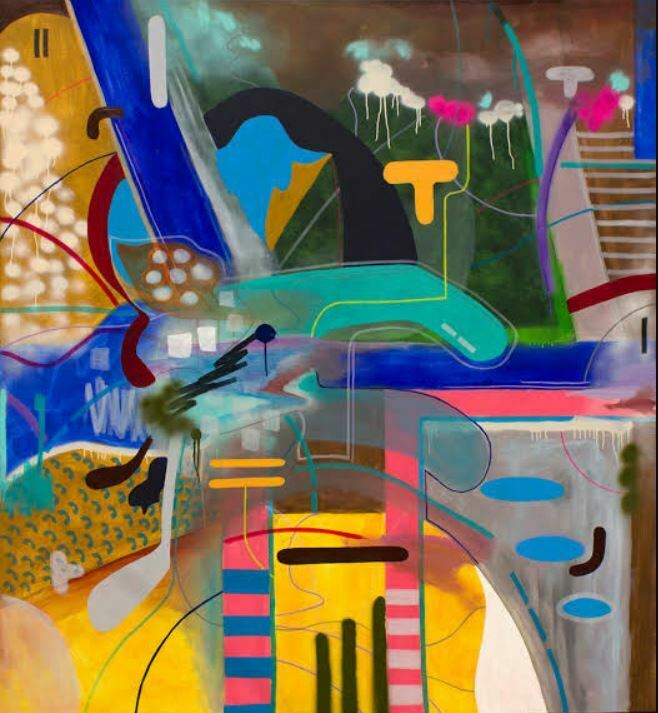Hikayat Lagu-lagu | Cerpen Roydatun Nisa
Hikayat Lagu-lagu
(Cerpen, Roydatun Nisa)
Dadaku berdebar. Seperti menyepuh masa yang lalu-lalu. Seperti mengubek lagi isi otak dan meraba-raba September yang lusuh dan waktu sekitarnya yang bergerak pilu, nan rusuh. Ada orang-orang berkerumun, poster-poster lucu namun menggertak hati, lagu-lagu, nyanyi pilu, wajah sendu, ah…
###
Di jalan yang lumayan lengang ini sepasang tua muda itu bercakap. Seperti percakapan sepasang sepatu yang merenungkan kesetiaan. Begitu perih dan lirih. Perempuan kulit langsat mata sipit mengucapkan suatu hal. Di sebelahnya seorang lelaki yang kutaksir usianya menjelang tiga puluh tahun sedang asyik mengutak-atik laptop pada sebuah desain grafis.
“Kiamat itu benar-benar datang, kita tidak akan pernah dimenangkan, Bung!.” Lalu menenggak air mineral botol yang dibelinya di toko sebelahku berdiri.
“Belum tentu.” Ucapnya ragu. “Selesai.” Susulnya riang, sambil memperlihatkan sebuah gambar pada perempuan yang sesekali membuka masker penutup mulut itu. Ia kontak temannya yang ternyata seorang jurnalis. Sepersekian detik kemudian gambar itu diramaikan di kerumunan, di akun tweeter beberapa mahasiswa, nangkring di beranda facebook orang-orang, di grup WhatsApp keluarga, yang gambarnya selalu saja diteruskan dan diteruskan entah pada siapa saja oleh penghuni grup tersebut, terbang ke pelosok desa, diperlihatkan pada pada sepasang tua renta yang hanya melongo-longo. Begitulah secepat kilat gambar-gambar yang mengandung makna berat dipelupuk mata segera tersiar ke seluruh nusantara. Nyaris menyaingi deru cepat angin.
Dadaku berdebar. Ada suara pilu yang menyayat hati dari lagu-lagu kesedihan itu. Ada sepotong dua potong ingatan yang secara brengsek tiba-tiba nangkring di dalam otak. Dasar masa lalu!.
Di balik pohon ini aku mengintip. Doa-doa yang membubung ke udara. Isak-isak yang menyesak dalam dada. Ada berpasang-pasang mata berkaca-kaca. Mulut-mulut terbungkam. Seperti menunggui orang terkasih yang tak kunjung dijemput juga oleh Izroil. Tak sampai sepuluh meter dari pandanganku, orang-orang merubung, diiringi petang yang melintang sambil meniupkan doa-doa pada bangunan tinggi yang hendak tumbang namun hilir mudik orang-orang berusaha menopang. Doa-doa yang menyerupai raungan sekarat itu terus membubung mengandus ke udara. Dilantunkan oleh orang-orang bersepatu, berambut gondrong, gelandangan, pakai kpiah dan tidak, juga oleh sopir ojek pangkalan di simpang jalan sana, diikuti tukang papar gigi yang beroperasi tiap hari Senin-Kamis, diikuti tukang becak yang sebenarnya kurang paham, hingga loper koran yang menitipkan motornya di sebuah bengkel demi mengikuti arisan gotong royong itu.
Keringat-keringat yang lahir dari hilir mudik kerumunan itu setidak-tidaknya menyayat jantungku dan membisikkan suatu hal bahwa terkadang cinta patut diiringi perjuangan. Keringat-keringat itu, adalah hasil kerja keras supaya gedung menjulang itu tidak serta-merta tumbang. Diiringi alunan musik dan suara-suara, air mata, dan tempo lagu yang mendayu, terdengar begitu pilu di gendang telinga.
Aku masih saja mengintip sepasang tua-muda itu yang merundingkan suatu hal sambil sesekali memencet angka-angka atau nomor-nomor pada gawai pintarnya. Aku hanya menerka. Entahlah dengan tujuan siapa dan di mana. Sementara dari kejauhan ini sesekali kudengar suara sirene ambulan mampir di gendang telinga dalam sekejap. Entah imajinasi, entah halusinasi.
Gambar yang dikirimkan pada seorang jurnalis itu, seakan menambah serbuk gula maupun serbuk garam di atas kemenyan atau bara api dalam sepat. Meriuhkan asap yang menjilat-jilat ke udara. Semakin hilir mudik orang-orang merubung dan menopang. Gambar itu seakan memercikkan sisa air di ujung jemari pada wajan yang berisi minyak dan telah menghangat. Menggeremang menggema di udara. Sambil diliputi air mata, dipeluk tempo lagu yang mendayu dan terdengar pilu.
Di sudut-sudut ruangan orang-orang berpelukan, sambil menahan sesak yang ditahan-tahan. Entahlah, seperti baru saja melepas orang-orang kesayangan, atau menghadiri pemakaman seorang pahlawan. Mereka saling menguatkan dirundung petang yang segera bergegas.
Satu kali lagi sirene itu kudengar meraung namun sumbang menyerupai rintih. Lagu-lagu itu tanpa henti didengungkan seolah menjadi satu-satunya hal yang memompa kekuatan, mengucurkan keringat.
Ada bendera-bendera kuning dilambaikan oleh telapak-telapak tangan, dan samar-samar kulihat dari balik kaki di kerumunan itu bunga-bunga putih jatuh berguguran ke lantai, ke sepetak tanah. Masih diiringi tempo nada yang mendayu dan terdengar pilu. Aku masih belum paham, hanya bisa menerka-nerka.
Dari balik pohon ini aku mengintip sekali pun tak sepenuhnya dapat kutatap. Tapi yang jelas, semerbak bunga putih itu menguar, lumur dalam pengap lubang hidung. Sesekali menyerupai wangi kemenyan. Menyerupai wewangingan orang-orang kantoran, dan menyerupai bau apak baju gelandangan. Sementara orang-orang hanya diam, saling pandang, mengusap air yang menyembul dari kelopak mata secara diam-siam. Mata-mata sayu, wajah-wajah layu.
Di sampingku ini sepasang tua-muda tetap mematung. Membuka kancing di kerah jaketnya sambil sesekali mengibas-ngibaskan tumpukan koran ke lehernya. Petang yang kian bergegas itu aku lihat cahaya-cahaya kecil berpijaran, cahaya-cahaya benderang dimatikan. Sedang bulan dan bintang memberi kesaksian. Dalam pandanganku mereka susah payah menopang sambil mendengungkan lagu-lagu kesedihan. Hingga sedikit bergulir waktu, tempo-tempo nada berubah meruncing, memekak telinga. Kukira mereka berparade seperti suara-suara lebah yang mendengung. Kalimat-kalimat yang kudengarkan adalah lirik yang menyedihkan, adalah irama yang memilukan, dipeluk petang yang kian meradang.
“Kita ke sana!”
“Tunggu.”
“Kenapa?”
“Coba lihat!.” Pungkasnya pada perempuan sipit sambil mengarahkan telunjuknya pada bangunan yang hendak roboh itu.
“Dalam kegelapan bangunan itu bahkan tetap terlihat angker.” Kelakarnya disertai tawa kecil.
“Terlihat gagah, sekalipun nyaris kalah.” Sanggahnya. Sambil sesekali menunjuk pada tempias cahaya-cahaya kecil yang di arahkan pada bangunan itu. Cahaya-cahaya yang membuat bulu kududkku meremang. Cahaya-cahaya yang membuat dadaru renyuh.
###
Petang itu telah pamit, disususl bedug yang bertalu entah dari arah mana. Sayup-sayup lagu Darah Juang yang ku kenal dibangku kuliah, yang pernah mereka dengungkan di lapangan-lapangan, di jalanan menuju perkantoran, dulu, petang ini terdengar mengalun layu dan menyayat hati. Aku jadi bingung, mana yang menangis, mana yang melambungkan lirik-lirik itu. Dan kerinduan pada teman-temanku menyergapku begitu saja. Ingatan pada masa-masa turun jalan seakan menjerat leherku kembali.
Di penghujung petang itu, orang-orang semakin berkerumun, ada gertak-gertak nada gitar yang pilu dan mengubek kesabaran yang berusaha dibungkus rapi-rapi dalam dada. Dadaku, juga tentu dada mereka. Ada sesak yang juga menyusup lewat pori-pori kulitku. Menjemput air mata dan bertemu di ujung dagu.
Baju-baju hitam itu, seakan benar memberitahuku atau semua orang bahwa seseorang telah berpulang, dan diantarkan dengan ritual menuju pemakaman. Hatiku pilu, lagi-lagi terenyuh. Teringat ibuku, yang puluhan tahun hingga kini masih menunggu kepulanganku. Dan aku tak sempat memberitahukan seorang pun bahwa diriku dan beberapa temanku terpaksa disingkirkan. Dan ibuku yang sudah renta itu tak diberi kejelasan bahwa aku tak bisa pulang dan memeluknya hingga kapanpun.
Kerumunan itu, petang yang pamit dengan wajah gerah, dan lagu-lagu itu hanya bisa meremukkan kembali dadaku, melumurkan kembali air mataku. Aku seperti melihat ibu pertiwi tertatih-tatih dari kejauhan. Sementara diriku yang dilahirkannya hanya menjadi penonton, tak dapat menyokong suatu bantuan apapun. [*]

Nisa Ayumida, merupakan nama pena dari Roydatun Nisa’. Santri asal Sumenep yang sedang bergiat di Lembaga Kepenulisan PP. Annuqayah Lubangsa Putri, serta tercatat sebagai mahasiswi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Guluk-guluk Sumenep Madura. Beberapa karyanya dimuat di beberapa media daring. Alamat lian; taneyan lanjhang.blogspot.com


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co