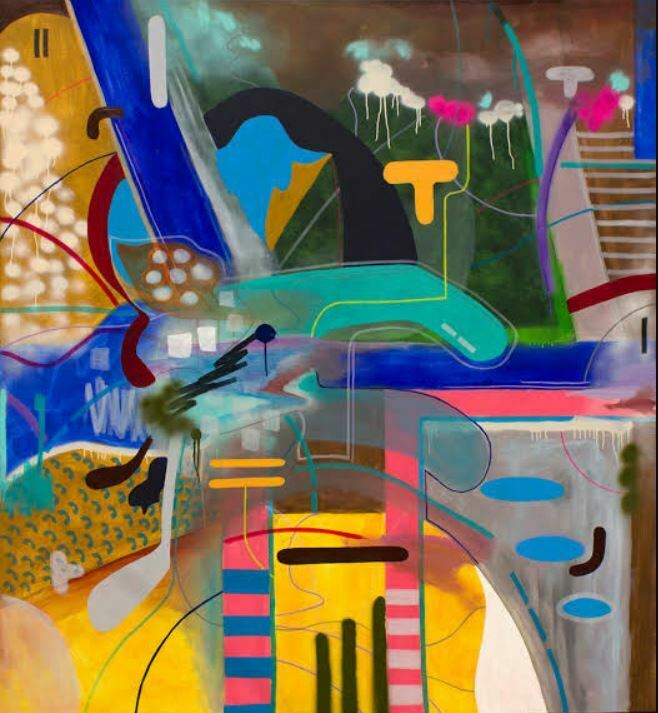
Ina Lefa*
Oleh: Beri Hanna
Seorang pemuda dengan kameranya, sedang memotret tulang-belulang juga potongan daging kotaklema2 yang terjuntai-juntai di sekitar rumah yang tegak menghadap Laut Sawu. Menurut apa yang didengarnya dari seorang lamafa3, dari potongan daging itu—rasa syukur mengalir dapat kasih makan babi ternak, kasih makan anak bini, kasih makan janda dan fakir miskin, kasih sambung rasa syukur pada leluhur yang mewarisi laut, tempuling4, peledang5, dan tradisi tikam kotaklema. Karena satu ekor saja, sudah kasih kehidupan sambung-menyambung dari laut sampai ke gunung semua orang bahagia akannya.
Di samping itu, ada hari-hari tidak melaut—bukan sebab tak ada kotaklema di laut, tapi pantangan bila badai dan hari minggu, atau juga hari-hari lain yang telah ditentukan turun-temurun oleh leluhur.
“Mengapa ada hari-hari tidak melaut? Oh, maksudnya mengapa demikian?” tanya pemuda pada lamafa di dekatnya.
“Karena begitulah adanya yang diajarkan pada kami. Bukan karena kami takut lantas badai bisa menentukan nasib. Boleh saja, tapi tidak dengan takdir. Karena takdir telah menggariskan kami sebagai orang-orang laut yang bergantung hidup dan mati hanya pada laut pula. Bagaimana pun laut tetap biru dan asin, ikan-ikan tetap berenang dan bernapas dengan insang. Namun persoalan badai dan hari minggu dan hari-hari tidak melaut bukan sesuatu yang baru. Sejak leluhur membasahkan tubuh di laut, hal itu sudah menjadi aturan adat kami,” jelas lamafa.
Pemuda itu pun mencatatnya, ini lah tradisi dan ajaran leluhur yang masih dipercaya. Semua penuh pertimbangan. Bukan sekadar melepas peledang ke tengah laut dan menikam kotaklema begitu saja. Salah-salah keras kepala, bisa dikutuk mendapat sial. Yang buruk dari kutukan itu ialah mati. Karena melanggar bisa berakibat mati, dan mati berarti sebab melanggar. Tidak melanggar tapi mati adalah jalan lain menuju pelukan Tuhan.
“Bolehkah saya mendengar kisah masa lalu anda?” tanya pemuda. Lamafa mengatur duduknya dan mulailah ia bercerita.
Sebuah kapal besar menepi di bibir pantai. Sepuluh awaknya yang berbadan pendek-pendek turun lalu takjub melihat-lihat. Kampung ini tanah leluhur yang diciptakan untuk membantai ikan-ikan raja laut. Tapi kemakmuran barang tak pernah berpihak pada kehidupan.
Orang-orang pendek itu semacam dewa yang datang dari roh leluhur—menawarkan sebuah kebaharuan—rumah dan sandang pangan yang melimpah, peledang berkekuatan mesin yang mampu melesat cepat, gadis-gadis amboi, serta apel, anggur, melon dan buah lain yang bagai mitos selama ini.
“Siapa mereka?” tanya pemuda.
“Saya tidak tahu. Yang jelas, dari percakapan manis waktu itu, terjalinlah kesepakatan untuk bertemu rutin melakukan yang disebut mereka transaksi di zaman sekarang.”
Mereka akan datang dan mewujudkan semua hal gaib di kepala kami satu per satu. Yang kami bayangkan saat itu kehidupan baru di depan mata. Sebentar lagi bini bisa bergaya dengan gincu merah terang, mempesona sampai isi lautan. Gadis-gadis yang pandai dansa akan berdatangan meliak-liuk dalam bangunan lampu kelap-kelip penuh irama disko. Musik-musik tidak lagi datang dari rumah ibadah. Tapi bisa dari duduk berdua dan bertiga sambil menenggak arak dari botol kaca, bukan plastik bekas.
“Cengkeramlah dayung. Paculah peledang. Belah laut biru dengan kecepatan penuh. Tikam kotaklema itu!” ucap lamafa menirukan suara orang-orang pendek waktu itu. “Cengkeramlah dayung! Cengkeremlah dayung! Jangan peduli badai dan hari minggu! Sekali tikam tetap tikam!” lengkapnya.
Selepas mereka pergi, badai datang. Di atas laut langit berwarna hitam. Kilat petir bercambuk-cambuk seraya hujan melengkapi, membuat kami bimbang saat melihat babi ternak merintih-rintih lapar, penanak nasi telah lelah merebus karang, umur gigi anak bini tidak akan lama karena sudah sering disombol jagung kering yang keras seperti kerikil. Juga para janda, fakir miskin, anak yatim di balik gunung punya perut yang menggantung hidup pada kami.
“Tunggu, transaksi apa yang disepakati?” potong pemuda.
“Menukar kotaklema tangkapan kami dengan uang, beton, perempuan dan segala sesuatu yang tidak kami punya di sini!”
“Lanjutkanlah ceritanya.”
Bagi kami, menceburkan diri ke laut untuk menjemput kiriman tuhan (menikam kotaklema) adalah jalan bertahan hidup. Tentu saja tak lepas dari adat dan aturan kepercayaan yang telah tetap dari leluhur, seperti menahan diri tidak melaut di hari minggu dan badai seperti yang tadi dikatakan, juga menghapus dosa, tidak bercinta, dan tidak minum arak sebelum berangkat melaut.
Tapi waktu itu, salah satu dari kami berteriak memecah kebimbangan seakan suaranya memberikan kami kenyataan takdir—hidup mati para lamafa takkan lepas dari laut.
Kami sempat berdebat di darat untuk melanggar yang berlaku demi tawaran menakjubkan orang pendek. Beberapa dari kami berpikir, biarlah yang mati tetap mati, dan tidak mengusik hidup. Sebab sejak leluhur melaut, kami tidak pernah membelah apel, mangga, alpukat, dan melihat gadis kulit putih menari liar karena pengaruh arak, kami juga tidak pernah dilindung dinding beton saat malam dan cuaca panas, juga tidur berselimut lembut dari bulu-bulu domba.
“Mungkin ini waktunya. Mengubah peradaban seperti kebanyakan orang hidup bergerak maju. Yang buta diberi lihat, yang tuli diberi dengar, yang bodoh diberi pintar,” ucap lamafa meniru dialog yang diingatnya pada waktu itu.
Tapi beberapa dari kami tidak setuju, karena masih kuat berkeyakinan dan bertahan pada ajaran leluhur. Debat jadi panas. Antara harapan baru, dan bertahan diam dengan masa lalu.
“Satu ekor kotaklema untuk semua kehidupan.”
“Hidup sudah berubah. Anak perlu sekolah! Bini perlu gincu merah! Dan kita butuh gadis berkulit putih itu! Jangan tunggu gigi patah mengunyah batu!”
“O, tidak. Gigi boleh patah mengunyah batu asal kita tetap satu!”
“Apa guna bersatu, kalau mati pun sendiri!”
“Terkutuklah pikiran itu!”
Tiada hari keselamatan kotaklema selain hari minggu dan badai besar. Tapi sejak bujuk rayu orang pendek menjelma penyakit, mau minggu mau badai semua sama saja. Sebagai orang laut, sekali tikam tetap tikam.Satu kotaklema untuk seluruh kehidupan baru, rumah beton, gadis kulit putih, musik, dan arak dari botol kaca bukan plastik adalah anugrah lain bagai menjemput kiriman Tuhan.
Dengan sepuluh tenaga lamafa dewasa mendayung, peledang sampai di tengah laut. Kami mengejar gerombolan kotaklema yang muncul dan tenggelam di tengah badai air laut. Juru Tikam tampak gelisah waktu itu, tapi masih kokoh berdiri menantang. Meski goyah badannya karena peledang buncah oleh angin kencang, tak sepotong ciut nyalinya untuk tikam kotaklema punya badan.
Tempuling bertangkai bambu panjang ditarik Juru Tikam dari perebahan, seperti menarik tangan seorang istri tercinta, doa-doa bertebaran mengelilingi peledang untuk keselamatan dari badai serta keresahan kotaklema yang mulai merasa terusik. Semakin sulit untuk bertahan tenang dari keterombang-ambingan serta jarak pandang yang tertutup kabut tebal semakin pula tertantang untuk dapat menaklukannya saat bayang-bayang kehidupan terlintas di kepala. Saat kotaklema muncul dengan badan lengkungnya, kami saling berteriak mendesak Juru Tikam untuk segera melumpuhkan kotaklema itu. Juru Tikam melompat, merobek sasaran dengan tempuling.
Hirkae! Hirkae!
Air laut memerah. Juru tikam naik ke peledang, mengambil tempuling dan sigap menikam lagi. Tepat sasaran. Dua tempuling bersarang di badan besar kotaklema. Tali tempuling diulur dan ditarik melawan kekuatan kotaklema yang tidak mudah menyerah, sekaligus mempertahankan peledang agar tidak terbalik oleh ombak badai. Tetapi perlawanannya begitu kuat, ditambah dengan adanya seekor kotaklema lain yang mengekor dari belakang langsung menabrak peledang kami. Dalam sekejap mata, peledang pecah terbelah dua, kami tercampak ke dalam gelombang laut yang murka. Mungkin itu jelmaan Ina Lefa.
“Apa maksud anda Jelmaan Ina Lefa?” tanya pemuda.
“Entahlah, tidak ada yang tahu, kata anak bini kesengsaraan para lamafa waktu itutampak jelas dari atas bukit batu, tetapi setelahnya hilang bagai samar menjadi satu dengan laut. Tidak ada satu pun yang terlewat, tetapi begitu saja setelah berlama-lama terpaku memandang pecahan peledang itu berubah menjadi bentuk kapal lain yang semakin menepi semakin membesar hingga mata tak bisa berkedip, ketika para bini telah berhadap dengan orang-orang pendek yang mencari para lamafa.”
“Lalu, ke mana sebenarnya anda dan para lamafa lain waktu dicampak-campakkan air laut?”
“Entahlah. Yang perlu anda tahu cukup kami sudah ada di sini!”***
* Ibunda lautan
2 Sebutan paus jenis sperma
3 Nelayan
4 Mata tombak
5 Perahu tradisional
Beri Hanna lahir di Bangko. Bergiat di Kamar Kata Karanganyar.
| Beritabaru.co menerima karya berupa cerpen dan puisi untuk dimuat di hari Sabtu dan Minggu. Silakan kirimkan karya kalian ke sastraberitabaru@gmail.com beserta biodata dan nomer rekening dalam satu file word. |


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Serdadu.id
Serdadu.id Beritautama.co
Beritautama.co kalbarsatu.id
kalbarsatu.id surau.co
surau.co





